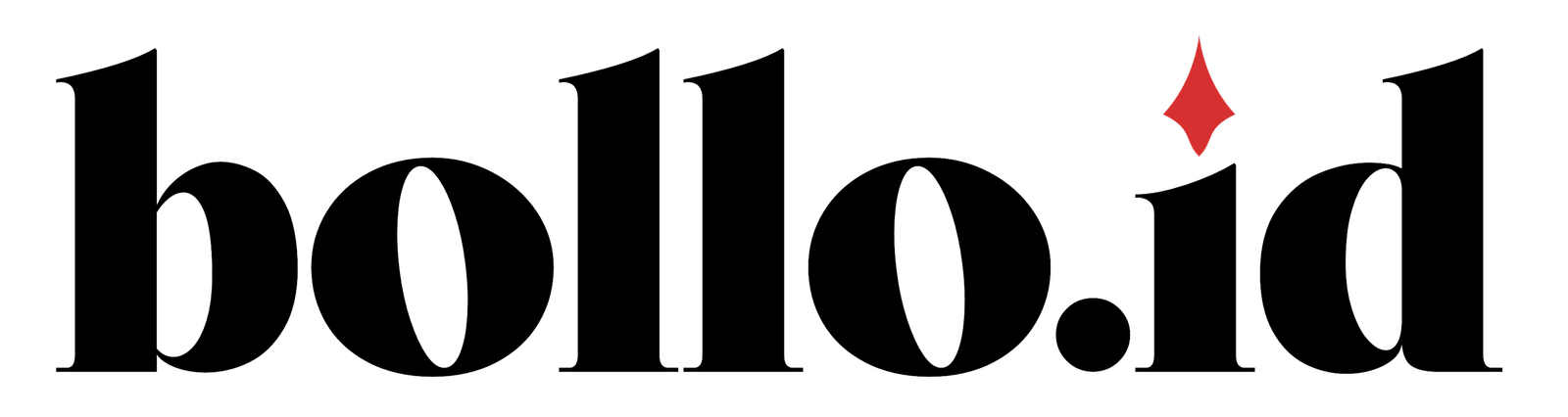PERINGATAN: Tulisan ini mengandung unsur kekerasan dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan.
Sehari sebelum ia meninggal, teman sekampusnya yang berumur lebih muda menjenguk dan melihat kondisinya yang mengenaskan. Perutnya membesar akibat luka dalam membengkak, kepala, tangan, dan kaki terlihat kecil. Ia tidur telentang di atas tikar dengan kaki terlipat; seakan-akan kita melihat bentuk tubuhnya serupa katak.
Saat si teman melongokkan kepala di muka pintu kamar, ia segera menyahut dengan nada lugas sebagaimana orang-orang telah mengenalnya, “Ko anak Mappi yang kepala batu! Ko masih saja tengok Kakak!”
“Ini Kakak mo habis, kenapa Ko datang lihat Kakak?”
“Ko bisa ikut Kakak kah tidak? Karena kau orang Papua dan bangsa sendiri, sama dengan Kakak.”
“Kakak, sa tra tahu, sa cuma datang mo lihat Kakak,” jawab temannya.
Bahkan dalam kondisi setengah mati itu, ia sadar risiko atas seseorang yang menjalin kontak dengannya. Sesungguhnya ia sudah kenyang pengucilan dan penganiayaan.
Keluarganya mencemaskan bayang-bayang pengawasan sejak ia kembali ke Merauke dalam kondisi tubuh mengeram sakit. Ia mesti dirawat di rumah sakit Katolik Bunda Pengharapan di perkampungan Kelapa Lima, sebuah daerah kelas menengah yang rimbun dan tenang, di dalam Kota Merauke.
Seseorang saat membesuknya melihat keningnya berdarah, bibir pecah, hidung, telinga, dan kaki hancur. Badannya lebam. Muka bengap. Ia sulit berjalan, dipapah dengan tongkat, dan pelan-pelan lumpuh.
Sembunyi-sembunyi, keluarganya memindahkan ia dari rumah kakak tertua ke adik terdekat—masih dalam lingkungan Kelapa Lima. Jarak rumah itu sekira lima menit dengan sepeda motor, melintasi jalan berbelok dibatasi lahan rumput dan di atasnya berdiri bangunan tembok beratap seng, menghadap muka jalan, berdempet balai kelurahan. Di situlah sekretariat Satuan Tugas Papua Barat di Merauke tempat ia pernah menyandang komandan harian manakala “Musim Semi Papua” berhembus sesudah kediktatoran Suharto tumbang.
Bangunan terbengkalai itu, setelah lebih dari sewindu, mewakili kisah senyap mengenai jejaknya, bersama rakyat Papua lain, atas ekspresi politik yang semula menemukan celah terbuka sebelum kemudian ditutup paksa dan suara kritis dicurigai dan dibungkam, kembali ke dalam era gelap kebebasan berpendapat.
Tokoh kita mengalami penyiksaan, meringkuk di penjara dan diadili. Ia didakwa makar kendati tuduhan itu tak terbukti. Ia pun dibebaskan meski riwayat penyiksaan itu terus bersemayam dalam tubuhnya.
Ia kembali disiksa, atas persoalan kampung yang remeh, dan kali ini diusir dari tempatnya menopang kehidupan keluarga.
Ia meninggal pada Kamis, 27 November 2008. Tercetak pada batang kayu salib yang tertancap di pusara: Nicolaus Yeem. Usia 37 tahun.
***
Nico Yeem, pada sebuah foto yang disimpan koleganya, mengenakan baju putih bergaris, celana katun krem dengan lipatan kecil di pinggang, tengah menyerahkan sebuah senjata rakitan di ruang sekretariat Satgas Papua, Merauke, kepada anggota militer Kodim 1707/Merauke. Mereka berdiri di sela meja kerja, di atasnya ada sebuah mesin tik, dan foto itu sendiri menandakan suatu seremoni yang tampaknya berlangsung hangat.
Pada foto lain, Yeem yang dagunya ditumbuhi cambang, sedang menandatangani surat penyerahan senjata itu kepada personil militer, duduk berhadapan di bangku kayu panjang.
Baca “Layak Dikenang” lainnya: Petani Tua dari Lereng Burangrang
Persis sesudah Presiden Suharto mundur diri pada Mei 1998, dokumentasi macam ini menjelaskan sebagian yang hilang kini di seantero Papua Barat, tujuh jam perjalanan dengan pesawat dari Jakarta, yakni angin segar kebebasan yang disebut beberapa pengamat sebagai “Musim Semi Papua,” dari pertengahan 1998 hingga November 2000. Kedatangannya secepat kegelapan yang mengurungnya.
Sebagian besar rakyat Papua menyambut kejatuhan Suharto, simbol rezim represif selama lebih dari tiga dekade, dengan sukacita dan merayakannya lewat pengibaran bendera Bintang Kejora—bintang putih tunggal berlatar merah dengan tujuh garis biru dan enam garis putih horisontal di sisinya, melambangkan jumlah distrik di Papua. Ada optimisme bahwa peluang-peluang kemerdekaan bisa dinegosiasikan dengan pemerintah Jakarta.
Harapan serupa menyebar di Timor-Leste, medan kekejaman 24 tahun pendudukan Indonesia, dan Aceh di ujung barat Indonesia yang memiliki sejarah perlawanan sengit sejak era Hindia Belanda. Timor-Leste memilih merdeka dalam proses jajak pendapat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1999. Elit Indonesia tak ingin Aceh dan Papua mengikuti jejak Timor-Leste. Pada tahun-tahun berikutnya, kedua wilayah itu tersuruk dalam operasi militer, betapa pun mereka berbeda nasib secara politik terutama setelah tsunami mengoyak Aceh pada 2004.
Cerita Papua menunjukkan satu kawasan terasing dan tertutup dari imajinasi politik masyarakat-masyarakat Indonesia. Hingga 15 tahun sejak Suharto turun, isu “Papua merdeka” ditanggapi kian sensitif oleh pemerintah Jakarta. Korban kekerasan berjatuhan terus-menerus, kadang seminggu satu, kadang dua, kadang lima; pokoknya sporadis. Polisi dan tentara Indonesia makin menambah pasukan, mengetatkan pengawasan. Jumlah tahanan politik tak pernah berkurang, bila tak terus bertambah.
Apa yang terjadi di Papua menunjukkan pendekatan Jakarta yang terus-menerus mengedepankan keamanan sebagai jalan menyelesaikan masalah.
Separuh bagian barat dari pulau New Guinea itu diklaim bagian dari negara baru Indonesia ketika pemerintahan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada 1949. Para nasionalis Indonesia menyebut rencana Belanda, yang membantu otonomi lebih besar dan luas terhadap Papua, sebagai aksi pendirian “negara boneka”. Pada 1 Desember 1961—dianggap pijakan legitimasi kemerdekaan Papua—saat dikenalkan secara resmi nama Papua Barat dan lagu “Hai Tanahku Papua” diperdengarkan serta bendera Bintang Kejora dikibarkan, segera sesudahnya presiden Sukarno menyerukan “mobilisasi” untuk infiltrasi “Irian Barat”. Dua tahun kemudian Organisasi Papua Merdeka terbentuk di Manokwari. Aksi-aksi pengibaran bendera mulai ditanggapi dengan kekerasan, termasuk lewat Operasi Sadar, operasi kontra-pemberontakan militer Indonesia perdana di Papua setahun kemudian.
Di tengah perang dingin, isu Papua menjadi masalah internasional terutama karena Amerika Serikat merasa khawatir atas langkah Sukarno yang kian dekat dengan Partai Komunis Indonesia. AS menawarkan Belanda menyerahkan Papua ke dalam skema transisi, mula-mula dari PBB lantas ke Indonesia, untuk kemudian diatur suatu plebisit untuk rakyat Papua: memilih memisahkan diri atau bergabung ke Indonesia. Namun skema ini tak melibatkan seorang pun wakil Papua.
Sukarno digantikan Mayjen Suharto dalam suatu kudeta merangkak dari akhir 1965 saat ratusan ribu orang tekait PKI dibunuh dan dipenjara, terutama di Jawa dan Bali, yang praktis membuat pemerintahan negara kepulauan ini dikelola makin sentralistik, dengan birokrasi terpusat dan ditopang represi militer. Pada 1967 Suharto mengizinkan Freeport McMoRan Copper & Gold, perusahaan tambang dari New Orleans, Amerika Serikat, mengeksplorasi Ertsberg di Papua Barat.
Pada pertengahan Juli 1969, Act of Free Choice diadakan, namun bukan lewat satu-orang satu-suara melainkan sistem perwakilan di mana sekitar 1.022 orang dari distrik Merauke, Wamena, Nabire, Fak Fak, Sorong, Manokwari, Biak, dan terakhir Jayapura, memilih bergabung ke Indonesia. Mereka berada di bawah pengawasan militer Indonesia disertai intimidasi dan kekerasan. Tak seorang pun yang memilih memisahkan diri.
Hasil itu, sering disebut “Act of No Choice”, pada akhirnya disahkan Majelis Umum PBB pada 19 November 1969, dengan 84 suara mendukung dan 30 abstain. Sebulan berikutnya Irian Barat resmi menjadi provinsi ke-26. Pada 1973 ia ganti nama Irian Jaya.
Sejak itu, seruan menggugat status politik Papua makin mengemuka terutama setelah Suharto mundur diri, dan dari 1998 para nasionalis Papua menuntut pemerintah Indonesia mengakui kecurangan historis tersebut.
***
Saya bertemu Filep Karma di penjara Abepura, Jayapura, pada awal April 2012. Bila Anda ingin memahami ekspresi politik di Papua, dari 1961 hingga periode di mana orang sering menyebutnya “reformasi” sejak Suharto turun, dan peralihan ke arah “demokrasi,” Anda perlu mendengarkan tuntutan dan penuturan perlakuan pemerintah Indonesia terhadap para “tahanan politik”, atau dalam istilah lain, “tahanan hati nurani.”
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sendiri tak menganggap orang seperti Filep Karma sebagai “tapol”, tapi murni “kriminal biasa”. Faktanya ia dipenjara karena dituduh “makar”—suatu pidana yang mengandung motif politik.
Karma dihukum penjara 15 tahun sejak 2005 karena mengadakan demonstrasi damai menolak otonomi khusus pada 1 Desember 2004. Ini kali kedua ia masuk bui setelah pada 6 Juli 1998, dalam aksi pengibaran bendera Bintang Kejora yang berakhir kekerasan di Biak, sebuah pulau dengan lanskap yang indah, ia didakwa tuduhan serupa, dihukum enam setengah tahun tapi kemudian bebas dalam sidang banding pada 1999. Sejumlah rujukan atas riwayat kekerasan di Papua menyebut peristiwa itu sebagai “Biak Berdarah.” Itu juga salah satu kekerasan paling mencolok di Papua pasca-Suharto.
(Catatan editor: Filep Karma, meninggal pada 1 November 2022)
Di Jakarta, di mana B.J Habibie diserahkan jabatan presiden sementara, suatu delegasi dari pemuka sipil Papua, yang menamakan diri Tim 100, diterima pada 26 Februari 1999 untuk membahas masa depan Papua, termasuk opsi kemerdekaan. Kendati terkejut, Habibie lebih memilih opsi pemisahan administratif provinsi guna mencegah pemisahan diri. Habibie berkata, “Aspirasi yang kalian bawa itu penting, tapi mendirikan sebuah negara tidak lah mudah…” Ia minta mereka memikirkan ulang dan pulang ke Papua untuk mengatur apa yang disebut “dialog nasional”.
Habibie digantikan Abdurrahman Wahid, tokoh muslim dari Nahdlatul Ulama, pada Oktober 1999 sesudah Indonesia menggelar pemilihan umum pertama pascaorde baru. Wahid segera mengambil posisi yang mengedepankan dialog terhadap Papua. Pada akhir tahun ia mengunjungi Jayapura sebagai lawatan simbolik menyongsong fajar baru abad ke-21 sekaligus mengusulkan nama “Papua” untuk provinsi yang selayaknya disebut demikian.
“Nama inilah yang hendaknya dipergunakan seterusnya…,” ujar Wahid yang disambut hangat rakyat Papua pada malam menjelang pergantian tahun.
Pada 23-26 Februari 2000, ratusan pemuka Papua menggelar “Musyawarah Besar” di Sentani, Jayapura, dan memutuskan pembentukan lembaga eksekutif mandiri, dikenal Presidium Dewan Papua, yang diberi mandat menggelar Kongres Rakyat Papua II. Kongres pertama dianggap telah diadakan saat era pemerintahan Belanda pada 1961. Hasil kongres kedua, digelar 29 Mei – 4 Juni, menyatakan rakyat Papua telah siap sebagai bangsa berdaulat dan negara-negara yang terlibat dalam “Act of Free Choice”—AS, Belanda, dan Indonesia—harus mengakui hak politik bangsa Papua. Ia juga memilih Theys Hiyo Eluay (kepala adat suku Sentani) sebagai ketua Presidium dan Tom Beanal (kepala adat suku Amungme, lokasi tambang Freeport di Timika) sebagai wakil—bisa dibilang mewakili daerah pantai dan pegunungan Papua.
Presidium bertugas menuntut referendum, atau upaya-upaya dialog secara damai dengan pemerintah Jakarta, yang bertujuan meraih kemerdekaan. Ia beranggotakan 24 orang, mewakili apa yang disebut “sembilan pilar”, meliputi pilar agama, adat, profesi, mahasiswa, perempuan, pemuda, tahanan politik, pelaku sejarah, dan jaringan internasional, yang membentuk “dewan panel” di tiap-tiap distrik.
Wahid tak hanya menyetujui dilangsungkan Kongres, dan mengizinkan pengibaran Bintang Kejora asalkan berdampingan dan ditempatkan lebih rendah dari bendera Indonesia, tapi ia juga memberi bantuan dana dari anggaran pemerintah sebesar Rp 1 milyar untuk acara Kongres. Dukungannya, dalam derajat tertentu, untuk mengedepankan kebijakan kemanusiaan terhadap Papua, yang disambut hangat rakyat Papua, justru ditentang para elit politik di Jakarta. Gambaran buruknya, menjelang akhir tahun, Jakarta mengirimkan lebih dari 3.000 pasukan Brigade Mobil dan prajurit Kostrad ke Papua.
Para birokrat dari rezim lama memiliki pandangan berbeda atas Papua. Segera setelah Kongres, sebuah pertemuan tertutup yang terungkap ke publik antara Bakin, Bais, Kostrad, dan Kopassus merancang suatu operasi yang memberangus para pendukung kemerdekaan, termasuk pemimpin terkemuka, pegawai pemerintah, akademisi, dan politisi. Ia juga menyusun operasi militer, termasuk merekrut, melatih, dan mendanai milisi-milisi pro-Indonesia. Dalihnya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di masing-masing distrik guna mendukung rencana otonomi khusus.
Satgas Papua, sebagian besar dari kalangan anak muda, segera bertugas mengamankan pertemuan-pertemuan politik sepulang Tim 100 dari Jakarta. Mereka menjaga rumah Theys Eluay di mana ketua Satgas sendiri adalah anaknya. Dengan seragam hitam dan lencana Bintang Kejora, anak-anak muda ini berjaga-jaga dalam acara Musyawarah Besar dan Kongres Rakyat Papua II, yang segera diakui sebagai salah satu pilar Presidium. Ia berubah jadi jejaring sayap pemuda dari semula perkumpulan cair di tengah orientasi perjuangan rakyat Papua. Mereka mendirikan posko-posko di nyaris seluruh distrik.
Lawannya, milisi Merah Putih bentukan militer Indonesia, sengaja dibikin untuk menggalang dukungan pro-Indonesia, diduga pula untuk menciptakan kondisi Papua terus tegang hingga ada dalih tindakan keras oleh aparat keamanan Indonesia. Tujuannya membendung arus pro-kemerdekaan.
Pada Maret 2000, bersama pasukan Kostrad dan regu Brimob, milisi Merah Putih melakukan kekerasan di sebuah kampung di Fak Fak, sebuah distrik yang didominasi Muslim. Pada April, Kodim1702/Jayawijaya membentuk milisi serupa di Wamena dengan merekrut 80 warga sipil. Para aktivis hak asasi manusia di Papua khawatir situasinya akan seperti Timor-Leste pascareferendum 1999.
Di sisi lain, sejak Satgas Papua terbentuk (ada yang menyebut 7.000 hingga 10.000 anggotanya hingga medio 2000), muncul kecemasan di antara kalangan intelektual Papua bahwa ia justru akan jadi duri dalam daging di tengah gerakan pro-kemerdekaan. Belakangan terungkap kabar, sayap pemuda Golkar, Pemuda Pancasila, diduga memiliki hubungan dengan Satgas Papua lewat wakil ketua Yorrys Raweyai, yang dekat dengan Theys Eluay. Eluay adalah politisi parlemen daerah dari Partai Golkar selama lima belas tahun yang berbalik mendukung kemerdekaan sesudah 1998. Raweyai, yang juga ikut dalam Tim 100, dikenal dekat dengan keluarga Suharto lewat sayap paramiliter Pemuda Pancasila. Dalam beberapa peristiwa, anggota-anggota Satgas mulai lakukan pemerasan terhadap pedagang non-Papua.
Sesudah Kongres, Letjen Agus Wirahadikusumah—salah satu dari sedikit perwira yang dianggap reformis—saat itu menjabat panglima Kostrad, menyerukan Satgas dibubarkan dan menangkap anggota-anggota yang melakukan pemalakan. Namun perintahnya tak dituruti.
Seruan dari kalangan internal Papua bahwa Satgas perlu direstrukturisasi tampaknya jadi perkara waktu karena, bahkan sebelum harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan rakyat Papua membesar, gelembung itu pecah di Wamena pada 6 Oktober 2000.
Beberapa jam berikutnya kekerasan menyebar ke Wouma, sebelah selatan Wamena, di mana kerumunan orang Papua membakar dan menjarah pertokoan. Aparat Indonesia dikerahkan dan mulai menembakkan peluru dari kampung transmigran. Itu dibalas serangan terhadap rumah-rumah penduduk transmigran, membunuh 24 orang non-Papua dan sedikitnya tujuh orang Papua tewas tertembak. Sesudah kejadian, 22 orang Papua ditangkap.
Itu adalah titik balik. Polisi menyerukan penduduk transmigran untuk mempersenjatai diri dan melakukan patroli kampung. Seorang perempuan non-Papua diperkosa dan kepalanya dipancung. Ini sengaja menciptakan narasi keji yang menargetkan pelakunya nasionalis Papua bahwa mereka kejam dan biadab; aksi sadis macam itu justru paling sering dipakai tentara Indonesia guna membentuk opini buruk dan memobilisasi kemarahan. Di Jayapura, polisi mewanti-wanti jika kekerasan berlanjut, mereka takkan dapat mencegah Laskar Jihad memasuki ibukota Papua.
Lima hari kemudian, di Jakarta, Wakil Presiden Megawati dan Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan Letjen Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan kebijakan untuk membungkam gerakan kemerdekaan, termasuk melarang bendera Bintang Kejora. Ia juga mendesak penyelidikan terhadap peranan Presidium dan Satuan Tugas Papua atas peristiwa itu. Menjelang akhir tahun, Theys Eluay dan empat pemimpin Presidium lain ditahan dengan tuduhan makar.
Antara 1998 hingga 2000, menurut sebuah laporan, sekurang-kurangnya terjadi 80 kasus bergaya eksekusi dan 500 kasus penanahan dan penyiksaan sewenang-wenang terhadap individu Papua oleh pemerintah maupun militer dan polisi Indonesia.
Musim semi Papua berganti musim penyiksaan.
***
Pada 4 November 2000, bulan di mana presiden Abdurrahman Wahid menghadapi perangkap parlemen di Jakarta, di Kota Merauke, terletak di pantai selatan Papua, dua warga tewas tertembak oleh regu Brimob. Kejadian pertama di pintu air Natuna, dekat pelabuhan, korbannya Adam Baits. Yang kedua Robertus Waimu, anak muda yang baru lulus SMA, di jalan Ampera.
Nicolaus Yeem, yang kembali ke Merauke pada 1998 setelah enam bulan bekerja sebagai navigator pelayaran di pantai Etna, Fak Fak, tampaknya pemuda 27 tahun yang biasa saja dan mulai sadar politik setahun kemudian, menurut kakak sulungnya. Ia kecil ikut pamannya dari pihak papa di kampung Kweel, dekat perbatasan Papua New Guinea, dan ikut bibinya dari pihak mama di Mindiptana, Boven Digoel, sebelum kemudian balik ke Merauke untuk sekolah teknik mesin. Pada 1995, ia pergi ke Yogyakarta untuk kuliah pastur tapi merasa tak cocok lalu pindah sekolah tinggi ilmu pelayaran untuk mendalami navigasi mesin dan radio kapal.
Orangtuanya dari suku Muyu, salah satu dari 17 suku di Merauke yang banyak dijumpai di sepanjang perbatasan, sementara di distrik Merauke sendiri, yang suku tradisionalnya adalah Malind Anim, berkat migrasi pekerjaan dan pendidikan missionaris Belanda, kelompok itu terkonsentrasi di kampung Kelapa Lima.
Suku Muyu seringkali dicap sebagai pemberontak, dan salah satu kelompok paling menderita selama operasi militer di seantero Papua pada 1980-an. Operasi itu untuk membongkar seluruh jaringan simpatisan Organisasi Papua Merdeka di lingkungan kampus hingga instansi pemerintah, termasuk pembunuhan terhadap antropolog Arnold Ap dari Universitas Cenderawasih, Jayapura. Imbasnya, pada 1984-1986, puluhan ribu orang Papua terpaksa menyeberangi perbatasan PNG, termasuk orang Muyu dari sebagian besar 9.435 pengungsi di selatan Papua. Tahun-tahun itu juga pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan transmigrasi ke Papua. Stigma pemberontak terhadap orang Muyu acapkali dijadikan dalih penangkapan, satu hal yang akan dialami Nico Yeem.
Begitulah, saat Yeem menyandang komandan harian Satgas di Merauke, kini seorang yang ditinggal kematian istri dan anaknya dalam dua tahun terakhir, sesudah ada penembakan pada awal November, Yeem minta anak buahnya menuruti permintaan otoritas kepolisian Indonesia di Merauke agar tak mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember.
Kakak iparnya (mengenang Yeem sebagai “orang yang pertama menyatakan kepadanya Indonesia sebagai penjajah” pada 1999 di Polres Merauke) mengingat perintah Yeem bahwa “kita tra usah upacara.”
Kata Yeem, “Jangan sampai konflik. Biar sudah. Tidak untuk kalah. Mengalah untuk baik.”
“Kita boleh lawan, tapi kita trada bawa barang itu (senapan). Kita tenang untuk baik,” kata Yeem.
Sebagaimana terdokumentasikan dalam foto, para anggota Satgas meyakini tentara dari Kodim 1707/Merauke bermain dalam senjata rakitan ke tangan penduduk transmigran di distrik Kurik. Senjata itu ditemukan anggota Satgas yang kemudian diserahkan ke personil Kodim. Ini taktik militer Indonesia untuk menyulut kerusuhan antara warga non-Papua dan Satgas Papua.
Yeem bilang, jika tak mau dengar perintahnya, ia lebih memilih pulang untuk cari makan, “Perjuangan kita harus ada uang.”
Pada 28 November, Yeem memutuskan pergi ke kampung Kweel di distrik Elikobel, sekira 172 kilometer dari distrik Merauke. Akhir tahun itu dikenal musim ikan kaloso atau arwana, biasa dibeli Yeem seharga Rp 15.000 per ekor lantas dijual kembali ke Kota Merauke dengan ambil keuntungan Rp 5.000.
Pada Jumat, 1 Desember, memang tak ada perayaan upacara, tapi justru terjadi esoknya; berbuntut kekerasan.
Pada Jumat malam, saat kumpul di Kuda Mati, kakak ipar Yeem memberi saran pada anggota Satgas agar mereka mengurungkan perayaan itu. Teorinya, Papua cuma mengenal 1 Desember sebagai hari bersejarah, bukan hari yang lain. “Kalau ada kegiatan tanggal 2 (Desember), siapa yang bermain?!”
Sulit menduga siapa yang mengatur peringatan itu. Namun pada pagi hari Sabtu, sebagaimana bertahun-tahun kemudian diceritakan seorang saksimata, rombongan orang Papua telah berkumpul di bundaran simpang empat di dekat masjid raya. Itu sebuah titik yang menghubungkan jalan Brawijaya, jalan Parakomando, jalan Trikora, dan sebuah jalan menuju kampung Kelapa Lima. Di tengah bundaran itu terpacak sebuah tugu “Maroka Eke”.
Rombongan menyusuri jalan Trikora, melewati pasar induk Ampera, kini pasar lama, menyanyi “Hai Tanahku Papua” dari sebuah tape besar dan megaphone ditenteng seorang demonstran. Dari sekelompok kecil menjadi besar, mereka putar kota ke arah pelabuhan, melintasi regu marinir dilengkapi senapan yang tengah berjejer di depan pangkalan Angkatan Laut Indonesia. Mereka berseru seraya mengangkat tangan: “Adil dan merdeka!”
Mereka lantas berbelok ke jalan raya Mandala, sebuah jalan utama yang menghubungkan bandara dan pelabuhan. Tiba di polres, kini pos polantas, mereka dihalangi kawat duri sepanjang 2 meter, yang lantas mereka terjang, membuka pintu sel, membebaskan para tahanan kriminal. Suara tembakan menggema di tengah kekacauan. Seorang demonstran kena tembak pada lambung kanan. Rombongan membiarkannya dan terus bergerak menuju kota. Sasarannya kantor bupati.
Di tengah jalan, mereka menurunkan bendera Merah-Putih di dua kantor pemerintah. Setiba di kantor bupati, mereka menaikkan bendera Bintang Kejora. Itu sekitar pukul 09:00, terjadi negosiasi, bendera diturunkan tigapuluh menit kemudian. Di sana polisi dan tentara telah berjaga-jaga. Ada dua truk kompi. Pecah kekerasan.
Sebagian rombongan, yang mempersenjatai diri dengan panah, lantas baku lempar dengan aparat Indonesia. Sebagian lagi memaksa masuk ke kantor parlemen daerah, di depan kantor bupati, merusak jendela dan atap seng. Mereka menyingkir ke puskesmas, mengatur jalan selanjutnya. Sebuah pick-up polisi terlihat didorong hingga terbalik.
Rombongan berlari kembali ke bundaran. Polisi terus menyerang. Sebagian orang memasuki toko, mengambil benda-benda yang ada di sekitarnya, melemparnya ke arah sumber tembakan. Demonstran membubarkan diri setiba di pasar Ampera. Sebagian besar pulang ke Kelapa Lima. Pawai itu berakhir sekira jam 4 sore.
Sekurangnya sepuluh orang tewas, termasuk seorang transmigran yang terjebak di tengah pawai, dan lusinan lain terluka.
Hingga tiga hari berikutnya, aparat gabungan menyisir perkampungan, terutama di Kelapa Lima, membongkar posko-posko Satgas di jalan, menyebabkan banyak anak muda dan para suami menyelamatkan diri ke daerah berawa di Tanjung Bupul, Matanding.
Sebagian besar tinggal di sana selama seminggu hingga ada negosiasi lewat perantara perwakilan pendeta Katolik. Terutama para anggota Satgas minta jaminan tak ditangkap sekembali mereka ke rumah.
Kapolres Merauke, Yohanes Agus Mulyono, yang melakukan negosiasi itu bersama bupati Merauke, Johanes Gluba Gebze, berjanji takkan tangkap mereka.
Namun, pada 11 Januari 2001, Nicolaus Yeem dijemput dari Kampung Kweel dan disiksa.
Sebuah unit gabungan dari polisi brigade mobil dan personil TNI dari Komando Pasukan Khusus, Kodim 1707/Merauke, dan Yonif Linud 431/SSP, menangkap Yeem di sungai Palda, kampung Kweel, sekira jam 6 sore. Mereka menggunakan delapan kendaraan hardtop dan enam sepeda motor Yamaha RX-King. Sepanjang jalan, mereka menyiksa Yeem.
Di pos polsek Erambu, distrik Sota, sekira 150 km dari distrik Merauke, iring-iringan itu berhenti.
Yeem dipukul dengan popor senjata, badannya disundut puntung rokok dan diludahi. Dengan tubuh telungkup, ia diinjak ke dalam genangan lumpur, ditindis dengan kayu balok di atas tulang belakang, sampai-sampai nafasnya sesak lumpur.
Sebuah pistol tanpa peluru dimasukkan ke dalam mulutnya dan dikutik hingga tiga kali.
Sembari menyiksa, mereka mencelanya: “Kau mau merdeka? Papua mau merdeka? Kau lawan orang Indonesia seluruhnya! Kau minum pasukan punya air kencing dulu…”
Esoknya, pukul 08:00, mereka tiba di distrik Merauke, dan segera menjebloskan Yeem ke sel polres Merauke. Ia meringkuk di sana hingga empat bulan di mana hukum di Indonesia hanya boleh menahan warga negara selama 21 hari plus perpanjangan 6 hari. Otoritas Indonesia di Merauke menuduh Yeem melakukan “makar.”
Kakak sulung Yeem, pada saat kejadian berada di Kweel untuk merayakan Natal dan tahun baru, segera mendengar dari ibu angkatnya, yang turun ke Merauke untuk cari kepastian, akhirnya mengetahui dari kabar Mama Yeem, “Adik su di sel Polres, Mama diusir oleh polisi di Polres.”
Mama Yeem, bagaimanapun, sesudah dibohongi (dibilang “ko pu anak lari ke hutan”; “punya anak bikin kacau”) akhirnya diterima untuk melihat keadaan Nico.
Kakak Yeem rutin membesuk, tiga kali dalam seminggu. Ia melihat jari kelingking kanan Yeem remuk.
Yeem tak menerima perlakuan terhadap dirinya, yang sempat dilarang bertemu keluarga, “Saya bukan pengacau, saya bukan perusak.”
“Kamu yang datang yang bikin kacau. Ko pu tempat di mana? Ko pu leluhur di mana?”
“Dia mengamuk sekali,” kata kakaknya kepada saya.
Jumat Agung pada bulan April, kakaknya mencari jalan untuk membebaskan Yeem. Ia mendatangi rumah ketua pengadilan.
“Ibu ada perlu kah?”
“Saya perlu. Saya warga negara Indonesia yang tidak mengerti aturan hukum negara Indonesia.”
“Maksud Ibu bagaimana?”
“Adik saya masuk sel, sudah lewat 21 hari, itu bagaimana?”
“Itu ada aturan, itu nanti ada tahanan jaksa, masuk ke LP.”
“Ibu pu adik masalah apa?”
“Saya pu adik tuntut hak sebagai orang Papua. Dia ditangkap dan ditahan di sel dengan tuduhan makar.”
“Apakah Ibu pu adik menurut Ibu benar?”
“Ya, benar.”
Pada bulan Mei, Yeem berada di bawah kewenangan Jaksa, dimasukkan ke lapas Merauke di bilangan Ermasu.
Dua bulan berikutnya, bulan di mana Abdurrahman Wahid menghadapi tekanan besar dari parlemen nun sejauh 3.732 kilometer di Jakarta, Yeem dibawa ke pengadilan. Tanpa saksi yang dibawa ke persidangan, selama sebulan setiap hari Rabu, Yeem diusut perkaranya. Pengadilan memutuskannya bebas pada 25 Juli, satu hal yang mengandung kecurigaan bahwa dakwaan yang dibebankan kepadanya hanyalah upaya meretas penyiksaan. Dua hari sebelumnya, di Jakarta, jabatan Wahid dicopot dan digantikan Megawati.
***
Perkembangan resolusi politik untuk Papua mulai jelas tapi pelan-pelan dramatis. Megawati menyetujui otonomi khusus untuk Papua segera setelah ia menjabat presiden. Dua tahun berikutnya, Januari 2003, ia mengeluarkan keputusan presiden yang mengesahkan pembagian provinsi baru, bernama Papua Barat dengan ibukota Manokwari, dan tiga kabupaten (Paniai, Mimika, dan Puncak Jaya), serta sebuah kotamadya (Sorong).
Elit politik Papua begitu terpecah, terutama dari semula tuntutan “merdeka” di tengah euforia dalam era apa yang disebut reformasi, belakangan jadi sekadar “otonomi khusus”— dinilai pengamat sebagai satu perubahan yang terlalu kompromis. Otonomi juga mengatur pembentukan majelis tinggi mandiri, bernama Majelis Rakyat Papua, yang mengakomodasi orang Papua untuk menduduki jabatan itu. Dalam perkembangannya, ia diletakkan sebatas peran simbolis. Pada 2002, Dewan Adat Papua terbentuk, tujuannya melindungi masyarakt asli Papua, yang idenya mengacu pada struktur tujuh pemerintahan adat era pemerintahan Belanda. Ada sejumlah faksi, dan di dalamnya muncul konflik dan persatuan, di tengah gerakan kemerdekaan Papua dalam tahun-tahun berikutnya.
Pada September 2001, dua bulan setelah Yeem dibebaskan pengadilan, Willem Onde—dianggap pimpinan Organisasi Papua Merdeka di Merauke—ditemukan tewas; jasadnya mengapung di Kali Maro. Pada 11 November, dalam apa yang diyakini banyak kalangan sebagai operasi terencana, Theys Hiyo Eluay dibunuh prajurit Kopassus.
Apa yang terjadi pada Yeem?
Ia kembali ke kampung Kweel. Menjalani rutinitasnya sebagai penjual ikan arwana. Seakan-akan ia menolak tunduk pada penyiksaan yang dialaminya, atau sesungguhnya kehidupan terlalu besar untuk dikendalikan oleh penderitaan.
Namun, bagaimanapun, pada November, ia sekali lagi menerima penyiksaan.
Itu lebih pada perkara remeh. Tapi stigma terhadap dirinya sebagai orang Muyu telah mengukurnya sebagai objek kekerasan. Itu juga disemai provokasi oleh personil Yonif 733/ Pattimura, kesatuan dari Kostrad yang diterjunkan untuk menjaga pos-pos perbatasan, yang menuduhnya telah menjual harga ikan Arwana terlalu mahal: Rp 25.000 di distrik Merauke dari harga yang dibeli Rp 10.000 di Kweel.
Seorang warga mencela Yeem sebagai “pengacau, separatis, OPM.”
“Orang Muyu tipu-tipu,” katanya.
Yeem tak terima tuduhan itu, lalu membalas dengan memukulnya.
Warga setempat berbondong-bondong menghajarnya—dengan kapak, parang, kayu, senter, radio—sambil menggelandangnya menuju kantor pos tentara terdekat sejauh 9 km, dari jam 11 malam hingga 3 pagi. Di sana dua tentara Yonif 733 menyambutnya dengan popor senjata yang menukik tulang belakang, dan menendang lambung kirinya berkali-kali. Yeem diikat di bawah tiang bendera Merah Putih, dari pagi hingga siang. Ia juga diminta bayar ganti rugi Rp 1 juta; setengah untuk warga setempat yang dipukulnya, setengah lagi untuk tentara. Yeem melunasinya.
Namun, dalam tahun-tahun berikutnya, kehidupan Yeem tampaknya berjalan tenang.
Ia menikah lagi dengan perempuan dari suku Yeinan, sub-suku Marind, yang bermukim di hulu Kali Maro pada 2002. Dalam dua tahun kemudian, mereka memiliki dua anak, seorang lak-laki dan seorang perempuan. Pada Mei 2007, anak ketiganya yang perempuan lahir. Namun, pada bulan berikutnya, Mama dia meninggal. Usia Yeem saat itu 36 tahun.
Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal “Merauke” dari sebuah lagu “Dari Sabang sampai Merauke”, yang diperkenalkan saat sekolah dasar, suatu kontak pertama usia anak Indonesia dengan negara, sebagai apa yang disebut “lagu nasional.” Liriknya, Indonesia terdiri pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke, tapi merupakan satu kesatuan.
Di Merauke, hamparan dataran rawa yang ditumbuhi pohon kayu putih dan gambir, jalan berlubang yang menghubungkan satu distrik dengan distrik lain, boleh jadi Anda akan menemukan kebosanan. Namun di sini lah, di ujung timur Indonesia, proyek-proyek dari Jakarta terhubung dalam bentuknya yang pelik, dan seringkali lewat jalan kekerasan. Dampaknya terlalu kontras antara penduduk transmigran dan penduduk Papua.
Sebuah studi 2011 memproyeksikan, bila populasi Papua sebesar 1.760.557 terus meningkat dengan rerata tahunan 1,84%, maka orang Papua akan berjumlah 2.112.681 pada 2020. Sebaliknya, jika penduduk non-Papua selalu bertambah pada rerata stabil 10,82%, maka ia akan berjumlah 5.174.782. Itu akan memberi prediksi populasi orang Papua 28,99% dan non-Papua 71,01% pada 2020. Ada yang menyebutnya sebagai “slow-motion genocide.”
Pada April 2012, saya bertemu dengan mama-mama penjual kepiting dan kangkung di sepanjang jalan Ermasu. Saya mengikuti kegiatan seorang mama dari suku Auyu, di mana keponakannya ditembak mati di bagian bahu oleh regu Brimob pada 4 November 2000. Itulah Robertus Waimu.
Mama cerita, saat mendengar kejadian itu, ia segera mencari Waimu, yang telah dibawa ke sebuah rumah pamannya. Di sanalah, pada jam 6 sore, ia mendekap jasad Waimu yang bersimbah darah, memangku kepalanya.
Ia menuntun saya ke titik jalan di mana 12 tahun lalu darah Waimu tergenang.
“Mengapa ditembak?” tanya saya.
“Mama tak tahu. Dia anak muda yang pintar bahasa Inggris. Bila ada tamu wartawan yang datang ke Merauke, dia yang antar wartawan itu, bicara dengan penduduk Papua.”
“Mungkin karena itu…” ujar Mama.
Papa Waimu, yang tinggal di Boven Digoel, datang sebentar ke makam anaknya pada 2003. “Dong sakit hati kenapa trada yang tangggungjawab anaknya ditembak? Pelaku tra ditangkap?” ujar Mama. “Dia berjanji tra akan turun ke Merauke.”
Setiap tahun saat Jumat Agung, Mama tabur bunga dan bakar lilin di tempat tubuh ponakannya ditembak.
Di Merauke, daerah yang sebagian besar dari masyarakat Indonesia tak pernah melihatnya, menjadi mungkin dilihat karena paksaan. Di daerah Tanah Miring, suatu kampung transmigran, terdapat Monumen Benny Moerdani. Itu suatu peringatan, atau situs pengagungan, atas apa yang dijalankan Kapten Moerdani pada Juni 1962 saat memimpin pasukan payung untuk menggagalkan rencana pendirian negara Papua. Kenyataan lain, bila Anda berjalan menuju pelabuhan di pusat Kota Merauke, di situlah anda tengah melewati jalan Sabang.
Saya bertemu dengan keluarga Yeem di kampung Kelapa Lima dan bicara dengan kakaknya. Saat menyinggung aktivitas politik Yeem sebagai komandan Satgas, ia segera menyahut, “Satgas bukan milisi. Dia pu satuan tugas yang mempertahankan bendera Bintang Kejora, tuntut hak untuk pengembalian kedaulatan politik bangsa Papua. Bukan pengacau, bukan teroris, bukan milisi.”
Bagaimanapun, dalam banyak kejadian kekerasan, tentara-tentara Indonesia acapkali tak mengenal apakah anda penggiat politik atau warga Papua biasa. Pada Juni 2009, muncul laporan yang menguraikan para personil Kopassus di Merauke melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak muda Papua, sebagian besar karena persoalan kriminal biasa, atau dalam kamus hukum Indonesia dianggap “mengganggu ketertiban umum”—yang definisinya terlalu samar dan seturut otoritas setempat. Di Kelapa Lima, warga mengenal Kopassus dari sebuah rumah sewa di jalan Doom bertuliskan “Mess Kopassus.” Mereka muncul sejak 2006.
Jumlah aparat keamanan Indonesia di seluruh Papua, dalam suatu studi, meningkat pada dekade terakhir. Taksirannya seorang polisi atau tentara mengawasi 97 warga sipil. Itu satu perbandingan yang jauh melampaui seluruh kawasan lain di Indonesia di mana 296 warga sipil diawasi seorang tentara atau polisi. Sebagaimana Indonesia mengesahkan pemekaran di sebagian besar kawasan Papua, dari kabupaten hingga provinsi, jumlah satuan teritorial militer dan pos polisi juga ikut bertambah. Militer Indonesia, terutama Angkatan Darat, mengukur Papua dengan garis mistar keamanan sebagai operasi perbatasan dan pemberontakan, serta “aset vital nasional”. Polisi bertugas memantau dan meringkus aksi ekspresi politis. Di sisi lain, elit politik Papua juga melobi Jakarta untuk membentuk provinsi baru di sebelah selatan Papua.
Pada 2007, Presiden Yudhoyono mengenalkan megaproyek pembangunan pertanian dan perkebunan, dikenal “Merauke Integrate Food Energy Estate,” memetakan dataran Merauke sebagai lumbung pangan yang akan “memberi makan rakyat Indonesia, kemudian dunia.”
Lahan yang dikenalkan pada 2010 dibuka seluas 1,28 juta hektar, dua kali luas pulau Bali, 90 persen masih hutan alami yang belum pernah ditebang. Proyek itu didukung 32 investor, sebagian besar dari pengusaha Jakarta. Dalam perkembangannya, peta luas lahan itu selalu mengalami revisi. Para aktivis adat dan lingkungan mengkhawatirkan megaproyek itu akan merampas tanah adat, mendatangkan puluhan ribu buruh non-Papua, yang gilirannya mengusir masyarakat adat di sana.
Sekurang-kurangnya, tim peneliti pemerintah Indonesia membahas persoalan di Papua. Ada empat soal, tulisnya, “marjinalisasi dan diskriminasi; status sejarah dan politik; kegagalan pembangunan; dan kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia.” Mereka menjelaskan empat soal itu ke dalam diagram yang mereka sebut “Papua Road Map.” Titik magnetnya, soal-soal itu diselesaikan untuk meraih “Papua Baru.”
Namun, yang lebih terlihat adalah bentuk kekerasan baru.
Pada akhir 2011, Kongres Rakyat Papua III di Abepura dibubarkan aparat keamanan Indonesia setelah Kongres berjalan tiga hari. Lebih dari 300 orang ditangkap, tiga orang Papua tewas, dan 90 lain luka. Enam aktivis Papua diadili dengan dakwaan “makar.” Ini menambah daftar panjang tahanan politik Papua di bawah pemerintahan Yudhoyono.
Saya bertemu Edison Waromi di Lapas Abepura sebulan setelah vonis tiga tahun penjara terkait kongres itu, April 2012. Menurut istrinya, jika dihitung-hitung, “Bapak menghabiskan waktu di tahanan selama 19 tahun.” Waromi menjalani kehidupan pertama di balik jeruji selama 10 tahun di Kalisosok, Surabaya, pada dasawarsa terakhir rezim Suharto. Putri mereka pernah diculik dan disiksa pada 2007 di Jayapura terkait kegiatan politik papanya.
“Apa yang dipilih Papua, dong pilih maut satu keluarga,” ujar istri Waromi. “Dong” maksudnya otoritas Indonesia, militer maupun polisi, yang sering melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil Papua.
Bagaimana meretas upaya jalan “Papua Baru” bila kekerasan-kekerasan tetap terjadi, bila postur keamanan terus bertambah?
Pemerintahan Yudhoyono, sebagaimana yang ia lakukan saat menjabat presiden 2004 dengan menegaskan penerapan otonomi khusus, memilih opsi “pembangunan” untuk persoalan Papua, dan pada 2011, ia membentuk sebuah unit kerja yang “mempercepat” pembangunan tersebut. Ia memilih kepala tim tersebut dari seorang perwira yang punya sejarah buruk dalam kekerasan di Aceh.
Yudhoyono enggan mendengarkan daftar rekomendasi, yang dibuat setahun sebelumnya oleh anggota-anggota Majelis Rakyat Papua di Jayapura, salah satunya menolak otonomi khusus dan menyuarakan referendum untuk Papua; satu peristiwa terbuka yang mengingatkan pada euforia 1998 saat rakyat Papua berani bicara “merdeka” sebelum mereka dirangkum dalam riwayat penangkapan, penyiksaan, pemenjaraan, dan pembunuhan pada tahun-tahun sesudahnya.
Pada 14 Februari 2012, saat tim kerja baru itu melakukan “sosialisasi” di lokasi transmigrasi di Distrik Semangga di Merauke, kakak Yeem—seorang aktivis perempuan yang bicara lantang—langsung menolaknya.
“Kita tidak bicara otonomi khusus,” katanya. “Kembali ke sejarah. Kami bangsa lain. Setiap bangsa yang ada di muka bumi ini, dia pu hak merdeka.”
Namun, di kalangan gerakan kemerdekaan Papua sendiri sering sekali terjadi konflik, sesama generasi dan antar-generasi dari 1963 hingga kini, yang menunjukkan lemahnya persatuan internal. Seorang pemimpin kharismatik seperti Theys Eluay dianggap kolaborator, kendati pembunuhan terhadap dirinya mengikis kesan buruk itu dan tak diragukan lagi menjadikannya pahlawan rakyat Papua. Di sisi lain, sebagian individu yang dulunya menyuarakan kemerdekaan malah berbalik mendukung Indonesia, memberi peluang kampanye negatif bahwa perjuangan Papua mudah “dibeli”. Sebagian lain juga menolak bekerjasama dengan individu dan masyarakat sipil Indonesia, yang dengan tulus bekerja untuk hak asasi manusia di Papua. Peran perempuan dalam perjuangan ini juga sering diabaikan.
Di tengah arus pemekaran, elit politik Papua mendapatkan keuntungan istimewa berkat otonomi khusus, yang lebih memilih seorang administrator dari satu suku, satu fam, yang gilirannya menyuburkan praktik korupsi. Papua juga menghadapi isu kesehatan HIV/AIDS tertinggi di Indonesia di mana sekitar 30.000 orang, menurut laporan 2012, diperkirakan hidup dengan HIV.
Saya mendatangi “mama-mama pasar” di kota Jayapura, 1,5 jam dengan pesawat dari Merauke, untuk melihat inisiatif sekelompok orang mendirikan “koperasi mama-mama pedagang asli Papua.” Sebuah tenda putih besar memayungi para pedagang di suatu areal lapang, menjual macam-macam sayuran dan ikan, dijajakan di atas meja papan atau di atas tikar karung.
Seorang penggiat di sana mengeluhkan soal lemahnya “kemandirian ekonomi” dan tingginya “diskriminasi ekonomi” terhadap mama-mama Papua. Cukup banyak juga cerita kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan Papua.
“Bagaimana mau merdeka kalau ekonominya saja lemah?” tuturnya.
***
Nicolaus Yeem menjalani aktivitas pulang-pergi dari distrik Merauke ke kampung Kweel di perbatasan. Perjalanan itu, dengan jalan becek, berlumpur, bergelombang, ia lintasi dengan sepedamotor RX-King. Ia memutuskan kuliah lagi pada 2007, kali ini mengambil studi politik di Yaleka Maro, di jalan TMP Folder. Seminggu di Merauke, seminggu berikutnya di kampung Kweel. Itulah rutinitasnya yang rutin.
Ia berkenalan dengan seorang kolega mahasiswa, yang beda kelas, usianya terpaut 15 tahun, dari suku Wiachar asal Mappi, yang mengenalinya dari nama fam. Ayah anak itu pernah satu aktivitas dalam Satgas.
“Ko pu bapak sekarang di mana? Su meninggal belum?
“Masih hidup,” katanya, “Ada di kampung.”
Begitulah polah Yeem. Orang mengenalinya bicara lugas, tak boleh tertawa sewaktu ia bicara. Orang mengingat jalannya tegap.
Kakaknya mengingat Yeem sebagai orang yang tegas, “Kalau tidak sesuai dengan dia, dia tidak ikut. Orangnya pu prinsip.” Bekas koleganya di Satgas pernah satu kali dipukul, “Pukul itu kalau kita kerja di luar komando, di luar instruksi Satgas.”
Pada tahun terakhirnya ia berambut tipis, dagunya bersih dari cambang, kumis dibiarkan tumbuh. Ia biasa ke kampus dengan berpakaian batik, celana kain hitam, kaki beralas sepatu. Ia juga perokok.
Ia mengumpulkan teman-teman di kampus, “Jangan ikuti arus. Bedakan mana yang benar.”
Pada akhirnya, Yeem menceritakan masa di mana ia pernah menjadi komandan Satgas, “Kita harus ingat pu sejarah.” Namun ia tak pernah cerita pengalaman ia disiksa. Ia juga menyembunyikan cerita bahwa sebetulnya, dalam masa tenang hidupnya yang singkat, ia kerap dimata-matai Kopassus.
“Kita harus tahu jati diri. Ko pu jati diri, martabat, identitas bangsa Papua,” satu kali Yeem berkata. “Kita bangsa Papua beda dengan Indonesia. Kita pu ras Melanesia.”
Pada satu kali, Yeem cerita pada temannya asal Mappi, kalau ia pukul orang Marind yang bakar hutan di Kweel.
“Kenapa ko bakar? Jangan sembarang bakar, kena pohon kayu putih,” ujar Yeem, bertahun-tahun kemudian diceritakan ulang temannya.
Orang Marind itu malah menjawab dengan berusaha pukul Yeem pakai penokok sagu. Yeem menangkis dengan tangan. Orang Marind itu lari ke bevaak dan ambil busur. Yeem lebih dulu memukulnya. Seminggu kemudian, setelah Yeem kembali ke Kweel dari Merauke, orang Marind itu telah melaporkannya kepada Kopassus, “Ada bantah apa di jalan?”
“Sa tra bikin gerakan atau apa. Sa kasih tahu ke saudara satu, jangan bakar sembarang hutan.”
Katanya, “Kau su pukul dan babak belur?”
Dua orang Kopassus buka mulut Yeem; pistol kutik tapi tak bunyi. Pistol ditembakkan ke dua telinganya—juga tak bunyi. Begitupula saat tembak di dahi. Mereka lantas mengambil bambu satu meter dan menggebuk badan Yeem hingga hancur-hancur.
“Kejadian itu diceritakan pada saya di kampus. Badan hitam-hitam, bengkak-bengkak,” ujar temannya.
Kali berikutnya, Yeem kembali dicap “separatis.”
Kepala kampung menebar isu bahwa Yeem hendak kibarkan bendera Bintang Kejora di tempat penebangan kayu gambir. Itu Agustus 2007. Sebagaimana di seluruh pedalaman Papua, otoritas keamanan setempat minta masyarakat untuk memoles kampung demi menyambut perayaan 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Yeem bersama 37 pemuda tengah membuka hutan untuk jalan raya, diminta oleh komandan militer setempat, pekerjaannya mengangkut kayu gambir. Pada 9 Agustus, kepala kampung melaporkan kepada Kopassus bahwa “pemuda-pemuda Kweel tidak kerja di kampung” karena ada kerja gambir.
Yeem menegur kepala kampung agar jangan suka lapor Kopassus, karena “pemuda kita di kampung sudah setiap kali dipukul terus sampai sudah rusak. Orang kampung ini kan orang Papua.”
Kepala kampung tak terima, kembali melaporkan teguran itu kepada Kopassus. Esoknya, Yeem dipukul dan diancam akan dibunuh.
Sebulan berikutnya, pada 7 Oktober sesudah ibadah Minggu, personil TNI dan Kopassus memerintahkan kepala adat untuk mengusir Yeem. Esoknya, jam 11 siang, Yeem bersama istri dan tiga anaknya menuju kampung Simpati, kelurahan Bupul 1 di distrik Elikobel. Belakangan Yeem sakit parah dan dibawa ke Merauke.
Kakaknya cerita, dalam setiap penyiksaan yang diderita Yeem, keluarganya abai merangkum rekam medis. Itu mungkin satu kesalahan kecil, tapi ini juga praktik umum di Papua.
Yeem bolak-balik berobat. Namun, pada satu hari yang menentukan, Yeem pelan-pelan kesulitan berjalan, memaksakan diri dengan memakai tongkat, sebelum akhirnya lumpuh total. Ia bilang kepada keluarganya, “Ya sudah, kasih tinggal saja.”
Bertahun-tahun kemudian kakak Yeem mengingat perkataannya, “Mati hari ini, besok, kapan pun sama saja. Kenapa harus takut mati? Yang penting kita kerja baik untuk tanah dan bangsa Papua, supaya orang Papua bisa kenang.”
Catatan editor: Musim Penyiksaan telah tayang di Pantau, pada 16 September 2014. Bollo.id memuat kembali tulisan ini, berkat izin dari Fahril Salam, sang penulis.
Keterangan foto sampul: Nicolaus Yeem/Anti-Tank (A)/Pantau