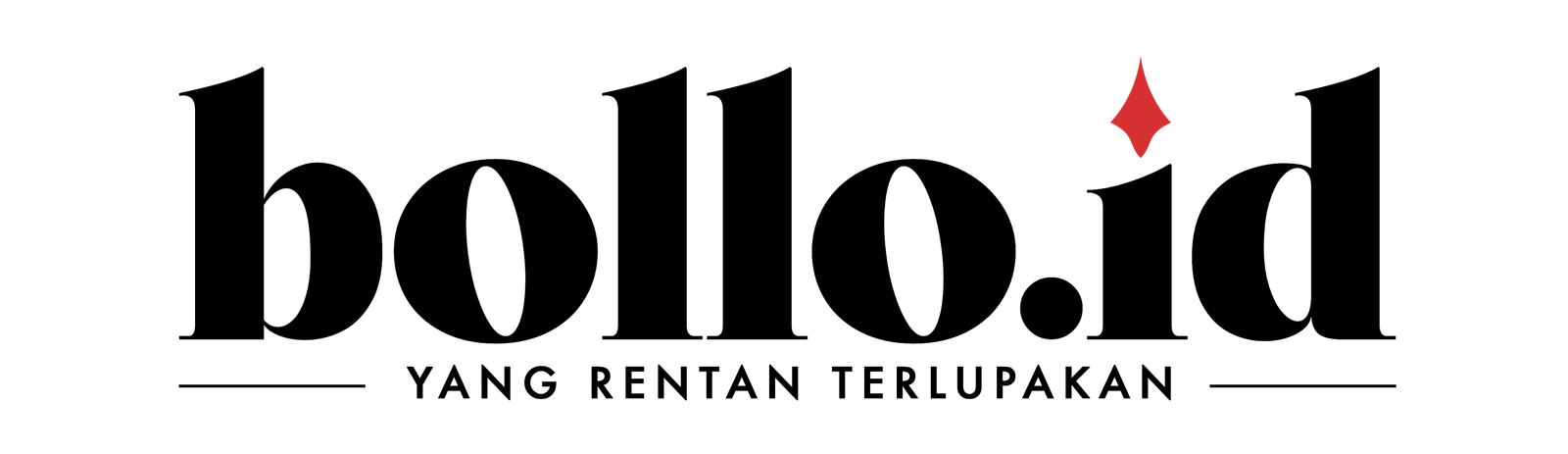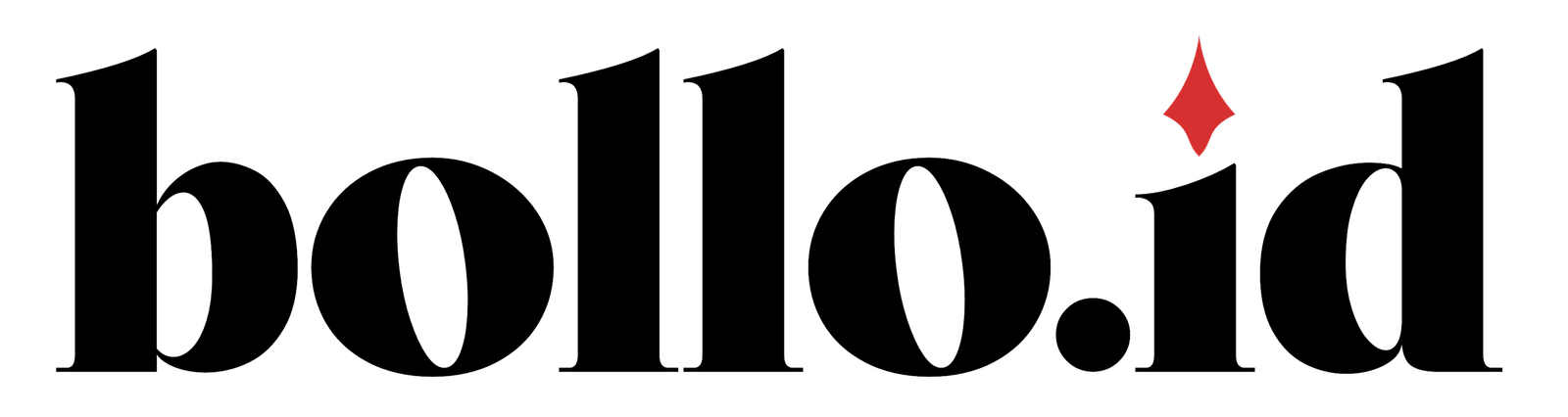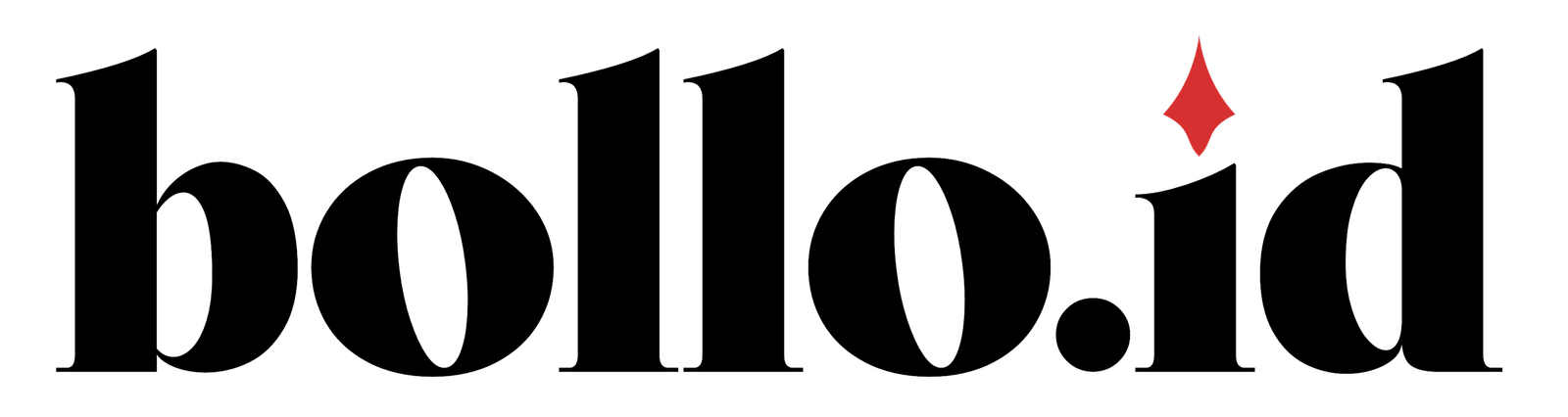Di Makassar, reklamasi sedang menuju Pulau Lae-Lae.
Namun, para perempuan menentang rencana itu.
Bagi mereka, reklamasi hanya membawa petaka.
Di bawah bayang reklamasi
Pagi itu, Daeng Siang duduk bersila di sebuah bale-bale depan rumahnya. Sarung batik coklat membungkus tubuh hingga dadanya.
Ketika kami berjumpa, Siang sedang memilah-milah tumpukan rumput hijau di depannya dari sebuah baskom plastik. Menanggalkan pasir dan bebatuan dari rumput itu. Satu demi satu.
“Ini namanya lato’, Nak,” kata Siang, menunjukkan rumput-rumput itu.
Sejak kecil Siang bertaruh hidup dari lato’, sejenis rerumputan laut yang tumbuh liar, di sepanjang sisi barat perairan dangkal Lae-Lae, sebuah pulau kecil berpasir putih di Kota Makassar, tempat Siang menaruh harapan.
Lato’ sebetulnya bernama Caulerpa lentillifera. Siang tak tahu kegunaan rumput itu sampai sang ayah mengajarkannya memanen lato’. “Dulu hanya untuk dimakan.”
Siang adalah seorang ibu tunggal bersuara serak, berusia separuh abad. Raja Mudin Tika, suaminya telah meninggal lima tahun lalu. Pasangan ini dikaruniai empat anak.
Ketika musim kemarau tiba, air laut mencapai titik surut terendah. Membuka jalan bagi Siang menuju tempat lato’. Saban pagi, sebelum laut kembali pasang, Siang akan bolak-balik, memboyong berkilokilo lato’.
“Kalau ada rejeki kadang tiga karung saya dapat,” kata Siang. “Harganya bisa sampai Rp300 ribu itu.”
Namun, kenyamanan hidup Siang selama ini akan tersentak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berniat menyulap tempat Siang mencari lato’ menjadi kompleks wisata, yang konon mendongkrak kehidupan Warga Lae-Lae macam Siang, sembari menekan angka pengangguran dan menyuntik pendapatan ke kas daerah.
Demi mewujudkan itu, pemerintah bakal menimbun laut di sisi barat Pulau Lae-Lae, seluas 12,11 hektare, dua pertiga lebih dari luas daratan Pulau Lae-Lae. Siang menentang rencana itu. Bagi Siang, reklamasi sama saja “membunuh para nelayan”–para kawan-kawan senasibnya.
Reklamasi Pulau Lae-Lae adalah bagian dari mega proyek Center Point of Indonesia, bagian kawasan strategis bisnis global terpadu Makassar, The Equilibrium Centerpoint Park (ECP), proyek reklamasi sebelumnya yang telah ‘membangun’ satu pulau baru berbentuk garuda raksasa, di ufuk barat Kota Makassar. Hasil ‘kongsi’ Pemprov Sulsel bersama PT Ciputra Development Tbk.
Di proyek ini, anak usaha Ciputra, PT Ciputra Nusantara menjalin operasi bersama dengan PT Yasmin Bumi Asri, sebagai pihak pengembang.

Dari 157,23 hektare luasan CPI–begitu akronim Center Point of Indonesia–Pemprov Sulsel kebagian 50,47 hektare, yang rencananya jadi kawasan publik. Saat ini, di lahan miliknya, Pemprov Sulsel telah membangun Mesjid 99 kubah, lego-lego, dan sebuah wisma negara. (Saat ini Pemprov Sulsel tengah membangun Rumah Sakit)
Sementara lahan sisanya jadi kompleks komersial bernama CitraLand City Losari. Sejauh ini, Ciputra telah menggelontorkan investasi hingga Rp3,5 triliun.
Namun jatah milik Pemprov Sulsel itu, tak sepenuhnya terbangun dan menyisakan 12,11 hektare.
Pembangunan itu terhalang persoalan administrasi: Sebab Tanah Tumbuh, yang semula dicanangkan jadi titik lahan itu telah terbit sertifikat atas nama Pemprov Sulsel, menurut seorang pejabat Pemprov Sulsel.
Setelah tersendat dua tahun, Pemerintah dan PT Yasmin Bumi Asri akhirnya meneken addendum keempat, atas Perjanjian Kerja Sama sebelumnya, pada 11 Januari 2023. “Untuk memenuhi kekurangan kewajiban investor (pembangunan lahan 12,11 hektare),” kata Harun Hajadi, Direktur PT Ciputra Development Tbk.
Pemprov Sulsel menunjuk Pulau Lae-Lae menjadi lokasi reklamasi, menutupi kekurangan lahan sebelumnya. Dan reklamasi itu setidaknya akan rampung pada Juli lalu. (Pembangunan kembali tertunda hingga hari ini).
Sebetulnya, Pemprov Sulsel telah merencanakan Pulau Lae-Lae, untuk direklamasi jauh sebelum addendum keempat itu diteken, sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 3/2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Selatan. (Perda RTRW Nomor 3/2022 telah dicabut).
Di atas reklamasi pengembang akan membangun spot untuk menatap senja, toilet, tenda wisata, taman publik, jalur pedestrian, gazebo, bermacam-macam sculpture, dan mengubah rumah-rumah warga menjadi warna-warni–dalam materi konsultasi publik, pemerintah menyebutnya dengan ‘colored island’. Sementara di luar areal reklamasi, adalah “areal milik Pemerintah Kota Makassar.”










Di Pulau Lae-Lae, kabar reklamasi itu terdengar pertama kali pada akhir 2020 lalu, melalui ungkapan Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ketika berkunjung ke pulau itu. Namun, warga menanggapinya sambil lalu.
Tak lama setelah addendum keempat diteken, sebuah spanduk besar berdiri di sudut pulau, tak jauh dari titik reklamasi. Spanduk itu menampilkan surat edaran berkop Pemprov Sulsel tertanggal 9 Februari 2023, mengumumkan bahwa reklamasi Lae-Lae akan segera dimulai.
Ketika spanduk itu berdiri, kehidupan warga mulai berubah–juga kehidupan Siang. Spanduk itu tak ubahnya mengabarkan sebuah petaka yang–suatu saat–mengetuk pintu mereka. “Kita pikir-pikir,” kata Siang.
“Kenapa pemerintah ini tega mau kasih begitu kita?”
Menurut pemerintah, Warga Lae-Lae menolak rencana itu karena “ketidaktahuan.”
“Kehadiran Pemprov Sulsel–dalam hal ini,” kata Muhammad Ichsan Mustari, Asisten II Pemprov Sulsel Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
“Tidak sama sekali membuat masyarakat sengsara. Itu. Catat baik-baik.”

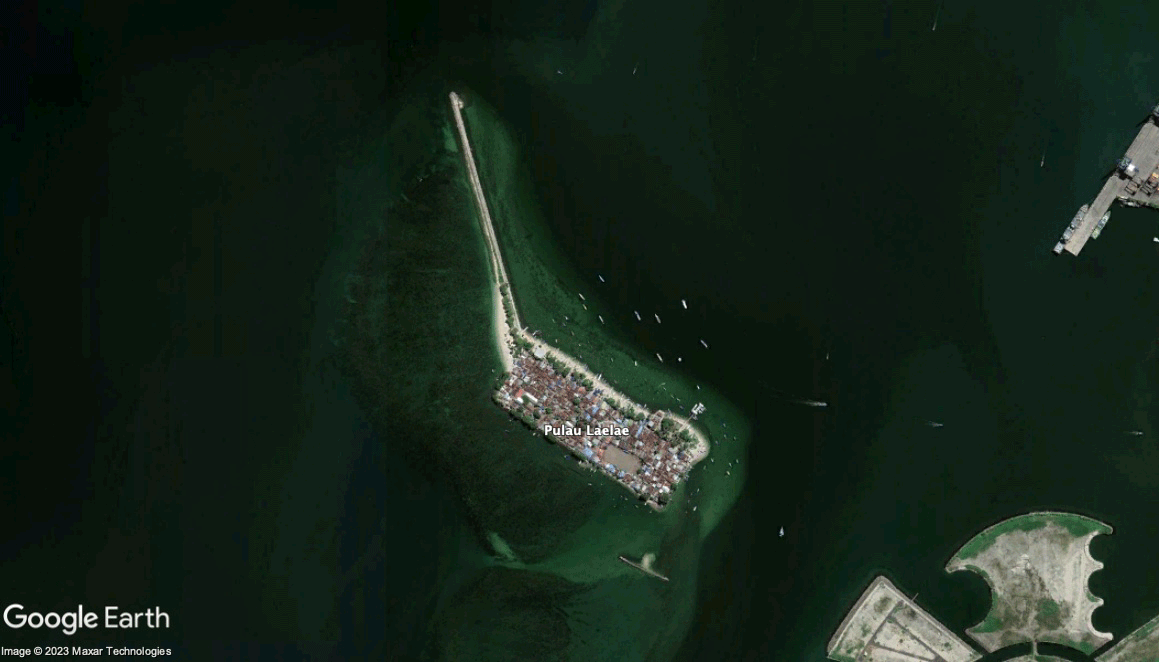
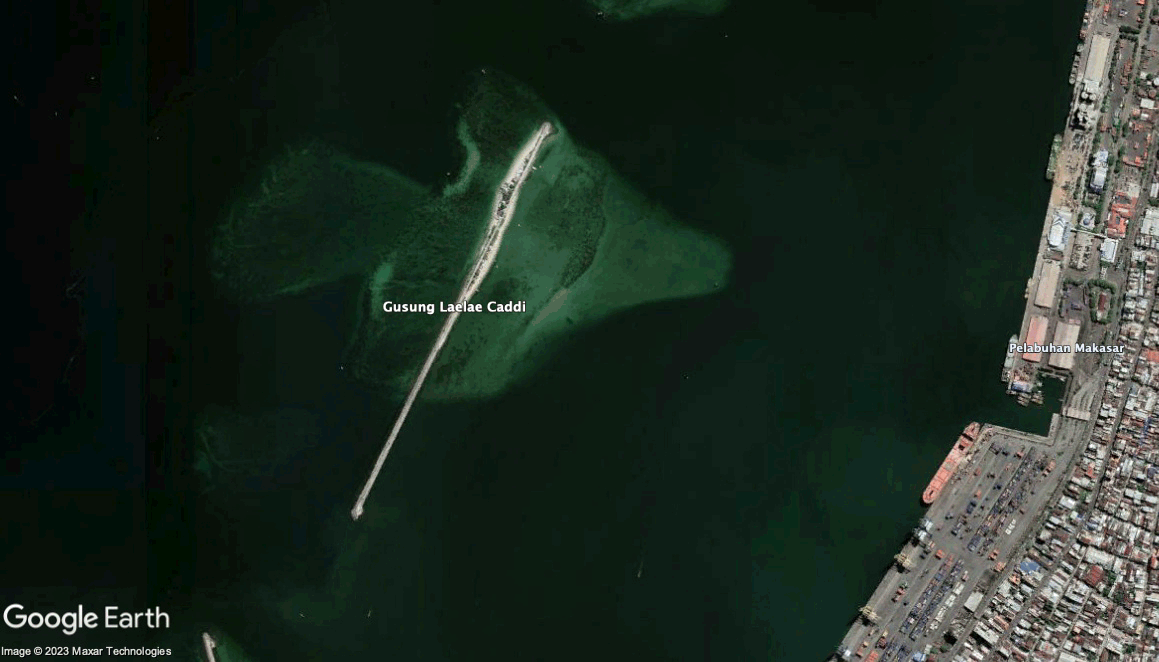
***
Pulau Lae-Lae adalah sebuah pulau kecil berpasir putih, seluas 9 hektare. Rumah bagi 1.523 penduduk dengan mayoritas perempuan. Di zaman kolonialisasi pulau ini jadi tempat persembunyian.
Di lahan sesempit itu, warga membangun rumah berderet-deret, membentuk pemukiman padat, dengan jalan setapak yang menghubungkan interaksi warga sehari-hari.
Di Lae-Lae, warga hidup dari berkat laut. Mereka menangkap ikan, cumi, kerang, lato’ hingga ambaring–sebutan udang rebon (Acetes indicus). Beberapa warga menyediakan jasa transportasi antar pulau, ketika aktivitas menangkap usai.
Di pulau ini, kami menemui Siang pada pagi terik pertengahan November 2023, jelang musim lato’ berakhir. Dia menyambut kami dengan penuh hangat, sambil mengenalkan lato’ hasil panennya di pagi itu, kepada kami.
Perempuan Lae-Lae seperti Daeng Siang akan mencari lato’ ketika musim timur bergulir. Ketika penghujan, para perempuan nelayan ini berganti menangkap udang rebon.
“Ayo, kita pergi cari lato’,” Daeng Siang mengajak kami. “Sebelum air laut naik lagi.”
Siang pun lekas mengganti sarungnya dengan pakaian basah, bekas rendaman laut pagi tadi.
Kami menuju sisi barat pulau, tempat lato’ tumbuh liar, pada perairan dangkal, belasan meter dari bibir pantai. Laut telah surut sejauh belasan meter, membuka jalan bagi kami. Muka laut kini hanya setinggi lutut dan kami harus menggulung celana.
Di sini, Siang berjalan sembari menunduk dan meneropong dasar air: berusaha mencari lato’ dan menghindari bulu babi yang berduri (Echinoide).
Memanen lato’ butuh ketelatenan. Siang, tidak mau lato’ yang dia cabut dari karang penuh pasir dan sampah. Itu hanya menambah beban buat Siang.
Di sini, di tempat yang bakal direklamasi, lato’ tumbuh melimpah dan telah menghidupi keluarga para perempuan nelayan sejak puluhan tahun.


Siang lahir di pulau itu, 1971 silam. Mendiang ayahnya, Bacoa adalah orang yang mengajarinya mencari lato’, saat dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Siang, adalah keturunan langsung dari Daeng Mamba dan Malolo Daeng Kebo, pemukim pertama di pulau itu.
“Dulu itu waktu masih anak-anak, ini lato’ cuma kita makan,” kenang Siang. “Sekarang ini baru kita tahu kalau banyak orang yang suka makan. Jadi kita jual.”
“Apalagi kalau air surut begini, kita panggil teman-teman lain turun cari lato’. Ramai kalau musimnya.”
Kini, mencari lato’ seperti adegan yang menyayat hati. Hubungan Siang dan lato’ bisa saja berakhir.
“Sekarang ini pikiran saya itu karu-karuan,” kata Siang.
Reklamasi menurut Siang tidaklah adil dan pemerintah telah gagal memahami kehidupan para nelayan di pulau. Jika reklamasi jadi, kata Siang, dia sudah tentu akan berhenti mencari lato’.
“Di mana lagi mau mencari?” tanyanya.
“Makanya kita tidak ikhlas mau direklamasi. Kita punya pulau di sini. Kita tidak mau reklamasi. Walaupun tiap hari pendapatan kita sedikit, yang penting tidak ada yang ganggu kita di sini.”
***

Penolakan reklamasi Pulau Lae-Lae telah bergulir setidaknya satu tahun. Warga telah melancarkan protes berbulan-bulan, bersimpul, dan saling menguatkan.
Di Pulau Lae-Lae, jika kamu berkunjung, kamu dengan mudah menemukan pataka-pataka protes di tiap sudut perkampungan. Mereka seakan-akan hendak menunjukkan, sebuah keteguhan menolak reklamasi.
Selama protes bergulir, pemerintah merespons dengan “solusi”, yang bagi Koalisi Lawan Masyarakat (Kawal) Pesisir hanya sekadar rayuan, agar proyek itu dapat berjalan, alih-alih membatalkannya. “Solusi itu lagi-lagi hanya mentok dikompensasi, soal ganti rugi,” kata Putra dari Kawal Pesisir. Kawal Pesisir adalah koalisi dari sejumlah organisasi non-pemerintah, individu aktivis, dan kelompok mahasiswa.
Di Lae-Lae, Siang bukan satu-satunya perempuan nelayan yang kelak kehilangan mata pencaharian.
Perkenalkan, Kartini. Seorang perempuan nelayan. Selama ini, kata Kartini, nelayan di Pulau Lae-Lae telah hidup dari hasil laut yang kaya.
Hubungan Kartini dengan pantai itu telah terukir sejak dia berusia sepuluh tahun.
“Pokoknya kalau untuk dimakan saja, tidak susah,” katanya.
“Kalau ada reklamasi, hilang semua kasihan karena ditimbuni sampai keluar.”
Musim barat adalah saat Kartini turun ke laut mencari ambaring. Sehari, Kartini bisa membawa uang puluhan ribu ke rumah. Satu keranjang ambaring seharga Rp30 ribu.
“Apalagi kalau musim hujan itu, bisa banyak pendapatan karena naik ambaring,” kata Kartini.
“Bahkan ada ikan bolu laut kalau musim hujan.”
Di tempat lain, kami berjumpa dengan Ramlah, seorang perempuan nelayan berusia 35 tahun. Ramlah juga menaruh hidup dari lokasi yang akan direklamasi. Di sana, ketika musim timur dan air laut mencapai titik surut terendah, dia mencari kerang tude untuk dikonsumsi.
Ketika warga berdemonstrasi, Ramlah ikut di garis depan. Menentang rencana reklamasi itu.

Nenneng tersenyum, menyilahkan kami duduk di depan rumahnya. Dia sedang menganyam tali nilon tipis untuk membuat purupuru, satu alat umpan kecil. Gerak tangan Nenneng yang lincah memberi kesan kepada kami: aktivitas itu telah dia tekuni sejak lama.
Purupuru seperti sangkar kecil seukuran ibu jari. Nelayan memasang purupuru di tali pancing, sebagai tempat ambaring, umpan kesukaan ikan-ikan pelagis.
Pengetahuan membuat purupuru adalah warisan keluarga Nennneng. Diturunkan dari Ibu ke anak perempuan. Pembuatan purupuru bergantung pada musim ambaring. Di musim itu, dia dapat memproduksi 20 hingga 30 purupuru setiap hari.
“Satu purupuru, saya jual lima ratus rupiah,” katanya.
“Kita juga tidak bisa kejam-kejam pasang harga sama nelayan. Saling bantulah begitu.”
Rumah Nenneng berhadapan dengan lokasi yang bakal direklamasi. Nenneng tidak sanggup membayangkan bagaimana kelak jika reklamasi tetap dilakukan di Pulau Lae-Lae. Dadanya sesak ketika membayangkan itu.
“Liat itu,” Nenneng melempar telunjuknya ke arah laut.
“Itu nelayan. Tidak usah banyak bicara bilang di situ tidak ada ambaring, ikan, apa segalanya,” Nenneng menghela nafas.
“Itu sudah ada bukti, nelayan di situ mencari. Kalau direklamasi di mana mau mencari? Pemerintah mau bangun besar-besaran, padahal itu semua wilayah tangkap.”
Apa yang ditunjuk Nenneng adalah letak-letak rumpon. Di Lae-Lae, rumpon diartikan sebagai tempat ikan berkumpul. Rumah ikan. Menurut catatan Kawal Pesisir, di lokasi itu terdapat sebelas rumpon, yang keberadaannya dinafikan oleh pemerintah. “Di mana ada rumpon dekat Lae-Lae di situ? Tempatnya itu tidak ada rumpon,” kata Ichsan Mustari.
Pemerintah mematok proses pembangunan reklamasi di Pulau Lae-Lae akan memakan tiga bulan. Selama pembangunan, nelayan yang terkena dampak, kata Ichsan akan diberikan kompensasi uang.
“Dihitung,” katanya. “Seberapa banyak sih dia dapatkan seharusnya dalam tiga bulan itu. Setelah itu [pembangunan reklamasi usai] mereka akan diberdayakan di sana.”
Namun, bagi Nenneng, ungkapan reklamasi akan meningkatkan taraf ekonomi warga tidak masuk akal. “Apa mau dia tingkatkan kalau sudah tidak ada mata pencaharian?”
“Memang gampang bicara memperindah, mempercantik,” katanya.
“Hasilnya bagaimana? Ini sudah jelas membunuh mata pencaharian nelayan. Indah pulaunya tapi tidak ada makannya, lebih bagus tidak usah cantik.”
Selain bikin purupuru, Nenneng jualan sayur keliling di Pulau Lae-Lae. Jika sedang ramai pembeli, Nenneng meraup untung hingga Rp300 ribu. “Yang pertama itu setengah mati nelayan kalau reklamasi jadi,” kata Nenneng. “Kalau begitu, penjual sayur juga pasti setengah mati.”
Nenneng bersoloroh. “Siapa mau beli? Apa mau dia belanja istrinya kalau sudah tidak ada kerjanya?”

***
Siang selalu menolak melibatkan diri dalam rapat sosialisasi perencanaan reklamasi. Dia khawatir jika dalam pertemuan itu, dia bersama dengan nelayan lain justru terjebak karena membubuhkan tanda tangan: tanda bahwa mereka menyetujui reklamasi di Pulau Lae-Lae.
“Pemerintah itu pintar,” katanya.
“Dia bilang, ini semua orang Pulau Lae-Lae sudah tanda tangan, dia baleki kita.”
Suatu waktu, kata Siang perwakilan pemerintah bertanya. “Kenapa tidak mau direklamasi pulaunya?”
“Jadi kita bilang,” kata Siang.
“Kalau direklamasi itu, Pak, di mana mata pencaharian kita? Sedangkan yang mau direklamasi itu, di situ kami mencari. Jadi kami tidak mau.”
Sejauh ini rencana reklamasi itu masih dalam tahap persiapan. Pemprov saat ini sedang menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). “Baru mau dianalisis lingkungannya, tapi didemo-demo terus,” kata Ichsan Mustari.
“Apa dampak lingkungannya?” jurnalis Bollo.id bertanya.
“Saya kira tidak berdampak pada lingkungan, insyaallah,” Ichsan menjawab. “Karena kan, dilakukan analisis dulu toh. Kalau memang tidak sesuai dengan lingkungan, kita tidak bangun. Kan gitu.”
Reklamasi Lae-Lae membutuhkan 380 ribu meter kubik urugan. Dalam dokumen kerangka acuan, urugan itu berasal dari sedimen di kanal pelabuhan milik Pelabuhan Indonesia IV, melalui proses penambangan. Ichsan mengklaim penambangan itu sudah sesuai aturan.
“Regulasi hukum ada yang kita pakai. Saya tidak terlalu tahu teknisnya yang pasti bahwa itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” katanya. “Itu saja.”
Selama di Pulau Lae-Lae, kami kerap mendengar ungkapan warga bahwa, jika reklamasi terjadi, maka pemerintah akan membangun sebuah jembatan yang menyambungkan CPI dan pulau itu. Ichsan membantah. “Saya tanda tangan lho, saya bikin pernyataan bahwa tidak ada dibikin jembatan.”
“Siapa yang bilang? Saya ini mewakili Pemprov,” kata dia.
“Di dalam [memang ada jalur pedestrian] bukan jembatan. Dia [Pergub Nomor 14/2021] tidak sebut mengenai jembatan toh,” kata Ichsan, sambil mencolek perut jurnalis Bollo.id, yang mewawancarainya.
Jurnalis Bollo.id juga menanyakan dampak sosial yang akan timbul dari reklamasi Lae-Lae.
“Dampak sosialnya?” jawab Ichsan. “Yaa… Masyarakat semakin punya tempat untuk meng-healing-kan dirinya, karena destinasi wisatanya ada.”
Icshan tertawa. “Masyarakat sudah punya banyak tempat untuk bersantai. Kumpul dengan keluarga. Sehingga, bisa betul-betul memperbaiki kondisi psikis mereka untuk menghadapi hari Senin sampai Jumat, saat mereka kerja.”
Pada kami, Ichsan mengklaim bahwa reklamasi Lae-Lae berbeda dengan reklamasi yang lain–tanpa menunjukkan contohnya. Yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial. “Jangan kita bayangkan sama dengan reklamasi yang lain,” katanya.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
***

Hari kian terik dan laut mulai pasang. Siang masih mencari lato’. Memungut dan memasukkannya ke dalam ember.
Sebelum kami pulang, Siang menebar potongan-potongan lato’ ke tempat itu. “Biar kembali tumbuh.”
Kami bersama Siang kembali ke rumah, membawa lato’ satu ember penuh. Beberapa pekan ke depan, musim telah berganti dan reklamasi mungkin akan dimulai tak lama lagi.
Siang telah memulangkan lato’ ke laut, berharap di tahun depan dia kembali memanen rumput itu. Namun, itu mungkin yang terakhir kali dia lakukan.
Tetapi, Siang tak mau itu terjadi. “Biar apa pun dia bawa, pokoknya kita tolak,” kata Siang.
“Tidak takut polisi, tidak takut apa-apa. Kita mau mati demi kita punya pulau di sini.”
Foto sampul: Kawal Pesisir
Tim Laporan Mendalam: Chaerani, Muh. Aidil, dan Muh. Syawal.
Penulis: Muh. Aidil dan Muh. Syawal
Editor: Agus Mawan W
Penata ruang: Agus Mawan W