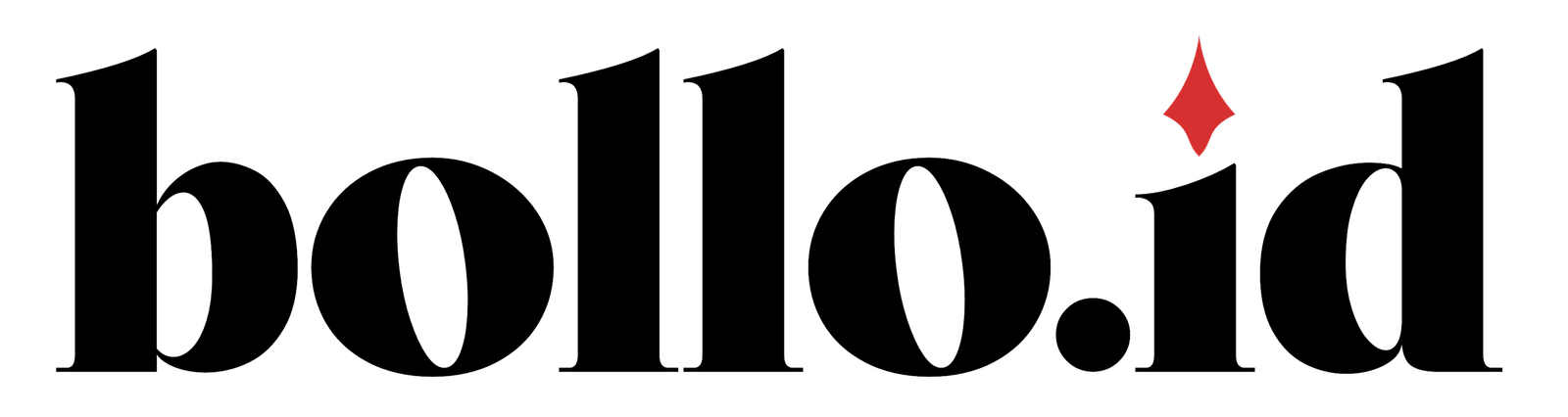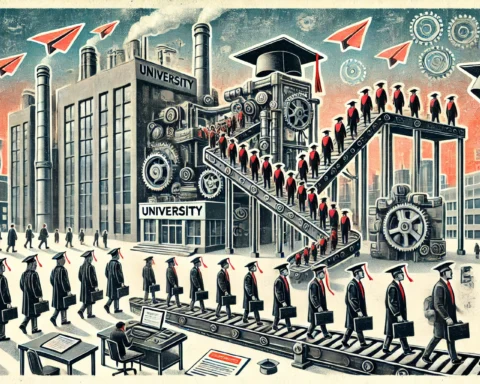Pada sejarahnya masyarakat mengenal hukum tidaklah sama dengan yang ada sekarang. Dulu hukum lebih rendah daripada perkataan penguasa atau raja yang dipandang oleh masyarakat sebagai kehendak tertinggi dan wajib dipatuhi. Hukum saat itu hanyalah aturan biasa yang digunakan terhadap masyarakat kelas bawah saja. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, melalui pergantian zaman, bangkit keinginan untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang didasarkan pada kesetaraan dan kebebasan, dimana setiap individu yang termasuk di dalamnya akan dilindungi oleh suatu aturan sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur dan menjaga masyarakat menggantikan ide kekuasaan penguasa maupun raja.
Aturan ini diharapkan menjadi dasar yang akan melindungi setiap orang secara setara dan adil yaitu hukum. Untuk itu banyak pemikir telah memikirkan ide mengenai apa itu hukum, pemikiran mereka telah melalui proses penyempurnaan ide dari generasi ke generasi guna mencapai pemahaman yang utuh tentang hukum. Disini saya mengambil tiga ide mengenai hukum dari para pemikir hukum berbeda zaman yaitu Aristoteles, John Locke, dan Lon Fuller. Mereka menafsirkan hukum tersebut melalui banyak pengalaman dan pemikirannya.
Sangat patut untuk kembali memikirkan ide pemikiran hukum Aristoteles. Dalam karya-karyanya, Aristoteles memberikan sumbangsihnya mengenai hukum. Dalam tulisan-tulisannya terdapat konsep hukum yang kuat selagi dirinya membahas mengenai filsafat politik dan cara masyarakat menuju kebahagiaan (Eudaimonia). Aristoteles berpendapat bahwa hukum yang adil lahir dari pertimbangan rasional akal budi manusia dan hukum digunakan sebagai instrumen untuk membimbing masyarakat agar berperilaku etis serta bermoral. Dalam pandangannya, Aristoteles meyakini bahwa lebih pantas agar hukum yang memerintah masyarakat dibandingkan satu orang ataupun segelintir orang yang memerintah. Sebab menurutnya, kekuasaan tertinggi pada seseorang lebih baik berperan sebagai penjaga atau pelayan dari hukum dan setiap individu tunduk dalam ruang lingkup hukum.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
John Locke sendiri berpandangan bahwa kontrak sosial yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah, diwujudkan dalam hukum yang tak hanya melindungi dan menyediakan stabilitas keamanan, tetapi juga melindungi hak-hak mereka yang mana dalam pandangannya adalah perihal hak asasi. Dalam pemikiran Locke, pemerintah melalui hukum yang diwujudkan harus melindungi hak individu dan masyarakat yang berada dalam kekuasaannya. John Locke melihat kekuasaan haruslah dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan kepentingan masyarakat menjadi hal yang utama.
Yang terakhir, adalah pemikiran hukum dari Lon Fuller yang memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang mengatur dan menjaga ketertiban di dalam masyarakat, tetapi juga sebagai pembimbing yang memiliki peran moral dalam membentuk masyarakat. Hukum bagi Fuller harus sesuai dengan norma-norma etika yang ada dan memiliki aspirasi masyarakat di dalamnya. Ide hukum Fuller melihat bahwa moralitas dan hukum tidak dapat dilihat secara terpisah, inilah yang kemudian dalam pandangannya menyatakan jika hukum haruslah mencerminkan nilai dan pandangan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hukum pun dinilai perlu selama proses pembentukan aturan tersebut.
Kebijakan Hukum Indonesia
Perjalanan panjang telah dilalui bangsa Indonesia dalam mencari tatanan hukumnya. Hal ini dikarenakan sejak awal berdiri Indonesia telah memiliki tiga bentuk hukum yang hadir dalam masyarakatnya. Yakni hukum pemerintah kolonial, hukum adat, dan hukum islam. Ketiga hukum tersebut masing-masing berperan penting dalam perjalanan hukum bangsa Indonesia. Hukum adat dan hukum islam pun dalam beberapa kasus lebih diminati masyarakat daripada hukum formal negara. Pada era Orde Baru, hukum tampak tidak berbeda dengan kekuasaan, justru hukum itu tunduk pada kekuasaan dan tidak memiliki nilai atau aspirasi yang ada dalam masyarakat. Hukum pada saat itu hadir sebagai anjing tirani yang mengawasi setiap orang yang berbeda pendapat dengan penguasa, menjadi lambang represif. Menimbulkan pertanyaan apakah hukum Indonesia adalah hukum yang represif?
Di era saat ini, pembangunan baik secara infrastruktur dan ekonomi begitu gencar dilakukan oleh pemerintah untuk tahun emas 2045. Melansir dari CNN dalam data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), telah terjadi 2.710 konflik selama sepuluh tahun terakhir yang menekan masyarakat hingga berujung pada konflik agraria antara pemerintah dan masyarakat. Hukum yang seharusnya menjadi wadah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan justru digunakan menjadi instrumen yang sah menekan mereka yang tidak patuh, slogan pembangunan pemerintah tersebut nyatanya membuat masyarakat terpinggirkan. Masalah dari pembangunan yang digagaskan ini adalah seringkali tidak memenuhi aspek-aspek lain selain ekonomi seperti ekologis dan sosial, sehingga kebanyakan membuat masalah sosial yang berkepanjangan. Dalam kasus tulisan ini, adalah isu reklamasi Pulau Lae-lae yang menjadi masalah antara pemerintah dan masyarakat Pulau Lae-lae.
Baca juga: Sisi Kelam Hutan Pinus: Folk bagi Orang Kota, Bencana bagi Orang Desa
Untuk mengerti lebih dalam mengenai isu ini, saya melakukan perjalanan menuju Pulau Lae-lae untuk memahami bagaimana masyarakat melihat reklamasi yang telah menjadi produk hukum oleh pemerintah. Pulau Lae-lae dekat dengan Kota Makassar karena hanya sekitar 10 menit perjalanan dari wilayah pesisir. Masyarakat di sana hidup sebagai pappalimbang atau penyedia jasa penyeberangan laut, nelayan, dan penjual makanan yang ada di tiap sudut pulau. Kehidupan sosial berjalan harmonis dan memiliki kedamaian khas pulau yang tidak terlalu dijamah oleh individualisme modernitas. Di sana, saya bertemu dengan Daeng Bau sebagai salah satu perwakilan masyarakat yang menolak rencana reklamasi Pulau Lae-lae. Dikatakan bahwa awalnya rencana tersebut terjadi dan disosialisasikan oleh orang-orang pemerintah yang masuk ke Pulau Lae-lae dengan maksud ingin memperindah pariwisata yang ada di pulau tersebut.
“Tiba-tiba 2023 bulan 3 kemarin, mereka datang. Datang ingin melangsungkan pembangunan untuk reklamasi wilayah tangkap Pulau Lae-lae seluas 11,12 hektar. Kami kaget, tiba-tiba warga yang lain termasuk saya. Saya kesana berkerumun dengan semua warga. Kaget, tiba-tiba kami diserang, jadi kami tiba-tiba juga melawan ingin menghentikan pekerjaan mereka, suruh cabut semua bagangnya. Semua alat bornya di laut kita suruh cabut, suruh kembali ke PT Yasmin. Dari bulan 3 itu terjadi, saya mulai aksi di situ sama warga Lae-lae yang menolak,” ucap Daeng Bau kepada saya saat saya temui untuk keterangan mengenai awal isu reklamasi terjadi.
Dalam keterangan Daeng Bau, proyek reklamasi yang dalam penjelasan pemerintah tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat Pulau Lae-lae juga karena ingin memperbaharui pariwisata yang ada di pulau tersebut. Melansir dari sumber Kompas Wakil DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif mengungkapkan, bahwa proyek reklamasi Pulau Lae-lae belum memperoleh izin yang diperlukan dan masih terus dalam proses pengkajian. Ini merupakan pertanyaan besar tentang transparansi dan keberlanjutan lingkungan dalam proyek reklamasi ini. Berdasarkan kenyataan inilah, proyek reklamasi yang ingin dilakukan di Pulau Lae-lae nampak tidak memiliki roadmap yang jelas dan memang tidak memiliki aspek-aspek yang memadai dalam pelaksanaannya, baik izin lingkungan maupun izin dari pihak-pihak terkait layaknya otoritas pelabuhan dan perhubungan.
Reklamasi yang ingin dilakukan pun tidak melibatkan partisipasi masyarakat Pulau sebab seperti dalam keterangan di atas dari Daeng Bau, justru masyarakat pulau terkejut dengan adanya rencana tersebut di pulau mereka. Dasar alasan penolakan rencana reklamasi oleh masyarakat pulau pun kuat, Daeng Bau menuturkan, bahwa masyarakat tidak menginginkan reklamasi terjadi di Pulau Lae-lae sebab reklamasi sama saja menghilangkan ruang hidup masyarakat Pulau Lae-lae.
“Kami berhak menjaganya, terutama demi untuk kelangsungan kehidupan kami selanjutnya, anak cucu kami sebagai nelayan. Yang kami tahu reklamasi itu tidak ada yang mensejahterakan warga setempat, apalagi penimbunan di laut. Otomatis ruang hidup kami sebagai nelayan hilang,” ucap Daeng Bau.
Dalam kata-katanya, Daeng Bau menjelaskan bahwa masyarakat Lae-lae menolak dengan alasan ini, “Mengapa kami disini menolak keras? Karena sudah ada dampak yang kami rasa sejak terjadi pembangunan Pantai Nusa Hari CPI sana. Reklamasi di sana dampaknya sangat besar bagi kami di sini. Terutama pada saat mereka membangun di sana, berlangsung pembangunan. Salah satu hasil nelayan yang biasa kami dapat itu di ombak besar, musim hujan itu ambaring. Angin kencang kami biasa dapat itu di bulan 1 sampai bulan 5. Itu sudah hilang sejak adanya CPI Pantai Nusa Hari. Karena airnya di sebelah selatan Pulau Lae-lae sudah keruh air, sudah kotor, sudah tercampur dengan semen. Itu sudah hilang, sudah 3-4 tahun yang lalu sudah hilang. Sejak adanya CPI sana. Terus dampak kedua dari sana, abrasinya. Tanggul-tanggul kami di sini di Pulau Lae-lae hancur di sebelah barat dari ujung ke ujung.”

Perihal kelanjutan isu reklamasi Pulau Lae-lae, Daeng Bau menjelaskan, “Kita tetap waspada adanya reklamasi karena memang reklamasi tetap dilakukan sampai 2027, menurut hasil dari RDP kemarin di DPRD Provinsi Kota Makassar,”. Baginya, masyarakat Lae-lae merupakan orang-orang yang sejahtera. Reklamasi menurutnya tidak akan mensejahterakan masyarakat pulau, justru sebaliknya sehingga masyarakat tidak setuju dengan adanya reklamasi pulau. Isu reklamasi Pulau Lae-lae berdampak besar tidak hanya kepada kehidupan sosial dan warisan budaya pulau tersebut tetapi juga dapat mengantarkan dampak negatif terhadap aspek lingkungan secara keseluruhan di wilayah laut sekitarnya. Dalam aspek lingkungan telah dijelaskan oleh Daeng Bau, banyak masyarakat sebagai nelayan pun akan terdampak oleh sebab reklamasi ini.
Reklamasi telah menjadi produk hukum melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 yang dilegalkan oleh pemerintah dengan maksud memperindah pariwisata Pulau Lae-lae. Tetapi dalam kenyataannya, produk hukum ini justru memungkiri nilai dan aspirasi masyarakat yang seharusnya ada dalam produk kebijakan hukum pemerintah. Bagaimana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Provinsi Sulsel dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembangunan Destinasi Wisata Bahari di Pulau Lae-lae dapat disebut sebagai produk hukum yang mendukung masyarakat Pulau Lae-lae jika yang terjadi justru dapat menghilangkan ruang hidup mereka sebagai masyarakat pesisir. Proyek reklamasi Pulau Lae-lae berlawanan dengan harapan yang mereka bawa untuk pulau tersebut.
Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa produk hukum menghasilkan suatu kebijakan yang terealisasi dalam masyarakat dan pemerintah tidak mengikuti apa yang ada dalam pemikiran ide hukum Aristoteles, Locke, ataupun Fuller. Tak ada moralitas dan rasa aman dari reklamasi Pulau Lae-lae sebab hal tersebut justru menghilangkan ruang hidup mereka, tak ada hak yang dilindungi justru tampak pemerintah datang sekuat tenaga melaksanakan kebijakannya atas Lae-lae saat masyarakat pulau menentang hal tersebut dengan berbagai bentuk aksi yang menunjukkan mereka adalah masyarakat yang mandiri dan mampu. Bagaimana pemerintah dapat melegalkan suatu produk hukum kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat disaat ada keinginan untuk melakukan revisi terhadap RT/RW perihal alokasi ruang reklamasi.
Benar bahwa hukum merupakan produk dari proses politik tetapi kepentingan siapa yang dibawa oleh reklamasi Pulau Lae-lae? Tentu kita tahu dari kenyataan masyarakat menolak, itu bukan kehendak masyarakat Pulau Lae-lae. Produk hukum yang melegalkan reklamasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang RT/RW Provinsi Sulsel dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 dinilai oleh Koalisi Masyarakat Sipil melalui KAWAL Pesisir harus direvisi kembali sebab menghilangkan ruang hidup masyarakat pulau melalui reklamasi. Hukum yang seharusnya menjadi tempat masyarakat Pulau Lae-lae merasakan rasa stabil dan aman serta terlindungi haknya justru digunakan untuk melegalkan sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai dan aspirasi mereka.
Filsafat hukum dalam ide pemikiran baik Aristoteles, John Locke, dan Lon Fuller yang merangkum hukum sebagai instrumen mencapai stabilitas serta rasa aman, hak terjamin, dan pembimbing moral tampak bak ide-ide utopis yang di idam-idamkan ada dalam masyarakat tetapi ditiadakan oleh kekuasaan. Ini memicu gerakan-gerakan masyarakat Pulau Lae-lae yang melakukan berbagai kegiatan di pulau maupun demonstrasi dalam berbagai kesempatan sebagai satu-satunya instrumen yang dapat mereka gunakan untuk mengungkapkan aspirasi dan nilai yang mereka yakini sebab hukum tidak dapat mewujudkannya bagi mereka.
Ini adalah ironi dalam sebuah negara yang mengatasnamakan negara hukum tetapi banyak pembangunan justru memunculkan konflik agraria yang meminggirkan masyarakat dan hukum yang ada justru digunakan untuk mempertanyakan keabsahan masyarakat yang bernaung di wilayah tersebut. Sudah seharusnya kita kembali merefleksi ulang apakah hukum saat ini adalah hukum nyata atau hukum kaku yang culas? Apakah hukum kita telah menjiwai “hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya”? Bagaimana kita dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti dalam grundnorm atau teori hukum murni kita yakni Pancasila saat hak masyarakat untuk kehidupan yang layak dan aman terbayangi oleh kukungan produk hukum pemerintah beserta pihak pengembang swasta itu sendiri.
Editor: Sahrul Ramadan