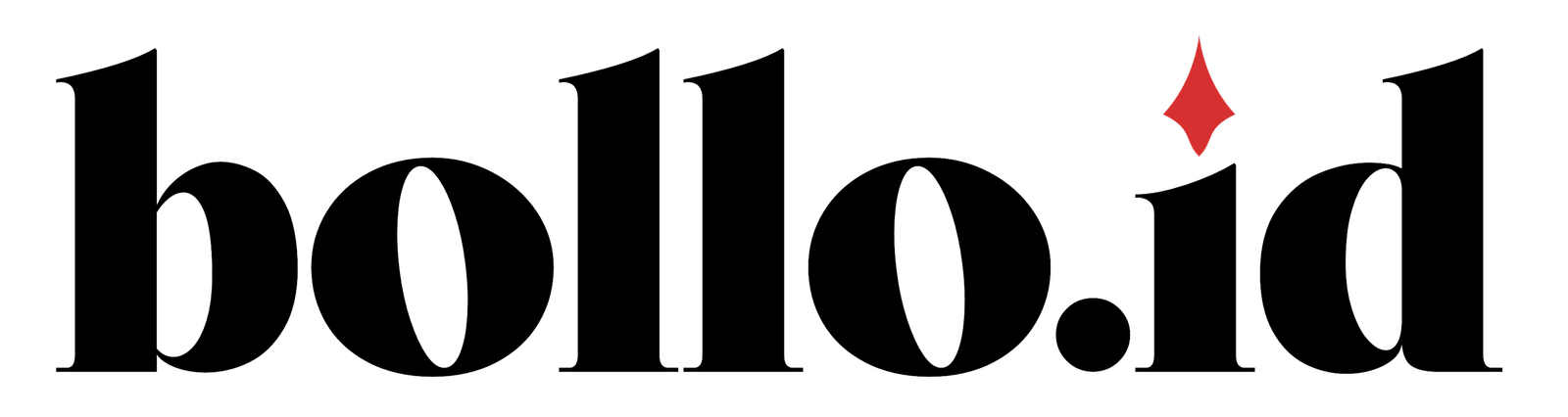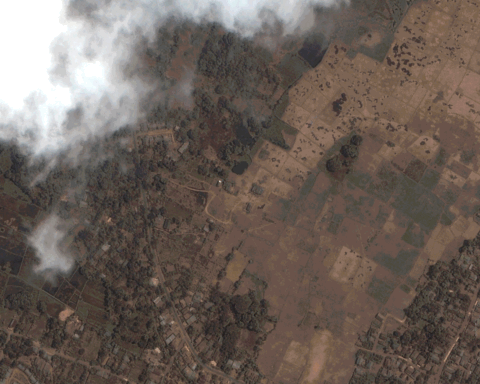Perubahan iklim, hasil tani yang menurun, bencana iklim, dan ketimpangan penguasaan lahan di Kajang, telah menciptakan prekariat; suatu lapisan masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian kerja dan penghasilan. Memicu migrasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Laki-laki hingga perempuan.
Migrasi itu bermuara di perkotaan. Arena berburu peruntungan. Bertaruh hidup pada remah-remah pusaran ekonomi dari tepian kota.
Makassar, sebuah kota metropolitan di Timur Indonesia telah jadi muara bagi perantau Kajang. Di sini, mereka memupuk keakraban yang erat. Membentuk kampung di sudut kota. Dan meringankan beban sanak keluarga di kampung asal.
Kisah tentang migrasi kali ini, datang dari para perempuan perantau yang bermukim di Kajang, sebuah wilayah administrasi di Bulukumba, meliputi berbagai desa, tradisi, adat, dan bentang alam.
Para perempuan yang telah ‘membantu’ kota ini tumbuh.

‘Bangsal’ dan Katering
“Di kampung, penghasilan sama sekali tidak ada,” keluh Upa pada saya.
Upa seorang ibu berusia 39 tahun. Di Dumpu, sebuah dusun di Kajang–kampung asalnya–ibu dua anak itu punya beberapa kebun. “Tapi sudah semua mi dijual,” Upa bercerita.
“Saya tanami jagung, tapi nda cukup. Hasilnya hanya berapa ton. Suami saya capek-capek kerja. Ongkos besar, sementara penghasilannya kecil,” Upa mencelupkan tangannya yang penuh debu semen ke baskom berisi air.
“Rugi ki!”
Kami berjumpa pada awal Mei 2024, di sebuah kawasan proyek pembangunan perumahan subsidi, di Moncongloe, Kabupaten Maros, belasan kilometer dari pusat Kota Makassar. Di sini, Upa jadi seorang buruh bangunan, dengan upah Rp 120 ribu per hari.
Upa telah bekerja sembilan hari, saat saya menemuinya. Dia ikut proyek borongan milik pamannya. Di kompleks ini, Upa tinggal di sebuah gubuk berdinding tripleks, dibangun per petak dan berderet di balik rumah-rumah batu yang sedang dibangun. Di gubuk itu para buruh beristirahat dan tidur.
Para buruh menamakan gubuk-gubuk mereka itu sebagai ‘bangsal’.
Dukung kami
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Selama masa proyek, Upa tak meninggalkan tempat itu kecuali akhir pekan, hari dia akan libur dan telah mengantongi upahnya. Akhir pekan kemarin, Upa pulang ke rumahnya, di Borong, satu kelurahan terpadat di Manggala, kecamatan paling timur Kota Makassar.
Keluarga Upa menempati rumah yang sejak akhir 2020, dia bangun dari hasil seluruh kerja serabutannya dan upah per bulan suaminya sebagai supir truk sampah. Terletak di sebuah pemukiman, salah satu tempat gelombang perantauan dari Kajang bermuara.
Kota Makassar bagai magnet. Pusaran ekonomi yang berusia ratusan tahun telah merayu orang-orang dari pelosok Sulawesi Selatan, bertaruh nasib di kota ini. Setidaknya Kota Makassar telah jadi muara gelombang perantauan sejak era kolonial.
Tahun-tahun kemudian, Makassar berubah jadi kota metropolitan dan kini menyatakan dirinya sebagai Kota Dunia! Setiap sudut muncul kantong-kantong ekonomi, menjadi tumpuan mimpi bagi perantau.
Sebelum Tahun 2000, banyak Orang Kajang memulai gelombang perantauan ke Kota Makassar, sebagai kuli bangunan yang telaten dan bekerja sebagai awak truk sampah dengan gaji di bawah upah minimum kota. Mereka yang telah di Makassar mengajak sanak keluarganya datang dan mencoba peruntungan bersama.
Di sini, mereka menjalin keakraban dan menempati suatu wilayah dan membentuk semacam ‘perkampungan.’ Bersebaran di pinggiran kota, tempat di mana biaya hidup tak menguras seluruh upah mereka.

Di Borong, tempat Upa tinggal, dulunya dipenuhi sawah, yang perlahan-lahan berubah jadi pemukiman padat. Upa menebus tanah yang dia tempati seharga Rp100 juta, patungan bersama sepupunya.
Pada Tahun 2000, ketika usia putra sulungnya belum genap setahun, Upa bersama suami dan anaknya merantau. Mereka mengontrak sebuah rumah di belakang Kantor Camat Panakkukang. Upa lekas bekerja sebagai tukang bangunan. Dari tukang aci tembok, cat, hingga aduk semen. Dari sebuah rumah hingga sebuah gedung yang telah berdiri di kawasan elit.
Kini, anak sulung itu telah besar. Dia menemani ayahnya menjemput sampah-sampah warga Makassar menuju Tempat Pembuangan Akhir.
Dan, baru-baru ini Upa menggeluti usaha katering, bersama kawannya.
Pertemuan pertama kami terjadi di depan rumahnya. Upa, dengan baju terusan menenteng kantongan bahan-bahan makanan. Dia baru saja pulang dari pasar.
Hari itu, Upa harus segera pergi. “Besok baru kita ketemu,” kata dia. “Saya mau pergi dulu. Teman saya sudah menunggu.”
Baca tentang migrasi Orang Kajang ke Makassar:

Dari Tani, ke Pabrik, Menjadi Kuli
Sore terik, 30 April lalu, sebelum perjumpaan saya dengan Upa, saya berkunjung di sebuah kampung para perantau Kajang, di Kelurahan Borong–tempat Upa bermukim. Truk-truk sampah berjejal di tepi jalan. Di sebuah persimpangan saya bertemu sekelompok ibu.
Saya singgah dan mematikan mesin motor.
“Permisi, Bu,” saya menundukkan badan. “Mau bertanya. Di mana di sini tinggal Orang Kajang?”
“Saya orang Kajang,” balas seorang ibu.
“Ini juga Kajang,” menunjuk ibu di sampingnya dan menunjuk ibu yang lain yang memangku anaknya. “Itu juga orang Kajang.”
Tiga ibu itu bernama Rosma, Mega, dan Hadrawati.
Rosma berusia 44 tahun, seorang ibu tamatan Sekolah Menengah Atas. Dia pertama kali tiba di Borong, di tahun 1996, bersama keluarganya setelah lulus dari bangku sekolah.
“Orang tua jual rumah di Kajang, lalu beli rumah di sini,” Rosma mengenang.
Ketika tiba, Borong masih lah sebuah hamparan rawa-rawa, dengan lusinan rumah yang menjulang. “Kalau banjir itu naik perahu. Pete-pete (Angkutan Umum–Angkot) itu belum bisa sampai di sini,” jelas Rosma.
Sedekade kemudian, sebagian rawa-rawa itu berubah jadi hamparan sawah, yang kini telah menjadi pemukiman dan tanah yang lapang.
Dua tahun setelah Rosma mencapai kota ini, Hadrawati merantau ke Makassar, saat umurnya masih 15 tahun, meninggalkan Maccini, kampung kelahirannya di Kajang.
Di kota ini, Hado–nama sapaannya, tinggal bersama Kakaknya, di bilangan Jalan Andi Pangerang Pettarani. Hado mengawali kisah perantauannya dengan bekerja di Kawasan Industri Makassar sebagai buruh pabrik, menggantikan kakaknya yang berhenti.
Tujuh tahun, Hado bekerja sebelum akhirnya menikah bersama seorang laki-laki asal Bontonompo, Kabupaten Gowa.
“Tahun 2011, saya pindah ke sini,” Hado melempar telunjuknya ke segala arah. “Waktu awal tiba di sini masih banyak sawah.”
“Dulu hanya enam jutaan, kita sudah dapat tanah,” tutur Hado dalam Bahasa Konjo, salah satu bahasa rumpun austronesia yang menyebar di Selatan Sulawesi.
Bertahun-tahun kemudian, kampung itu kian padat. Orang-orang sesama asal Kajang berpindah ke Borong. Berharap ikut menikmati keajaiban ekonomi sebuah kota metropolitan.
Selepas berhenti bekerja di pabrik, Hado memulai kerja bangunan sebagai tukang plamir tembok bersama suaminya, yang juga bekerja sebagai tukang cat.
Hado mendapat panggilan kerjaan itu dari mulut ke mulut. Dari sekian ajakan dan serangkaian perkenalan. Para tetangga–sesama dari Kajang, takjub dengan hasil kerja Hado.
“Kadang itu juga ada temannya tetangga, bilang Hado saja panggil karena bagus caranya,” kata Hado.
Mega memegang tubuh anaknya, menyimak cerita Hado dari tadi.
Mega juga tukang bangunan. “Kalau tidak kerja bangunan, kita pergi potong padi.”
Mega tiba di kampung ini, pada 2017 setelah menikah dan ikut bersama suaminya merantau ke Makassar, yang bekerja sebagai petugas kebersihan.
Di kota ini, Mega belajar satu hal: mencari nafkah tak pernah selalu mudah.
Dia harus bekerja meski sedang mengandung. Sejak pagi hingga sore hari. “Tapi kadang tergantung maunya kepala tukang.”
Mega diupah Rp80 ribu per hari. “Mandor kadang tidak jujur, karena sudah tidak ada uang dia pegang,” Mega mengeluh.
Hado ikut bicara. “Kadang itu mandor bikin gaji kita menunggak. Kadang malah tidak ful gajinya, dipotong sama mandor.”
Mega dan Hado tidak lagi jadi kuli bangunan. Mega berhenti karena mengandung anak kedua dan ingin mengasuh anak-anaknya yang masih kecil. Hado berhenti sejak tahun 2017. “Sudah tidak lagi mampu bekerja seperti itu.”

Passolo’
Di lokasi proyek tempat Upa bekerja, saya bertemu Ida, seorang Ibu berusia 31 tahun. Di sini, Ida tinggal di salah satu ‘bangsal’ bersama suaminya. Sudah dua tahun, Ida telah hidup di perantauan, dari lokasi proyek satu ke proyek lainnya. “Tapi saya kadang pulang. Apalagi kalau ada acara di kampung. Pasti pulang.”
Ida sebetulnya sudah punya dua anak, yang dia titip ke orang tuanya jika sedang bekerja. Selain bekerja jadi buruh bangunan, Ida juga kerja jadi buruh tani. “Kalau selesai musim panen, kerja begini lagi. Kalau musim menanam padi, kami baru pulang kembali ke kampung.”
Ida tak punya pilihan selain bekerja seperti ini. Ida tak punya seinci lahan untuk berkebun dan berharap menikmati hasilnya dan dia mesti membalas passolo’, sumbangan uang yang dia terima ketika menggelar hajatan.
Kata Ida kebanyakan Orang Kajang, merantau karena mencari ‘uang passolo’, yakni uang sumbangan yang diberikan sanak keluarga ketika hajatan untuk merayakan siklus hidup: lahir hingga nikahan. “Itu uang passolo’, Rp100 ribu itu saja kurang.”
“Pokoknya kalau di kampung, semua acara harus massolo, biar bukan pesta pernikahan.”
Ida melansir beberapa ritual adat yang menyaratkan uang sumbangan, serta rata-rata nominal rupiah yang harus dikeluarkan. “Acara akikah, pesta adat kalomba, pernikahan, maddangan (peringatan 100 hari orang yang telah meninggal), mangurut (tujuh bulanan kehamilan), dan masih banyak lagi,” kata Ida.
“Kalau saudara itu sekitar Rp10 sampai Rp20 juta ke atas, dan keluarga jauh minimal Rp200 sampai Rp500 ribu ke atas.”
Abdurrahman Abdullah, dari Forest and Society Research Group (FSRG) Universitas Hasanuddin, mengatakan mahalnya biaya ritual seringkali memaksa orang-orang yang hidup miskin untuk menggadai lahan dan pada beberapa kasus tertentu, mereka tak mampu menebusnya. Memutus akses lahan dan membuat perpindahan lahan yang luas ke segelintir orang berpunya. Para pemberi utang.
Temuan ini jamak ketika Abdurrahman meneliti di Kajang, berbulan-bulan untuk Sekolah Rakyat Petani Payo-Payo, sebuah Organisasi Non-Pemerintah yang berfokus pada isu pedesaan dan perubahan iklim.
“Tidak adanya akses terhadap lahan ini yang bikin eksodus orang-orang Kajang jadi buruh tani di perkebunan tebu Takalar, buruh tani cengkeh di Kolaka, burun panen sawit di Kalimantan dan Malaysia, dan jadi buruh bangunan di berbagai daerah,” katanya.
“Dari sini kita bisa tahu kenapa ada kelompok yang akhirnya menjadi prekariat.”
Penumpukan lahan di tangan segelintir orang menurut Abdurrahman, juga terjadi karena ada penyingkiran bagi orang-orang terhadap tanah giliran, yang semestinya dapat diakses oleh warga tak berpunya lahan.
Konsentrasi kepemilikan lahan yang luas oleh segelintir orang, kelompok, atau perusahaan, kata Abdurrahman telah mengakibatkan masyarakat lokal, terutama anak muda, tidak lagi punya akses terhadap lahan. Membuat mereka mencari alternatif lain demi memenuhi kebutuhan hidup, seperti pakkampas, sebuah tren baru di Kajang, di mana segelintir anak muda meninggalkan pertanian.
Pakkampas adalah praktik bisnis menjual barang grosir ke pedagang campuran di berbagai daerah, menggunakan mobil bak terbuka atau tertutup. Seringkali, pakkampas menempuh perjalanan hingga menyeberangi provinsi.
Banjir, longsor, dan kekeringan, yang merupakan dampak dari perubahan iklim, juga menurut Abdurrahman telah membuat produktivitas pertanian menurun atau bahkan gagal panen.
Kondisi inilah yang mendorong situasi ekonomi masyarakat yang telah lama bergantung pada pertanian, terutama bagi petani gurem berada di tepi jurang.
***
Sejak pagi, saya bersama Ida dan Upa, di lokasi proyek. Ida sedang mengerjakan plesteran rumah kedua. “Saya baru mulai mengaci. Dulu itu bantu-bantu tukang mencampur pasir, ambil batu,” kata Ida sembari menempel adonan semen ke tembok.
Upa muncul dari balik rumah. “Punna pakunjomi nai’,” Upa menunjuk Ida. “Dodongmi nyahaku ku sa’ring, tala ku kullemi,” Upa mengeluh. (Kalau sudah seperti itu di atas, saya sudah merasa lelah, saya sudah tidak bisa).

Upa melanjutkan. “Injomi pangambikang, apalagi maengnga dabbung. Selalu na goyang tangan, nda ada istirahat.” (Itu lagi memanjat, apalagi saya pernah jatuh. Tangan harus selalu bergerak, tidak ada istirahat).
Ida tertawa. “Memang tidak ada istirahat kalau kerja begini.”
Pada tengah hari, Ida dan Upa mulai bebersih diri. Menghilangkan debu semen yang menempel pada sekujur tangan dan kakinya. Upa dan Ida pamit. Mereka kembali ke bangsal masing-masing untuk istirahat siang.
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi Bollo.id dan Project Multatuli untuk direktori Jendela Perempuan Adat.
Editor: Agus Mawan W