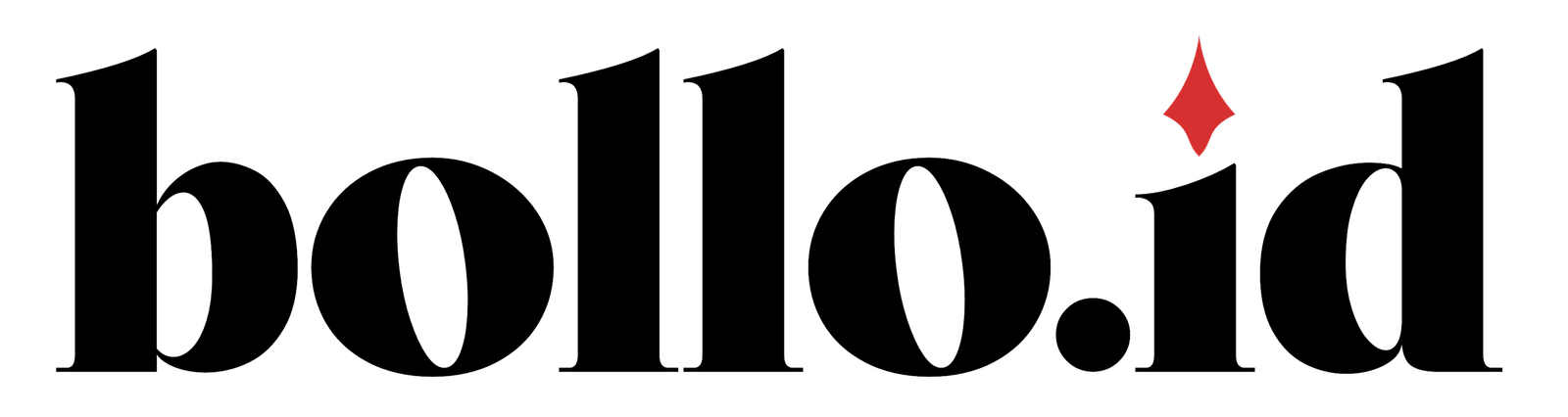Setiap musim panen, Orang-Orang Oetimu berbondong-bondong ke Toko Subur. Mereka menukarkan hasil buminya: Lima liter jagung bisa ditukar dengan seliter beras. Tiga junjung singkong bisa ditukar dengan dua bungkus mie instan lezat. Jika ditambah sebakul kacang-kacangan, bisa mendapat satu butir telur.
Mereka rela berjalan kaki berkilo-kilo meter untuk masa-masa yang ditunggu itu. Lalu setelah melakukan transaksi yang membanggakan tersebut, mereka akan pulang dengan kegirangan.
Cerita di atas adalah penggalan dari novel Orang-Orang Oetimu, karya Felix K. Nesi. Oetimu adalah sebuah desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di novel terbaik 2021 menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi itu, Oetimu digambarkan sebagai sebuah wilayah terpencil dan terbelakang.
Meski cerita di atas hanya fiksi, tetapi kenyataannya benar-benar terjadi di Indonesia. Di media sosial, berseliweran konten-konten yang menggambarkan hal serupa.
Konten-konten barter makanan di media sosial itu mendapat interaksi yang bagus di dunia maya. Media mainstream bahkan turut mereproduksi konten tersebut. Namun bagai bara dalam sekam, konten tersebut sebenarnya problematik. Selain karena ia kerap kali didramatisasikan dengan narasi-narasi memilukan, ia juga berperan penting membuat praktik penjajahan pangan atau gastro kolonialisme tumbuh subur di Indonesia.
Dukung kami
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Apa Itu Gastro Kolonialisme?
Istilah gastro kolonialisme atau penjajahan pangan pertama kali diperkenalkan oleh Craig Santos Perez. Seorang peneliti sekaligus aktivis asal Pasifik-Guam. Ia menggunakan istilah itu untuk menggambarkan bagaimana perubahan pola konsumsi yang terjadi pada masyarakat lokal di Hawaii, akibat impor massal dari berbagai olahan murah yang terus-terusan diproduksi oleh perusahaan multinasional. Alhasil, produk itu menjadi kebutuhan baru.
Di Indonesia sendiri, penjajahan pangan bisa dilacak sejak Belanda menetapkan domain “Bumi Cenderawasih” tanah Papua, khususnya Merauke sebagai pusat pertanian dan peternakan (1974), rice bedrijf atau perusahan padi dan sistem irigasi untuk menghidupi sawah-sawah, gencar dilakukan untuk kepentingan Belanda.
Setelah Indonesia mengambil alih Papua dari tangan Belanda, praktik ini tak serta merta hilang begitu saja. Setidaknya, kita dapat melihat ada tiga faktor penting dalam praktik gastro kolonialisme atau penjajahan pangan pada masyarakat lokal Papua.
Pertama, kebijakan pemerintah secara periodik seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), dan Food Estate atau lumbung pangan. Kedua, hadirnya para transmigran.
Dua proyek ini membuat Papua sebagai objek gastro kolonialisme. Politik beras menjauhkan penduduk lokal dari makanan khasnya–yang tersedia di lahan mereka. Di saat yang bersamaan, makanan olahan instan makin mendekat, kondisi itu lalu dikukuhkan dengan faktor ketiga, peranan media.
Baca essay lainnya:
Peran Media
Akun TikTok @wikeafrilia, dalam salah satu unggahannya pada (26/3/2023), menggambarkan seorang anak Papua bernama Nelis Besakin, jauh-jauh datang ke rumahnya dengan membawa segenggam sayur dan sebuah jantung pisang yang hendak ia tukarkan dengan mi instan. Pemilik akun lalu dengan senang hati memberinya lebih, karena “seharian dia menahan lapar karena tidak ada makanan” tulisnya dalam video.
Potongan kalimat “seharian dia menahan lapar karena tidak ada makanan” jelas-jelas adalah dramatisasi yang berlebih.
Pembingkaian konten seperti ini tak hanya mendulang empati warganet yang ikut menonton, tetapi juga seolah mengajak mereka menormalisasikan praktik gastro kolonialisme atau penjajahan pangan yang tengah dilakukannya. Lantas konten itu memikat belasan ruba suka, ratusan komentar dan nyaris seratus ribu yang membagikan.
Sialnya, konten serupa tidak hanya diproduksi oleh konten kreator. Sejumlah media mainstream ternama turut mereproduksi. Polanya, setelah konten tersebut viral di media sosial, media mainstream yang mengejar klik untuk mendulang pendapatan dari adsense Google, mereproduksinya.
Misalnya ini, lalu ini, dan ini.
Judulnya kadang diberi emot sedih dan atau menangis, atau dibumbui dengan musik yang membuat hati tersayat-sayat. Tetapi inti narasinya sama, menjual iba yang sangat-sangat tidak perlu!
Lewat produksi konten barter makanan yang dilakukan terus-menerus di berbagai media sosial, para pembuat konten sebenarnya ikut menjajah secara mental masyarakat lokal dengan olahan instan yang mereka punya. Selain menjadikan mereka sebagai objek konten (komodifikasi) belaka, para konten kreator juga membuat masyarakat lokal bergantung dengan semacam keyakinan “belum makan nasi dan mi maka belum kenyang”.
Namun disini kita tak sekedar melihat posisi konten kreator sebagai aktor tunggal dalam mengukuhkan praktik gastro kolonialisme atau penjajahan pangan itu, tapi juga warganet. Tetapi apa dasarnya?
Benarkah Warganet Ikut Menjajah?
Dalam teori resepsi Stuart Hall, seorang tokoh penting dalam Cultural Studies, ia menyebut analisis encoding-decoding begitu penting. Karena pada dasarnya teori ini berfokus kepada penerimaan khalayak terhadap informasi dari media.
Menurut Stuart Hall, proses pemaknaan pembaca (decoding) pada informasi yang ia terima (encoding) bergantung pada latar belakang dan pengalaman hidup (worldview) khalayak itu sendiri. Proses pemaknaan pembaca ini bisa dilihat dari tiga kemungkinan posisi dalam teorinya yakni, posisi dominan, oposisi, dan negosiasi.
Pertama, posisi dominan adalah hasil interpretasi pembaca terhadap isi konten selaras dengan maksud encoding. Kedua, posisi oposisi merupakan pengecualian. Pembacaan ini didasarkan pada gugatan kritis mengenai maksud isi media dari encoding. Ketiga, posisi negosiasi di mana pembaca menerima sebagian dan menolak sebagian maksud encoding karena alasan tertentu.
Misalnya, awal tahun 2024, seorang koki sekaligus konten kreator, Bobon Santoso mengumumkan sebuah program ekspedisi Kuali Merah Putih. Sebuah perjalanan yang dilakukan untuk memasak dengan porsi besar di 38 provinsi di Indonesia. Program ekspedisi ini dia proyeksikan dengan memakan anggaran Rp5 miliar dengan estimasi waktu dua atau tiga tahun. Dimulai dari Merauke lalu berakhir di Sabang.
Bobon memulainya di wilayah yang berada di Papua. Tiap titik dia memasak, Bobon konsisten mendokumentasikannya lalu diunggah di media sosial. Baik YouTube, Instagram, maupun TikTok. Di YouTube, tiap episode berdurasi 20 sampai 40 menit. Di Instagram dan TikTok, kontennya diunggah dengan format video yang dipotong seperti cuplikan.
Dalam sebuah kontennya di Youtube umpamanya, Bobon, masih dalam ekspedisi Kuali Merah Putih 02 yang diberi judul “Papua Berdiri di Atas Emas, Berjalan Tanpa Alas” agaknya berhasil dibanjiri komentar belasan ribu yang tak lain hanya berisi puji-pujian terhadap aksi heroik lelaki asal Bali itu. Contohnya bisa dilihat beberapa komentar di bawah ini:
“Gak kebayang ribetx ngurus ijin, biaya yang besar, melibatkan banyak pihak, keamanan yang tidak stabil. Gila keren bangetlu bon. Lanjutkan, GBU,” tulis warganet @betibeti-kp5yv.
“Harusnya di tahun 2024 channel Bobon Santoso mendapatkan penghargaan “YOUTUBER TERBAIK,” ucap @ferdiansyah1718.
Komentar apresiatif di atas nyatanya sudah mengklasifikasikan posisi warganet sebagai bagian dari decoding yang berada dalam posisi dominan. Yang terbentuk karena kesamaan pemaknaan (worldview) terhadap masyarakat Papua, yang tertinggal, terjauh, dan terbelakang (3T). Makanya praktik serupa rata-rata dianggap absah, wajar, normal, benar, serta taken for granted (tak perlu dipertanyakan lagi).
Praktik gastro kolonialisme atau penjajahan pangan lewat warganet pun juga bukan sekedar dilihat komentar-komentar apresiatif itu. Mengapa demikian? Perhatikan komentar-komentar di bawah ini:
“Buat teman-teman jgn lupa ya beli produk tango karena dari situ juga kita sedikit menyisihkan rezeki buat saudara saudara kita yg ada di pelosok pelosok, terima kasih buat koh bobon dan support dari tango, semoga banyak masuk support dari pihak lain, doanya semoga semuanya menjadi berkah bermanfaat dan berjalan lancar, aamiin,” tulis @muhammadyudarifani1210.
“Tango beli banyak sama ja kita amal buat warga Papua,” tambah @lalilulelo39.
Seruan atau ajakan beli wafer Tango yang mensponsori Kuali Merah Putih itu sebetulnya tak berhenti di situ. Ajakan ini bisa jadi berbuntut pada aksi langsung pembelian produk-produk olahan instan yang tersedia di kota-kota, lalu dibagikan secara gratis kepada masyarakat lokal Papua.
Meski kelihatannya optimisme warganet untuk membantu program Kuali Merah Putih, tetapi ajakan tersebut mengidentifikasikan bahwa sebagian besar warganet juga ikut melibatkan diri untuk mendukung sekaligus mengukuhkan praktik penjajahan pangan ini, bukan?
Kembali ke teori resepsinya Stuart Hall, di luar kolom komentar, posisi oposisi datang dari Dicky Senda, seorang sastrawan yang juga mengasosiasikan dirinya sebagai aktivis pangan. Dalam unggahan instagramnya, dia menyentil program ekspedisi Kuali Merah Putih yang diinisiasi Babon dengan istilah gastro kolonialisme atau penjajahan pangan. Asumsinya sebagai pihak decoding terjadi karena pembacaan kritis atas praktik-praktik yang sebenarnya hanyalah memperkeruh berbagai masalah laten di Papua, yang sampai sekarang menjadi tugas pemerintah.
Tapi Dicky hanya bagian kecil yang berada di posisi oposisi. Dia kalah telak dengan sebagian besar pendukung yang berada dalam posisi dominan yang membludak di kolom komentar, yang sepenuhnya mendukung kerja-kerja “kemanusiaan” Bobon atas programnya itu. Bagaimana tidak, selain warganet, narasi yang dibangun Bobon juga diperkuat oleh sejumlah influencer lain sebagai pihak decoding.
YouTuber yang juga mentalis kawakan, Deddy Corbuzier meminta Bobon untuk keukeuh pada apa yang dia lakukan. Tak saja mendengar kritik dari orang-orang seperti Dicky Senda. Deddy bahkan mengundang Bobon dalam podcast di YouTubenya. Di sana, Bobon bercerita soal aktivitasnya di Papua hingga meneteskan air mata.
Nonton video explains Bollo.id
Menjajah dengan Gaya Baru
Jika dicermati, perubahan pola konsumsi di Papua dan di Oetimu, seperti di novel nyaris tidak ada bedanya. Orang-Orang Oetimu tidak punya sawah, tetapi makanan pokok mereka adalah nasi. Mereka dominan peladang, menanam jagung dan singkong di ladangnya. Tapi kebanyakan mereka merasa malu untuk makan jagung dan singkong, kadang perut mereka sakit sebab telah terbiasa makan nasi.
Makan nasi jadi budaya baru di Oetimu sejak sebuah mobil milik pemerintah yang dilengkapi pelantang suara, bertahun-tahun masuk ke kampung itu. Mengumumkan narasi yang sama dengan berulang-ulang: Makan jagung dan singkong buat orang bodoh, dan untuk jadi pintar dan berbudaya, tiap orang harus makan nasi.
Toh, fungsi mobil dengan pelantang suara itu, perannya mirip dengan konten Bobon, Wike dan yang serupa yang tersebar di media sosial. Jika dulu gastro kolonialisme atau penjajahan pangan itu dikukuhkan dengan mobil pelantang suara yang mengkampanyekan komoditi seperti beras dan jagung di kampung-kampung, kini cukup lewat media. Sebuah gaya baru dalam menjajah.
Editor: Agus Mawan W
Nonton Podcast Bollo.id