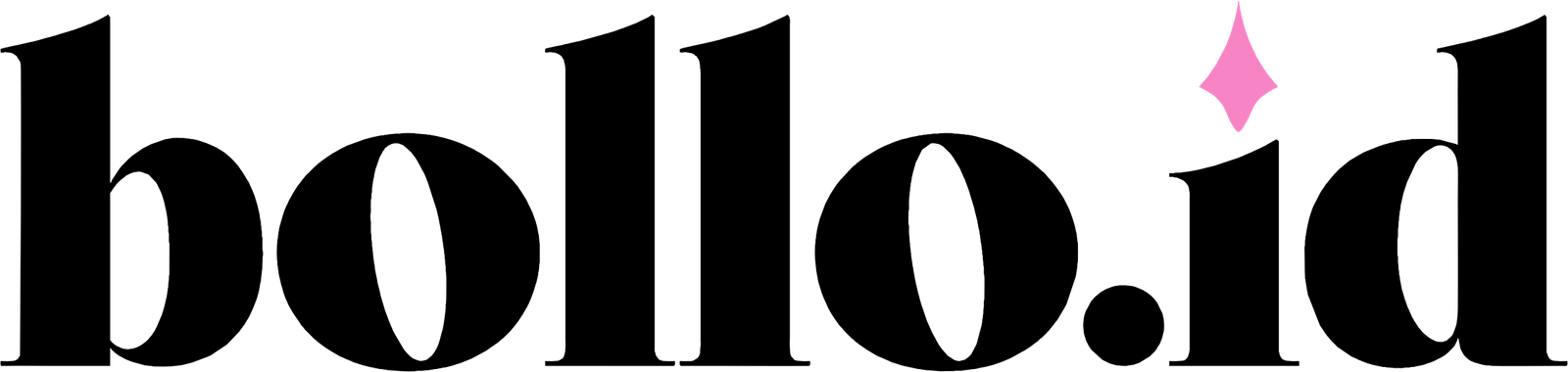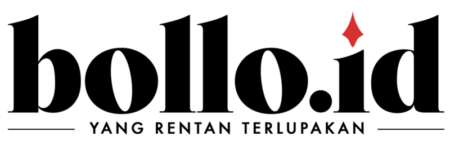Pada 2007, sebuah buku berjudul Shock Doctrine menjadi perbincangan penting. Buku ini terbit tiga tahun setelah bencana tsunami hebat menghantam Aceh, dan beberapa wilayah di Asia. Media-media silih berganti mengulas buku itu dan mewawancarai penulisnya, Naomi Klein, seorang penulis dan aktivis asal Kanada. Buku ini seperti melucuti topeng lembaga-lembaga bantuan internasional yang selalu tampil dengan wajah kemanusiaan.
Klein membongkar muslihat para kapitalis yang disokong oleh Amerika Serikat di balik bantuan bencana untuk memuluskan jalan neoliberalisme di tempat-tempat yang dilanda bencana. Dengan tanpa malu, mereka meraup laba dari kehancuran para korban bencana.
Buku ini menunjukkan, bahwa bantuan kemanusiaan tidak bebas dari kepentingan politik ekonomi.
Bantuan-bantuan internasional untuk pembangunan mengalir setiap tahun ke negara-negara miskin atau berkembang seperti Indonesia, bukan hanya ketika ada bencana. Urusannya macam-macam, dari menangani krisis iklim, krisis ekologi, pemberdayaan masyarakat sampai persoalan ketimpangan gender. Barangkali sebagian masyarakat, aktivis dan pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat, berharap bantuan tersebut bisa menjadi semacam solusi dari berbagai masalah yang timbul akibat salah kebijakan, kejahatan struktural, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis lingkungan.
Dukung kami
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Bagaimana lembaga-lembaga donor itu bekerja?
Saya akan menyempitkan pembicaraan ini ke persoalan hutan, dan lingkungan hidup.
Mari kita lihat hasil penelitian Karno B. Batiran dalam disertasinya yang berjudul Ekologi Politik Solusi Lingkungan di Indonesia; Aktor, Kepentingan, dan Relasi Kuasa. Karno bekerja sebagai peneliti di Forest and Society Research Group yang berdomisili di Makassar.
Ia meneliti proyek-proyek lingkungan hidup yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga donor internasional di Berau, Kalimantan Timur.
Di Berau, proyek lingkungan isunya mengikuti trend pendanaan, Ketimbang isu nyata yang dihadapi oleh masyarakat setempat; para penerima manfaat. Di tempat lain, kemungkinan juga begitu. Lembaga donor menciptakan trend isu. Setidaknya dalam dua dekade terakhir, isu yang berkembang, antara lain; keanekaragaman hayati, perubahan iklim, mangrove, karbon, perhutanan sosial, ekowisata dan sawit lestari.
Pendanaan untuk isu-isu tersebut termasuk dalam skema besar di atas USD 10 juta dan dalam jangka waktu panjang, setidaknya lebih dari 10 tahun. Proyek tersebut dibuka dalam beberapa siklus. Setiap siklus berlangsung 2 tahun, paling lama 4 tahun.
Dalam dua dekade terakhir, lembaga-lembaga donor dan lembaga perantara yang beroperasi di Berau, antara lain, TNC/YKAN, TFCA Kalimantan (USAID Amerika Serikat), MCAI (Amerika Serikat) dan Forclime (GIZ Jerman). Mereka tergabung dalam Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), membela perusahaan sawit, dengan isu sawit lestari. Dana mereka sebagian dari Kerajaan Inggris, lainnya dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan RSPO.
Lembaga donor menjalankan proyeknya dengan menggandeng LSM lokal dan menempatkan mereka sebagai subordinasi.
“Mereka sudah merancangnya, dan memutuskannya, entah di Amerika, entah di Eropa, sebelum membawanya ke desa-desa di sini,” kata Karno, saat membawakan hasil risetnya di sebuah kelas diskusi di Universitas Hasanuddin, Jumat, 6 Agustus, lalu.
“LSM lokal hanya melaksanakan apa yang sudah mereka rancang.”
Baca:
Di sektor kehutanan dan lingkungan, sama dengan sektor lain, skema bantuan berjalan melalui hubungan multilateral, bilateral dan swasta. Di Indonesia, setelah pembangunan demokrasi dan pengentasan kemiskinan di awal tahun 2000 an, saat ini sektor lingkungan hidup paling menyita perhatian, dan paling banyak mendapat bantuan dana internasional. Secara global, Indonesia berada di urutan keempat sebagai negara dengan laju kehilangan hutan, setelah Brazil, Congo, Bolivia. Pada tahun 2020 saja, Indonesia kehilangan hutan tropis primer sebanyak 270 ribu hektar.
Karno meneliti proyek Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, rumah terbesar kedua bagi hutan tropis, setelah Papua. REDD+ merupakan skema insentif keuangan dalam rangka upaya mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, usaha mereka mencakup kegiatan konservasi hutan, demi meningkatkan penyerapan karbon. Indonesia penyumbang gas rumah kaca terbesar ketujuh setelah China, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Rusia dan Jepang.
Faktor yang mempengaruhi dalam menentukan negara penerima donor, bukan hanya persoalan seberapa besar kerusakan lingkungan yang terjadi di negara itu, tapi ditentukan juga oleh hubungan dagang, tingkat demokrasi, dan kandungan sumber daya alam di negara tersebut.
Akan tetapi, benarkah rancangan program yang mereka bikin, bisa mengatasi krisis ekologi yang sedang berlangsung?
Dalam penelitian ini, proyek REDD+ itu telah gagal, setidaknya dalam satu dekade terakhir. Dalam laporan-laporan evaluasi proyek yang dikeluarkan oleh Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Kalimantan dan Yayasan Kehati, kedua lembaga yang menjalankan proyek di Berau; “Secara umum, tidak ada penurunan emisi di tingkat kabupaten agregat maupun di wilayah intervensi dengan menggunakan pendekatan FREL (Forest Reference Emmisiion Level) dan Forest Carbon Partnership Fasility (FCPF.) Hal ini disebabkan oleh laju deforestasi yang lebih tinggi dibandingkan periode referensi. Namun Kabupaten Berau baik secara keseluruhan maupun khususnya di wilayah intervensi mitra TFCA Kalimantan, berhasil menurunkan emisi akibat degradasi hutan, walaupun secara agregat tidak ada penurunan emisi.”
Penyebabnya, intervensi yang salah arah dan mengabaikan tiga hal yang berpengaruh besar terhadap konversi hutan dan ekstraktif, yaitu, industri kayu, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit yang menguasai lebih dari separuh wilayah Kabupaten Berau.
“Alih-alih mengatasi kerusakan hutan dan menelusuri penyebabnya, REDD+ malah sibuk memberdayakan masyarakat adat,” ujar Karno. Di hutan Berau tinggal masyarakat adat, Dayak Mapnan. Mereka menggantungkan hidupnya di hutan. Berladang, meramu, berburu.
“Mereka menuding masyarakat sebagai sumber penyebab kerusakan hutan,” ujarnya. Padahal masyarakat Suku Mapnan telah lama hidup di dalam hutan dan mempraktikan ladang berpindah-pindah mengikuti siklus alam yang mereka ketahui. Pada musim hujan, mereka menanam padi untuk keperluan sehari-hari, sementara saat kemarau mereka berburu dan memetik buah di hutan, serta memanen madu.
Para pegiat LSM yang menjalankan proyek ini mengarahkan Suku Mapnan untuk menetap, dan “dipaksa” membudidayakan tanaman komersial seperti karet, kopi dan kakao serta pola hidup “sedentary” lainnya. Padahal sudah banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa ladang berpindah baik untuk ekologi. Bagi Suku Mapnan, ladang bekas padi mereka akan mengalami bera jangka panjang dan kembali menjadi tutupan setelah ditinggalkan. Dengan demikian, mereka hanya menanami satu lahan untuk satu periode.
Tanaman jangka panjang seperti kopi dan kakao malah akan mengeluarkan ladang tersebut dari daftar rotasi ladang berpindah, karena ladang bekas kopi dan kakao tidak bisa mereka tanami padi. Ini malah akan memperluas pembukaan lahan, karena mereka harus mencari lahan lain untuk ladang berpindah.
Tapi di luar itu, mereka bukanlah peng-konversi lahan terbesar. “Dalam kenyataannya, yang melakukan deforestasi skala besar sebenarnya korporasi-korporasi yang bergerak di tiga sektor itu yang mereka klaim menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi,” kata Karno, merujuk pada perusahaan kayu, tambang dan perkebunan sawit.
Tapi pihak-pihak di Kabupaten Berau, LSM-LSM lokal dengan arahan donor lebih sibuk mengarahkan masyarakat lokal yang tinggal dalam hutan agar tidak melakukan deforestasi dan merehabilitasi lahan dengan memaksakan program REDD+ kepada mereka. Inilah yang mereka sebut “pemberdayaan”.
“Pemberdayaan ibarat mantra,” seloroh Karno. Lagi pula, kata dia, “Jika dibandingkan dengan korporasi, daya rusak mereka atas hutan tidak seberapa.”
Dalam penelitian ini, lembaga-lembaga donor menggunakan pendekatan konservasi neoliberalisme atau solusi berbasis ekonomi pasar. Celakanya, pilihan ini merusak lingkungan itu sendiri dan berpotensi menyingkirkan masyarakat lokal atau adat. Mekanisme konservasi berbasis pasar akan mendorong solusi lingkungan ke dalam transaksi pasar. Misalnya, perdagangan karbon.
Negara-negara maju menyuruh negara-negara tropis seperti Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan menghisap karbon yang mereka emisi dari praktik bisnisnya, lalu dihitung berapa karbon yang bisa dimitigasi dari praktik menjaga hutan itu. Indonesia akan mendapat kompensasi berupa uang dari praktik menjaga hutan, sementara negara-negara maju akan tetap menjalankan bisnisnya seperti biasa dengan tetap mengemisi karbon.
Cara ini dirancang supaya orang berpikir dan bertindak menggunakan asumsi ekonomi; mencari keuntungan untuk kepentingan diri sendiri. Pendekatan ini juga akan menghilangkan peran pemerintah dalam upaya mengatasi krisis lingkungan.
Tanggung jawab dibebankan pada individu atau sektor swasta berdasarkan mekanisme pasar. Seperti pembangunan ekowisata. Beberapa kasus pembangunan ini tetap menghasilkan emisi karbon, menyingkirkan masyarakat setempat, dan mencaplok sumber daya yang menjadi sumber penghidupan warga lokal sejak lama. Sementara keuntungan dari bisnis ini mengalir ke individu atau kelompok tertentu. Risiko ekowisata juga sangat rentan menghadapi hantaman krisis ekonomi. Masyarakat setempat yang tergantung pada sektor jasa juga rentan terhadap kelangkan pangan.
Membaca kenyataan yang terjadi dalam penelitian itu, saya menemukan keterkaitannya dengan kajian ekologi politis yang ditulis Tania Li, seorang antropolog dari Universitas Toronto yang bertahun tahun meneliti dan mengkritisi praktik pembangunan di negara-negara selatan, yang didanai oleh utang atau bantuan internasional. Refleksinya ia tulis dalam artikel berjudul, Rendering Society Technical: Government through Community and the Ethnographic Turn at the World Bank in Indonesia. Bagi Li, proyek-proyek bantuan dari Bank Dunia telah menjadikan segala urusan politik yang menyangkut hak-hak dasar warga negara menjadi urusan teknis semata. Hak mendapat layanan dasar, hak mendapat akses terhadap sumber daya digambarkan sebagai isu teknis belaka, dan dengan begitu bisa diselesaikan secara teknis.
Persoalan dasar yang semestinya diselesaikan oleh pemerintah, dilempar menjadi urusan warga. Misalnya, bantuan sanitasi air bersih yang didanai Bank Dunia, program yang dinamai Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau Pamsimas. Persoalan utama program ini hanya tentang kurangnya pipa, penampungan, dan bagaimana warga menyelesaikan dan mengelola penampungan air itu. Padahal persoalan sebenarnya adalah monopoli sumber air oleh segelintir orang melalui privatisasi sumber-sumber air.
Solusi bagi persoalan ekologi politis semacam itu ialah masyarakat menggugat kebijakan privatisasi karena hak-hak warga negara telah dirampas untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Proyek-proyek ini juga telah mereduksi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan memastikan kebutuhan dasar rakyat tersedia. Bukannya melepas tanggung jawab, seakan-akan segala persoalan penghidupan hanya urusan pribadi.
Artinya, bagi Li, masalah publik telah direduksi menjadi persoalan pribadi. Pola hegemonik ini, menurutnya, sejalan dengan cita-cita ekonomi liberal: serahkan semua pada pasar.
Baca: Menginterogasi Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Agraria
Para aktor yang terlibat dalam program ini ibarat sinterklas yang bawa paket bantuan untuk orang miskin sambil menciptakan ketergantungan. Mereka mengajari kaum miskin bahwa bantuan lain akan datang saat mereka butuh kan.
Kalau melihat polanya, dari hasil penelitian Naomi Klein, apa yang ditemukan dari penelitian Karno B Batiran, terdapat pola yang sama yaitu membuat urusan-urusan politik menjadi urusan pribadi dan kelompok, juga memperkecil tanggung jawab negara dalam urusan kebutuhan dasar rakyat, dan mengalihkannya kepada pasar. Pola ini akan memperbesar peran swasta dan menambah beban warga yang harus berhadapan dengan harga pasar yang terus melambung.
Editor: Agus Mawan W