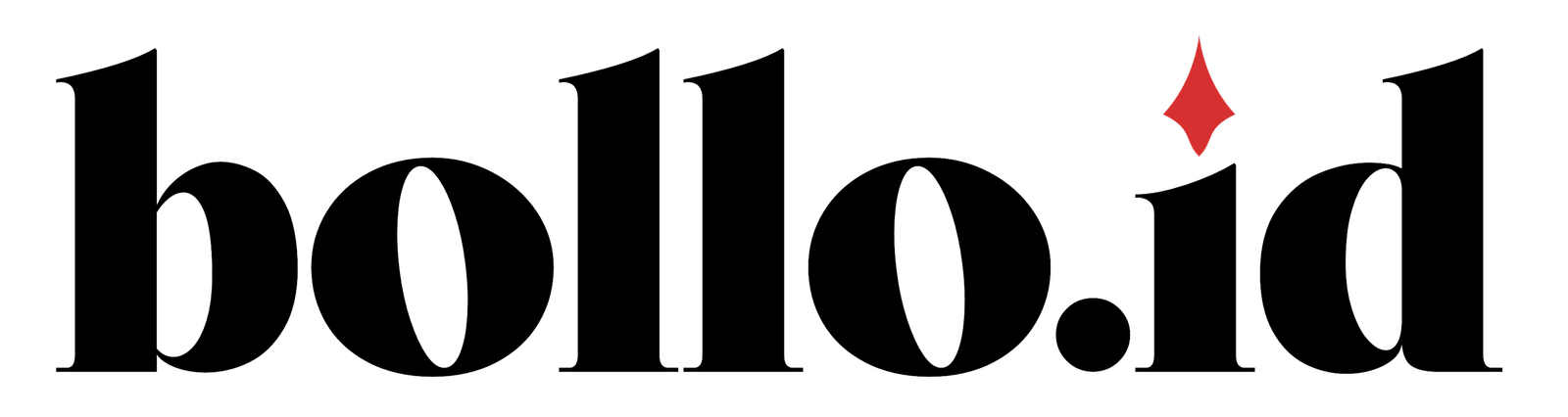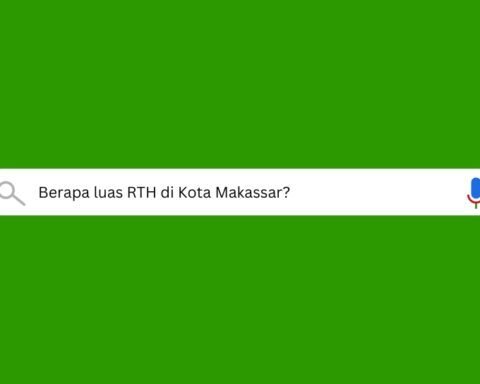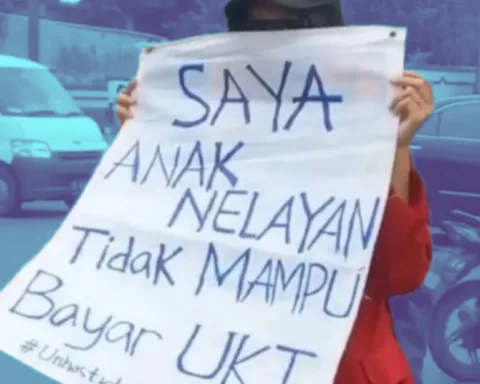Explains
“Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki,” kata Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) Periode 2024-2029 pada Minggu, 20 Oktober 2024 lalu.
Saat itu, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memperluas hilirisasi di berbagai sektor, termasuk nikel–salah satu mineral kritis yang punya cadangan besar di perut bumi Indonesia. Menurutnya, hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apa yang disampaikan Prabowo bukanlah hal baru. Sejak masa kampanye dan debat antar calon presiden, ia bersama Gibran–Wakil Presiden–seringkali menyebut hilirisasi.
Hilirisasi atau disebut penghiliran merupakan proses mengolah bahan baku dalam negeri dari bidang industri tertentu menjadi barang siap pakai sebelum diekspor. Dalam konteks nikel, seperti yang berulang kali diungkapkan Presiden sebelumnya, Joko Widodo, akan menambah nilai tambah.
Hilirisasi nikel pertama kali mencuat pada tahun 2014, ketika Joko Widodo melarang ekspor bijih nikel mentah. Presiden ke tujuh itu mau, Indonesia mengekspor nikel dalam bentuk setengah jadi.
Tampaknya, ambisi hilirisasi nikel Joko Widodo berlanjut ke pemerintahan Prabowo-Gibran–sebagaimana yang mereka sampaikan dalam banyak kesempatan ingin melanjutkan kebijakan Joko Widodo. Di antara 28 komoditi yang ditarget jadi komoditas hilirisasi di bawah Prabowo-Gibran, ada nikel. Ini naik dari jumlah target hilirisasi yang dicanangkan Joko Widodo.
Meskipun UU tentang Minerba di Indonesia tidak secara langsung mendefinisikan hilirisasi, konsep ini diuraikan melalui proses pengolahan dan pemurnian yang dilakukan di dalam negeri.
Melalui serangkaian regulasi sejak 2009 hingga 2019, pemerintah secara bertahap melarang ekspor bijih nikel. Larangan pertama berlaku sejak Januari 2014, meskipun bijih dengan kadar di bawah 1,7 persen masih diizinkan untuk diekspor pada rentang 2017 hingga 2019. Namun, sejak Januari 2020, seluruh ekspor bijih nikel telah dihentikan.
Dengan adanya pelarangan itu, pemerintah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun fasilitas pabrik smelter, yang nantinya mengolah bijih mentah menjadi barang setengah jadi. Untuk memenuhi kewajiban itu, perusahaan mengolah dan memurnikan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki fasilitas atau izin yang sesuai.
Larangan ini pula paling tidak mengundang investasi dari Tiongkok untuk membangun pabrik smelter di Indonesia, dan membuat negara ini mengalami booming nikel.
Namun, keputusan ini mendapat keluhan dari Uni Eropa yang kemudian melayangkan gugatan pada November 2019 lalu, melalui World Trade Organization (WTO), organisasi internasional yang mengatur perdagangan antarnegara.
Merespons gugatan ini, Indonesia mengajukan banding setelah panel WTO memutuskan bahwa larangan ekspor nikel Indonesia melanggar ketentuan GATT 1994. Pengajuan banding ini dikeluarkan pada 17 Oktober 2022 dan berfokus pada argumen Indonesia bahwa larangan tersebut diperlukan untuk mencegah potensi kekurangan pasokan produk esensial.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
***
Nikel pertama kali ditemukan dengan tidak sengaja oleh penambang tembaga Jerman pada abad ke lima belas. Mereka menemukan bijih coklat kemerahan yang diyakini mengandung tembaga. Tetapi bijih itu mengandung hal lain. Nikel.
Karena itu mereka mengutuk bijih-bijih itu dengan sebuah julukan: Tembaga setan.
Pada tahun 1751, Axel Cronstedt, seorang kimiawan Swedia untuk pertama kali mengidentifikasi dan mengisolasi nikel sebagai unsur, dengan simbol (Ni).

Setidaknya ada dua jenis nikel yang berserakan di planet ini. Bijih laterit terutama berlokasi di daerah tropis dan subtropis, sementara bijih sulfida terletak di daerah beriklim sedang hingga sub-Arktik.
Di Indonesia, bijih laterit lah yang paling banyak, meskipun beberapa artikel menyebut bijih sulfida terdapat di Indonesia bagian timur. Bijih laterit mengendap dengan proses jutaan tahun dengan keberadaannya yang diyakini hanya 73 persen di planet ini. Karena itu bijih jenis ini disebut langka, ditemukan di Pulau Kalimantan, lengan timur Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua.
Secara tradisional nikel laterit terdapat dua jenis utama: limonit, mengandung nikel rendah tetapi kandungan besi yang tinggi; dan saprolit mengandung nikel tinggi tetapi mengandung besi yang rendah.
Saat ini cadangan nikel di Indonesia diperkirakan mencapai 55 juta metrik ton pada tahun 2023, berdasarkan laporan dari United States Geological Survey (USGS) atau Badan Survei Geologi Amerika Serikat.
Dengan cadangan sebesar ini, Indonesia berada di urutan pertama sebagai negara penghasil nikel terbesar dunia di tahun 2023, dengan perkiraan besaran produksi mencapai 1,8 juta metrik ton dan berkontribusi 50 persen terhadap total produksi nikel global.
Menurut Kementerian ESDM, per 2023 Indonesia memiliki sumber daya nikel sebesar 18,55 miliar ton bijih dan cadangan 5,33 miliar ton.
Di Indonesia, fasilitas smelter didominasi pengelolaan bijih laterit dengan pirometalurgi, metode peleburan memakai energi batubara dan listrik melalui tungku dan rangkaian panjang. Saat ini setidaknya terdapat 147 smelter di Indonesia yang sebagian besar sudah beroperasi.
“Pirometalurgi ada 49 smelter beroperasi, 35 smelter konstruksi, dan 36 smelter dalam perencanaan,” jelas Muhammad Wafid, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, pada 3 November 2024.
“Sedangkan yang kedua, metode hidrometalurgi, ada 5 plan operasi, kemudian 3 plan konstruksi, dan 19 plan perencanaan.”
Melansir Katadata, pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan 53 unit smelter pada tahun 2024, dan 30 unit diantaranya adalah smelter nikel. Beberapa smelter masih dalam tahap perencanaan dan sebagian besar sudah beroperasi.
***
Pengolahan bijih nikel melalui serangkaian proses, mulai dari pemurnian, peleburan, pembentukan hingga produk setengah jadi yang siap ekspor. Dalam pengolahannya, ada dua cara mengekstrak bijih nikel. Hidrometalurgi dan pirometalurgi.
Pengolahan secara hidrometalurgi menggunakan larutan kimia untuk mengekstrak bijih nikel kadar rendah, menggunakan tangki atau autoklaf untuk memicu reaksi kimia pada suhu atau tekanan tertentu. Metode ini mengolah bijih nikel dengan kadar rendah–nikel limonit– salah satunya menghasilkan produk nikel untuk baterai kendaraan listrik.
Simak cerita foto soal Kawasan Industri Bantaeng: Kiamat Telah Tiba
Berbeda dengan hidrometalurgi, pirometalurgi tidak menggunakan tangki, melainkan tungku pembakaran. Metode ini mengolah bijih nikel dengan kadar tinggi–nikel saprolit– yang menghasilkan produk setengah jadi seperti nickel pig iron (NPI), feronikel, nickel matte, hingga stainless steel.
Metode ini menggunakan bahan bakar fosil, seperti batu bara, kokas, hingga kebutuhan energi listrik yang besar untuk menghasilkan temperatur tinggi.

Hilirisasi nikel di Indonesia disertai dengan jargon transisi energi. Meninggalkan kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik. Pada tahun 2027, Indonesia berambisi menjadi salah satu dari tiga produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia.
Negara ini mau sebagai pusat kendaraan listrik yang penting dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia.
Persoalannya di Indonesia, sebagian besar perusahaan pengelolaan nikel menggunakan metode pirometalurgi. Robby Irfany Maqoma, seorang Environment Editor menyorot penilaian terbaru Climate Action Tracker (CAT) mengenai kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia.
Bagi dia, Indonesia masih jauh dari cukup untuk meredam pemanasan global. Penilaian rendah ini disebabkan oleh dua faktor utama: meningkatnya penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan keberadaan PLTU captive di fasilitas smelter.
Robby menyebut PLTU captive ini menjadi petaka senyap bagi lingkungan. PLTU ini dibangun oleh banyak pabrik, terutama yang bergerak dalam pengolahan bahan tambang seperti nikel dan tembaga. Demi memenuhi kebutuhan energi, fasilitas pembangkit ini tersambung secara langsung tanpa terintegrasi dengan jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Akibatnya, perencanaan dan operasional PLTU captive sulit dipantau, berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. CAT memperkirakan emisi Indonesia akan mencapai 1.628 juta ton CO2 pada 2030, meningkat hampir 50 persen dari emisi pada tahun 2022.
Saat ini, banyak aktivitas industri nikel menyebar di wilayah Indonesia Timur. Berdasarkan laporan Auriga Nusantara, ada 24 perusahaan yang mendominasi.
Lalu bagaimana di Sulawesi Selatan?
Berdasarkan Catahu WALHI hingga akhir 2021, Sulawesi Selatan memiliki enam perusahaan industri nikel yang menguasai 87.556,4 hektar wilayah konsesi dan fasilitas smelter.
Dari total tersebut, tiga perusahaan di antaranya berada di tiga kabupaten; Luwu, Luwu Timur dan Bantaeng.
Lebih dari setengah abad, PT. Vale Indonesia Tbk. menambang di Indonesia, salah satunya di Sorowako, Luwu Timur. Perusahaan asal Brazil ini menjadi salah satu aktor utama pertambangan nikel, di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan.
Dengan kontrak karya yang berlaku saat ini, perusahaan ini beroperasi di area seluas 118.017 hektare. Mayoritas area operasinya berada di Sulawesi Selatan, dengan sebagian lainnya menyebar di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
Tak hanya PT. Vale, perusahaan milik Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke 10 dan 12 ini juga membangun smelter yang menyasar tiga desa di Kabupaten Luwu. Sampai saat ini, perusahaan ini telah melakukan pembebasan lahan seluas 400 hektare dan sedang melakukan tahap pembangunan kedua yang direncanakan tahun ini.
Menjadi anak perusahaan Kalla Group, PT. Bumi Mineral Sulawesi (BMS) berkongsi dengan Eramet, perusahaan tambang asal Perancis, yang juga sudah lama beroperasi dengan PT. Weda Bay Nickel yang ada di Halmahera, Maluku Utara.
Selain Luwu, pabrik smelter juga ada di Bantaeng, hanya berjarak belasan kilometer dari pusat kota Bantaeng.

Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2018. Di kawasan ini, ada enam pabrik smelter milik Huadi Group, perusahaan nikel asal Shanghai, Tiongkok. Pabrik-pabrik ini berdiri dekat dengan pemukiman warga. Mencemari kehidupan warga sekitar dengan semburan debu berbahaya, menurut laporan investigasi terbaru Bollo.id.
Baca laporan investigasi Bollo.id soal industri nikel di Bantaeng: Diabaikan Perusahaan, Ditinggalkan Pemerintah
Proyek ini direncanakan mencakup area seluas 3.252 hektare, yang terbagi menjadi lahan daratan seluas 3.151 hektare di enam desa dan 101 hektare wilayah perairan yang bakal direklamasi.
Dalam lima tahun terakhir, seiring lonjakan industri nikel dan adanya larangan ekspor, pada rentang 2019-2023, tren investasi hilirisasi di Indonesia terus meningkat hingga mencapai Rp375,4 triliun pada tahun 2023.
Sektor mineral menempati urutan pertama yang mendominasi investasi hilirisasi dengan komoditas nikel (Rp136,6 triliun), tembaga (Rp70,5 triliun) dan bauksit (Rp9,7 triliun). Disusul dengan sektor kehutanan, pertanian, minyak dan gas serta baterai kendaraan listrik.
Siapa yang untung?

Melansir laporan BBC, kebijakan Indonesia melarang ekspor bijih nikel sejak awal 2020 berhasil menarik investasi besar, terutama dari Tiongkok, Hong Kong, dan Singapura. Aliran dana tersebut mendukung pengembangan industri pengolahan nikel melalui pembangunan smelter dan kawasan industri.
Salah satu investasi terbesar berasal dari Tsingshan Holding Group, perusahaan Tiongkok yang berkongsi dengan Bintang Delapan Group. Dua perusahaan tersebut membangun Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah–bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) Tiongkok–PT Indonesia Morowali Industrial Park. Kawasan terpadu ini telah menarik investasi hingga USD20,9 miliar dan menjadi pusat produksi stainless steel, baja karbon, serta komponen baterai kendaraan listrik.
Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) menjadi program investasi besar yang fokus pada pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, rel kereta api, bandara, pembangkit listrik, dan jaringan telekomunikasi.
Melalui program ini, Tiongkok bertujuan membangun jaringan infrastruktur besar-besaran untuk menciptakan jalur perdagangan darat dan laut yang menghubungkan Tiongkok dengan berbagai wilayah di Asia, Afrika, hingga Eropa.
Sementara itu, laporan Auriga Nusantara menyebutkan lebih dari 90 persen ekspor feronikel Indonesia berlabuh ke Tiongkok. Data empat tahun terakhir menunjukkan total ekspor ke negeri tirai bambu ini mencapai lebih dari 8,8 juta ton, hanya untuk feronikel.
Tetapi dibalik tren hilirisasi nikel ini, persoalan bermunculan. Kerusakan lingkungan, kriminalisasi, hingga kecelakaan kerja.
“Sebenarnya hilirisasi dari tingkat pertama ini lebih banyak minus-nya sih sebenarnya,” kata Juru Kampanye Energi Trend Asia, Arko Tarigan. “Itu baru kita lihat dari sektor tambangnya, belum kita lagi lihat di sektor smelter.”
Bagi Arko, meskipun terdengar ambisius dan mendatangkan keuntungan besar, hilirisasi khususnya di Indonesia, hanya menarik investor semata dibanding memberi manfaat bagi masyarakat.
Transisi energi yang digembar-gemborkan melalui hilirisasi nikel dan pengembangan mobil listrik di Indonesia, kata Arko menghadapi berbagai persoalan. Terlebih lagi di rezim Prabowo-Gibran yang gencar mengampanyekan hilirisasi.
Arko bilang di tahap awal atau level hulu, aktivitas tambang nikel telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, terutama terhadap sumber mata air.
Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sumber air alami kini terpaksa membeli air karena sumber airnya tercemar. Selain itu, masalah kesehatan seperti gatal-gatal dan penyakit kulit menjadi umum di kalangan penduduk yang tinggal dekat dengan area tambang.
Dampak lainnya, pencemaran air memengaruhi populasi ikan, sehingga hasil tangkapan berkurang. Pada akhirnya, masyarakat yang seharusnya sejahtera justru kehilangan sumber pendapatan.
“Nelayan sudah tidak bisa melaut lagi di dekat tempatnya,” kata Arko. “Mereka harus (pergi) jauh bermil-mil untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang baik.”
Tak hanya itu saja, di pabrik-pabrik smelter, kata Arko menunjukkan kondisi kerja yang berat dan seringkali melanggar standar ketenagakerjaan.
Kata Arko, pekerja diharuskan lembur dengan upah rendah, dan lembur ini menjadi satu-satunya cara agar mereka bisa memperoleh gaji yang layak.
“Beberapa smelter yang saya datangi gitu flexibility labour market.-nya itu. Mereka dapat dengan mudah dimutasi, dapat dengan mudah diberhentikan, di-PHK dan sebagainya,” jelas Arko.
Pada aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di smelter, bagi Arko juga tidak diterapkan dengan baik. Kasus-kasus kecelakaan ini kadang tidak dilaporkan atau tidak terekspos kepada publik, membuat angka kecelakaan yang tercatat di media atau laporan resmi lebih rendah dari kenyataan.
Dalam kurun waktu 2015 hingga 2023, Trend Asia mencatat 93 insiden kecelakaan kerja yang terjadi di seluruh smelter nikel di Indonesia.
Salah satu perusahaan besar yang menjadi penyumbang angka kecelakaan tertinggi adalah PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), yang beroperasi di IMIP. Insiden yang paling buruk terjadi pada Desember 2023, ketika ledakan besar mengakibatkan 21 pekerja tewas dan 30 lainnya mengalami luka-luka.
Secara keseluruhan, dari total insiden, ada 91 pekerja meninggal dunia dan 158 lainnya luka-luka, dari berbagai kecelakaan yang terjadi seperti kecelakaan truk hingga kebakaran.
Lebih jauh, kriminalisasi juga turut meningkat terhadap masyarakat yang memperjuangkan lahan maupun lingkungan mereka dari cengkraman industri nikel. Adanya kriminalisasi ini, kata Arko, konflik sosial pun tak terelakkan.
Arko bilang ketegangan muncul antara mereka yang mendukung tambang dan mereka yang menolak, bahkan menyebabkan perpecahan dalam keluarga dan masyarakat.
“Orang tidak lagi bisa datang ke pesta pernikahan tetangganya karena mereka berbeda visi terkait pertambangan,” kata Arko. “Bahkan orang berduka tidak bisa lagi datang melayat.”
Bagi Arko, konflik ini menunjukkan bahwa pertambangan bukan hanya berdampak pada lingkungan dan ekonomi, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial masyarakat.

Apa yang disampaikan Arko bukan hanya terjadi di area pertambangan saja. Di area smelter juga terjadi hal serupa.
Beberapa desa di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mengalami dampak serius pabrik-pabrik smelter milik Huadi Group, menurut laporan investigasi terbaru Bollo.id.
Lingkungan warga menjadi semakin buruk dengan hujan debu, bau busuk, dan kerusakan pertanian. Mereka mengeluhkan kebisingan, debu yang dibawa truk, dan cerobong pabrik yang mengeluarkan asap, debu, dan cairan asam yang terbang bersama debu.
Proses hilirisasi nikel ini juga memicu konflik agraria yang menyebar di Indonesia bagian timur. Penyebabnya tak lain karena prosesnya masih dilakukan dengan cara-cara lama yang sering memicu konflik agraria dan kerusakan lingkungan.
Sehingga klaim keberlanjutan industri ini dinilai hanya menutupi kenyataan di lapangan, menurut Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Benni Wijaya.
Benni mengidentifikasi empat tahapan pelanggaran dalam industri nikel yang merusak kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
Pada tahap perencanaan dan perizinan, sering terjadi tumpang tindih klaim lahan antara perusahaan dan warga, dengan manipulasi izin yang kerap mengabaikan dampak lingkungan.
Kemudian, pada tahap perolehan tanah, masyarakat umumnya menerima kompensasi yang sangat minim untuk lahan mereka. Lalu tahap eksploitasi tambang membawa dampak serius terhadap lingkungan dan kerap memicu konflik antara pekerja tambang dan penduduk sekitar.
Terakhir, tahap produksi dan pengangkutan hasil tambang kata Benni, menyebabkan kerusakan jalan dan lingkungan di area sekitar tambang.
“Terjadi paradoks antara narasi yang digembar-gemborkan pemerintah mengenai industri ini dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi pertumbuhan ekonomi seperti apa yang bisa kita harapkan dari pembangunan industri bersih yang menempuh jalan kotor ini?” kata Benni.
“Ujung-ujungnya industri nikel hanya lebih konsolidasi kepentingan bisnis para elit daripada bertujuan untuk hajat hidup masyarakat yang lebih luas.”
Pada tahun 2021, menurut data KPA, tercatat ada tiga konflik besar yang berkaitan dengan industri nikel. Angka ini kemudian meningkat menjadi tujuh konflik pada tahun 2022, dan terus melonjak hingga mencapai 15 konflik pada tahun 2023.
Kasus-kasus tersebut melibatkan sejumlah proyek besar, di antaranya proyek PT. Gema Kreasi Perdana di Konawe Kepulauan, pengembangan smelter terintegrasi PT Vale Indonesia di Bahodopi di Sulawesi Tengah, PT. IMIP di Morowali, proyek pengembangan smelter terintegrasi PT Vale Indonesia di Pomala, Sulawesi Tenggara, dan smelter nikel baterai listrik PT. IWIP di Halmahera Timur, Maluku, dan PT. BMS di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Sebuah usulan moratorium
Ambisi hilirisasi nikel di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai persoalan yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.
Benni bilang, dari deretan konflik yang terjadi, pemerintahan di rezim Prabowo-Gibran ini harus segera melaksanakan reforma agraria demi menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh pertambangan dan industri nikel.
Tanpa langkah tersebut, kata Benni jumlah konflik dipastikan terus meningkat.
Sementara itu, Arko bilang di rezim Prabowo-Gibran yang baru terbentuk ini, pemerintah seharusnya tidak tergesa-gesa untuk menyatakan dukungan terhadap hilirisasi di semua sektor tanpa terlebih dahulu menata kembali peraturan yang berlaku.
Menurutnya, penting untuk melakukan moratorium dan mengevaluasi semua aspek terkait hilirisasi agar tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut.
“Perbaiki dulu dari konteks Undang-undangnya, perbaiki dulu bagaimana memandang semua aspek berkeadilan, dari HAM-nya, dari transisi energi nya, dari apapun itu,” kata Arko.
“Jangan digemborkan hilirisasi, tapi dari segi peraturan, dan bagi masyarakatnya carut marut begitu.”
Seperti yang dirasakan oleh para nelayan di Kurisa, Kabupaten Morowali. Mereka yang masih bertahan sebagai nelayan kini hidup dalam ketidakpastian.
Salah satunya adalah Awal, yang harus melaut sejauh tujuh mil dari rumahnya, dengan perahu kecil miliknya. Perairan sekitar rumahnya telah tercemar oleh limbah pabrik-pabrik smelter dan limbah bahang yang panas dari PLTU Captive milik PT. IMIP.
Setiap kali memancing malam hari, ia harus siap menghadapi risiko besar, termasuk bahaya ombak yang bisa membalikkan perahu dan mencelakakan nyawanya.
Belum lagi hasil tangkapan yang sering kali tidak sebanding dengan besarnya ongkos buat bahan bakar. Kadang, Awal kembali tanpa membawa apa-apa. “Makanya itu istilahnya buang rugi terus,” kata Awal.

Editor: Agus Mawan W