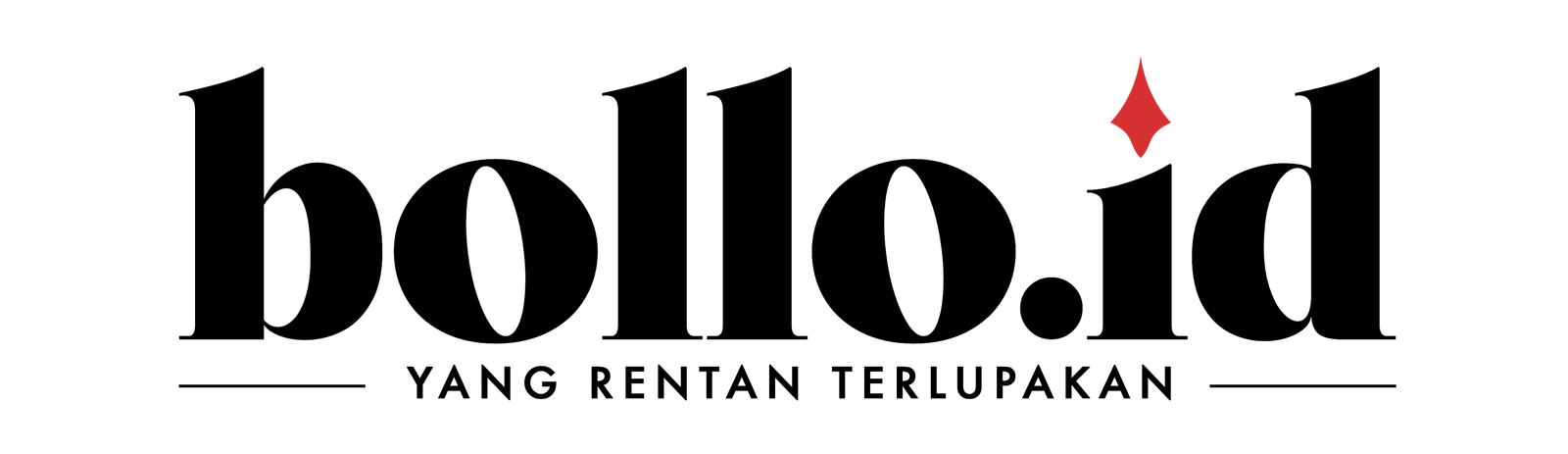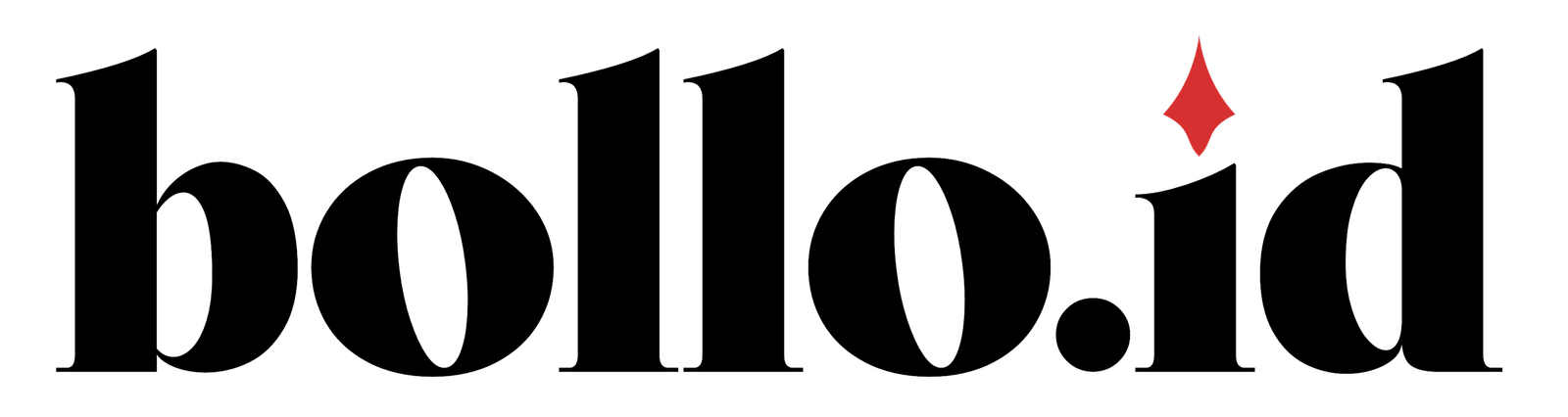Semarang – Bollo.id — Krisis iklim telah melanda semua makhluk hidup, setidaknya dalam satu dekade terakhir. Di Indonesia, bencana iklim makin marak. Angin puting-beliung, hujan lebat, banjir, tanah longsor, panas ekstrem, perubahan cuaca tidak terduga, serta kenaikan permukaan air laut yang menenggelamkan banyak wilayah pesisir.
Dari dampak krisis iklim itu, perempuan menanggung beban terberat, bahkan tidak hanya saat terjadi bencana iklim.
Namun alih-alih memunculkan solusi, arah kebijakan mitigasi justru membawa persoalan baru yang kian memperburuk situasi mereka yang sudah terkena beban krisis iklim.
Hal ini berakar pada kesepakatan internasional, yang mengatakan bahwa solusi perubahan iklim perlu mengarah kepada kepentingan pasar dengan melakukan investasi ke sumber-sumber energi karbon rendah.
Dampaknya adalah banyak mega proyek energi seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal, pembangkit listrik tenaga surya dan angin, bahan bakar nabati (sawit, antara lain) yang masuk secara masif.
Apa yang dimaksud orientasi pasar rupanya adalah kepentingan ekspor industri teknologi dan mesin dari negara industri maju ke Indonesia dan negara berkembang lainnya.
Dari fakta inilah, Aksi! for gender social and ecological Justice bersama Solidaritas Perempuan menginisiasi sebuah Dialog Komunitas pada Pertemuan Kedua Global Thematic Social Forum on Mining and Extractive Economy (Global TSF-Mining), di Kota Semarang, Kamis, 19 Oktober 2023.
Dialog ini membahas PTLPB atau geothermal di Indonesia. Pertemuan ini diikuti 65 orang dari Indonesia dan negara lainnya. Dialog ini menjadi ruang bagi para perempuan untuk berbagi pengalaman ketika menghadapi ekspansi geothermal.
Linda Tagi, dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas Nusa Tenggara Timur, menceritakan perlawanan masyarakat di 17 desa akibat kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencaharian akibat operasi PT. Ulumbu di Poco Leok.
Di sana, tutur Linda warga ditindas secara brutal oleh aparat militer. Termasuk didalamnya adanya tindakan kekerasan seksual. Operasi PT Ulumbu sejak 2018 ini dibiayai oleh lembaga keuangan Jerman ‘Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) dan Asian Development Bank, menurut Linda.
Geothermal itu mulai beroperasi sejak 2002 lalu. Kata Linda, fasilitas pembangkit itu kerap kali terjadi kecelakaan. Bahkan pernah mengeluarkan semburan panas lumpur, merusak 1.579 rumah di 11 desa, dan mencemari sungai yang merupakan sumber mata air masyarakat setempat. Akibat itu, kata Linda banyak penduduk desa harus meninggalkan rumah dan tanahnya.
“Geothermal adalah eksploitasi perempuan, masyarakat adat, tradisi, budaya dan ekosistem, melahirkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan”, tegasnya saat membagikan pengalaman di sela-sela dialog.
Kepulauan Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kata Linda juga ditetapkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Pulau Panas Bumi (Geothermal Island) pada 2017 dengan menetapkan 27 lokasi geothermal.
“Tentunya sudah bisa kita bayangkan bahwa pulau-pulau kecil yang indah tersebut akan mengalami kehancuran,” tegas Linda Tagi.
Cerita lain datang dari Nurlaela, seorang perempuan dari kaki Gunung Slamet. Tujuh tahun lalu, ketika pembangunan fasilitas geothermal berlangsung, sungai mereka dicemari lumpur. Mata air dan irigasi yang berada di kaki Gunung Slamet ikutan tercemar.
Saat itu, kata Nurlaela, pencemaran juga menghancurkan tambak-tambak ikan milik warga, juga industri tahu rumahan yang menjadi primadona warga setempat. “Saat ini dampak pencemaran lumpur tersebut masih tetap dirasakan,” katanya.
“Debit air sungai menurun drastis, produsen rumahan tahu yang mampu bertahan, harus mengeluarkan biaya produksi lebih banyak untuk membeli air bersih, tambak-tambak rumahan yang hancur akibat lumpur, tidak bisa pulih.”
Dari dampak yang telah terakumulasi itu, kata Nurlaela, banyak usaha perekonomian perempuan yang merayap. Banyak dari mereka bahkan, terlilit utang rentenir demi menutup biaya kebutuhan sehari-hari.
“Mereka sering mengalami kekerasan seksual untuk membayar utangnya,” kata Nurlaela. “Hidup kami sebenarnya akan lebih baik tanpa geothermal.”
Ikuti akun instagram Bollo.id
Di Tingkat Perencanaan: Solusi Geothermal Diklaim Bermasalah
Menurut Leorana Sihotang, dari Kelompok Studi dan Pengembangan Masyarakat (KSPPM), persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama perempuan, tidak saja saat geothermal dalam tahap eksplorasi dan eksploitasi, tetapi di tingkat desain dan perencanaan pun sudah bermasalah. Salah satu contoh adalah rencana pengembangan geothermal yang dideklarasikan pemerintah pada 2012 lalu di Pulau Samosir, Danau Toba.
Di mana diketahui, kata Leorana Pulau Samosir ini merupakan wilayah adat yang telah dihuni turun-temurun dengan dukungan kawasan pertanian dan peternakan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Di level tapak, kata Leorana, tidak ada informasi jelas yang sampai ke telinga masyarakat Pulau Samosir. Soal rencana proyek hingga proyek itu sendiri. Baginya, hal ini jelas melanggar ketentuan nasional dan internasional tentang free, prior and informed consent (persetujuan yang diberikan dengan informasi yang disediakan sebelumnya dan dilakukan tanpa paksaan/kekerasan) yang berlaku untuk intervensi proyek ke wilayah masyarakat adat.
“Proyek geothermal tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat adat, termasuk para perempuan adat,” kata Leorana.
“Kita harus menolak proyek tersebut yang telah menyingkirkan hak masyarakat adat dan suara perempuan.”
Baca juga: Makassar Tak Memiliki Standar Pengelolaan Sampah Elektronik
Contoh lain diungkapkan oleh Aulia Utami, dari Solidaritas Perempuan Sebay Lampung. Di sini, geothermal akan digelar di Rajabasa, Provinsi Lampung. Dikembangkan sejak 2013 oleh PT. Supreme Energy (PT. SERB) bersama perusahaan asal Perancis (GdF Suez atau Engie), yang belakangan mundur dan digantikan perusahaan energi asal Jepang, INPEX Corporation, anak perusahaan Fortune 500, dan Sumitomo Corporation.
Masyarakat setempat, kata Aulia telah menolak rencana eksplorasi geothermal itu, apalagi fasilitas itu berada di dalam hutan lindung yang memiliki nilai budaya dan ikatan yang kuat dengan mereka, selain akan kehilangan ruang berlindung dari bencana tsunami.
Seperti sudah jadi kebiasaan, informasi rencana itu, kata Aulia tidak sampai ke telinga masyarakat dan tidak ada konsultasi maupun permintaan persetujuan terhadap masyarakat termasuk kepada perempuan.
“Pengembangan proyek geothermal berorientasi pada kepentingan bisnis, hanya menyengsarakan kehidupan masyarakat khususnya perempuan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi mengatakan, geothermal adalah wujud paradigma pembangunan yang eksploitatif dalam cengkeraman jalinan kuasa patriarki, globalisasi lewat politik neo-liberal, militerisme dan fundamentalisme negara untuk memfasilitasi kepentingan investasi.
Eksploitasi sumber daya alam untuk pengembangan geothermal yang memicu konflik tanah dan pencemaran lingkungan, katanya telah dan akan terus memiskinkan perempuan, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya.
Misalnya, kata Armayanti, pengembangan geothermal di Gunung Rajabasa, Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur serta wilayah lainnya.
Kondisi ini baginya, tentu saja telah mengabaikan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang merupakan perjanjian internasional yang mengikat dan Indonesia telah meratifikasinya. Bahwa negara bertanggung jawab untuk menghapuskan diskriminasi yang dilakukan oleh individu dan organisasi swasta.
“Juga mengabaikan Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 mengenai pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan pembangunan di Indonesia dengan ketentuan adanya analisis gender dan keterlibatan pandangan perempuan,” akunya.
Geothermal Hancurkan Lingkungan dan Sumber Kehidupan Perempuan
Risma Umar dari Aksi! for gender social and ecological justice menilai, dari dialog komunitas tersebut dapat memberi pembelajaran bahwa transisi menuju sumber energi dan ekonomi rendah karbon, bukan berarti membangun mega proyek yang diklaim sebagai rendah karbon, bersih dan berkelanjutan.
Transformasi atau peralihan dari model ekonomi ekstraktif dalam cengkeraman jalinan kuasa patriarki, globalisasi, militerisme dan fundamentalisme, menuju ekonomi regeneratif, rendah karbon dan berkelanjutan, kata Risma harus dengan mengganti model ekonomi tidak adil yang berlaku sekarang.
Proses transformasi, kata Risma harus mengedepankan kelestarian sumber kehidupan, menghormati Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan, melibatkan masyarakat lokal, khususnya perempuan dalam pengambilan keputusan memenuhi kebutuhan mereka termasuk kebutuhan energi.
“Dialog ini menggambarkan bahwa geothermal bukan energi bersih dan bukan solusi untuk mengatasi krisis iklim karena menghancurkan lingkungan dan sumber-sumber kehidupan perempuan,” kata Risma.
“Demikian juga melegalkan kekerasan negara bahkan kekerasan seksual terutama terhadap perempuan komunitas yang menentang proyek geothermal. Perubahan dan krisis iklim, demikian juga solusi iklim kini merupakan ancaman terbesar kepada hak asasi manusia dan hak-hak perempuan.”
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Sulawesi Selatan Jadi Wilayah Lokasi Geothermal
Musdalifah Jamal dari Perkumpulan Suara Perempuan, juga mengungkapkan contoh lainnya. Dia mengatakan, informasi mengenai geothermal sangat kurang.
Dari penulusuran Musdalifah, rencana geothermal di Indonesia, didanai oleh Bank Dunia yang menjadi penyalur dana dari Green Climate Fund (GCF). Pada Oktober 2018, katanya, GCF menyetujui pendanaan USD 100 juta ke Bank Dunia untuk membiayai kegiatan eksplorasi geothermal di 20 lokasi di Indonesia.
“Namun, 5 tahun sejak proyek tersebut disetujui, hanya ada satu titik merah yang mengindikasikan lokasi proyek pada website Bank Dunia, yakni di Kabupaten Bone,” kata Musdalifah.
“Tidak ada informasi lain.”
Situasi ini, kata Musdalifah menunjukkan tidak adanya keterbukaan informasi publik mengenai pengembangan geothermal. “Bayangkan, apa yang akan juga terjadi di 14 lokasi potensi geothermal yang telah ditetapkan pemerintah untuk Sulawesi Selatan.”