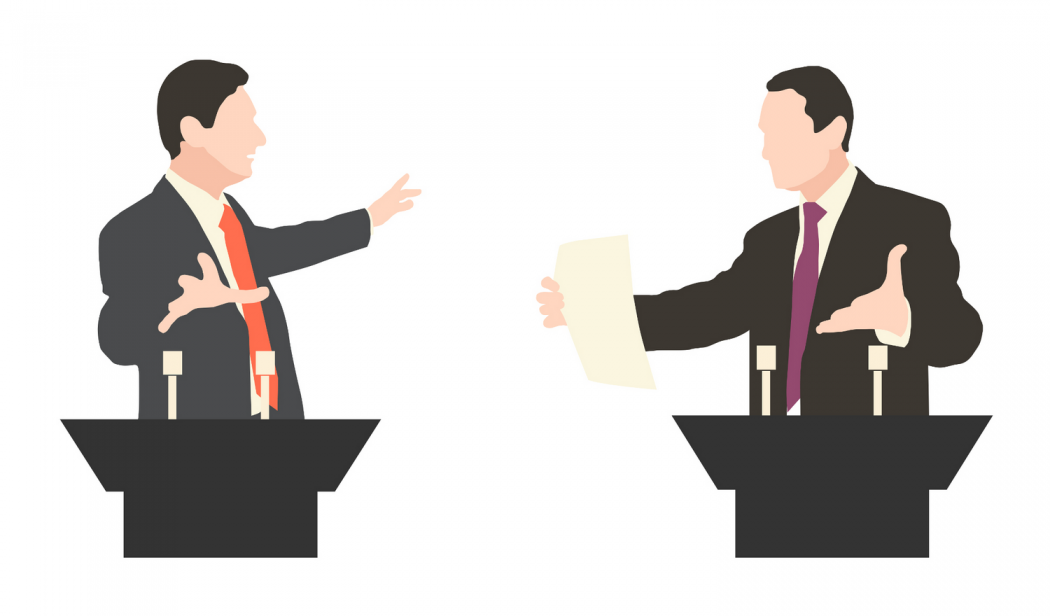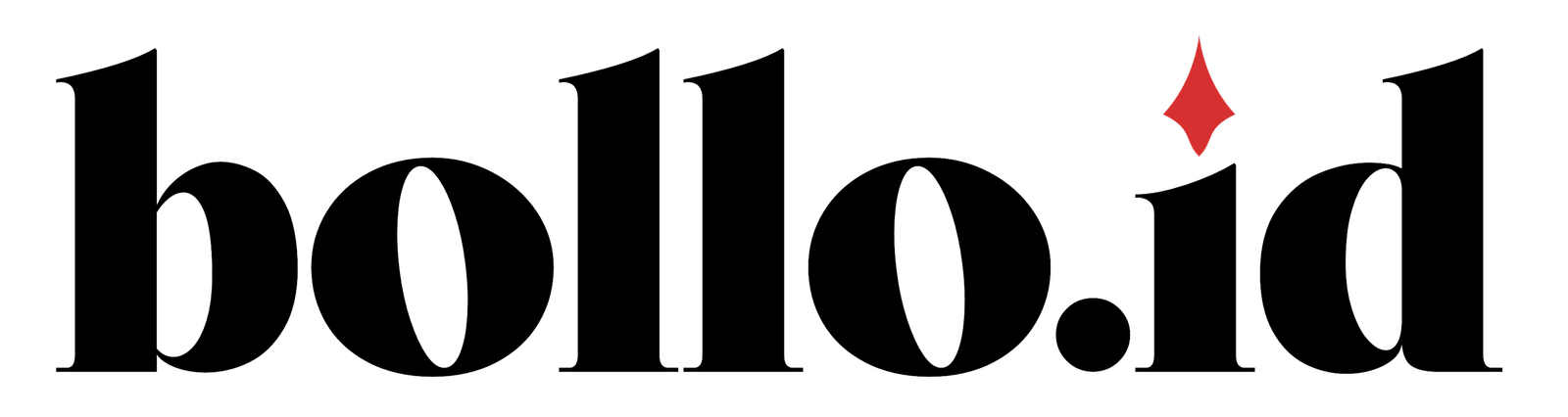“Butta Toa adalah belantara makna, gunung dan batu dikeramatkan, hutan dan mata air menyimpan cerita. Panen di sawah dan kebun yang menjelma rumah atau sepeda motor disyukuri dengan membakar dupa dan memanjatkan doa. Loka labbu, onde-onde dan songkolo tersaji mengiring doa yang dipanjatkan. Kerabat dan handai taulan yang meninggal akan dikenang dengan selamatan berjenjang; 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari, sampai tammu taung. Belum lagi kelahiran, khitanan, perkawinan, kehamilan selalu disertai barazanji. Di Butta Toa orang-orang bukan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka juga bekerja menghidupi tradisi.”
Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Bantaeng sebagai Butta Toa (tanah tua dalam bahasa Indonesia) memiliki akar tradisi yang kuat. Menempatkan alam sebagai sesuatu yang sakral, mengungkapkan rasa syukur dengan berkumpul dan berdoa sambil menyajikan beragam hasil bumi, menandakan tanah yang subur dan membawa kesejahteraan.
Sebagai kabupaten yang dikenal dengan julukan Butta Toa, budaya seharusnya menjadi diskursus penting dalam debat calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng periode 2024–2029. Sayangnya, harapan itu tidak terpenuhi. Debat yang berlangsung pada 16 November di Hotel Claro justru diwarnai saling sindir antar pasangan calon (paslon), sehingga substansi yang diharapkan tersaji menjadi kabur.
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng periode 2024-2029 diikuti dua pasang calon, yakni Fathul Fauzi Nurdin dan Sahabuddin sebagai paslon 01 berhadapan Ilhamsah Azikin dan Nurkanita Maru’dani Kahfi sebagai paslon 02. Dalam debat tersebut, moderator melontarkan pertanyaan terkait budaya kepada Paslon 02, didahului narasi pengantar yang menarik:
“Riset UNESCO (2016–2018) dan BRIN (2024) menunjukkan kurangnya dukungan kebijakan terhadap nilai, pengetahuan, dan kepercayaan lokal, padahal hal tersebut merupakan aset penting bagi keberlanjutan sosial dan budaya. Di Kabupaten Bantaeng, pengetahuan lokal seperti sistem penanggalan tradisional pananrang belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal potensi pananrang sangat relevan untuk sektor pertanian, perikanan, dan pelestarian budaya.”
Moderator kemudian bertanya: “Kebijakan apa yang diperlukan untuk memastikan budaya tak benda, terutama pengetahuan dan kepercayaan lokal, mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang tepat, serta dapat berinteraksi dengan perubahan zaman?”
Sebelum menyoroti jawaban kedua pasangan calon, ada baiknya kita mendalami terlebih dahulu bagaimana budaya lahir, tumbuh, dan berkembang menjadi pedoman hidup masyarakat lokal. “Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya.”
Lalu bagaimana manusia atau suatu komunitas masyarakat, termasuk di Bantaeng memperoleh pengetahuan yang kemudian menjadi pedoman dalam hidup dan perilakunya sehari-hari. Untuk memahami lebih jauh, mari kita bertandang ke Campaga.
Di Campaga, hutan bukan sekedar sekumpulan pohon dalam satu kawasan yang diklaim oleh negara. Bagi warga, hutan adalah pusat dari urat nadi kehidupan. Dari hutan di Campaga mata air mengalir menjadi anak sungai. Memasok 15 persen kebutuhan air minum pelanggan PDAM.
Mengairi 500 hektar sawah yang membentang dari Campaga, Barua hingga Rappoa. Melestarikan hutan dan memelihara mata air lalu menjadi identitas orang campaga. Dalam rangka memastikan hutan dan mata air tetap terjaga, lahirlah kesepakatan tak tertulis, pohon dalam hutan tidak boleh ditebang.
Tindakan yang bisa membuat mata air dan anak sungai menjadi kotor atau tercemar, tidak diperbolehkan, bahkan dilarang meludah di sekitar mata air. Barang siapa melanggar larangan, maka bersiaplah terkenal bala.
Kesadaran kolektif orang Campaga terbangun dari pemahaman sederhana: melestarikan hutan berarti melestarikan kehidupan. Untuk mengokohkan kesadaran kolektif, tumbuh kepercayaan mengenai sejumlah tempat keramat dalam hutan, antara lain pohon Erasa Lego-lego, batu besar yang dinamai Babangtangngayya, dan mata air Karengloe.
Situs keramat atau dalam bahasa setempat disebut Saukang, adalah manifestasi penghormatan terhadap alam. Di tempat-tempat ini, alam dan spiritualitas bertemu, membentuk benteng pelindung dari ancaman pengrusakan.
Selain menjaga hutan mata air, spiritualitas juga menjaga imajinasi (kepercayaan) tentang relasi antara orang-orang yang masih hidup dengan roh dan jiwa nenek moyang yang telah lebih dulu pergi. Roh dan jiwa-jiwa para tetua terdahulu hadir di tempat-tempat yang disakralkan (saukang).
Jika hutan rusak, maka itu sama dengan mengganggu saukang yang ada di dalamnya. Jika terdapat kejadian mistis yang berhubungan dengan orang-orang yang mengganggu hutan, itu berarti roh dan jiwa-jiwa telah terusik.
Tradisi menjaga hutan yang masih berlangsung di Campaga adalah cerminan bagaimana masyarakat lokal hidup dan membangun kebudayaan. Secara umum seperti itulah corak hidup masyarakat lokal Butta Toa.
Di setiap desa atau setiap kampung terdapat saukang, membuktikan akar budaya masyarakat lokal di Bantaeng adalah hidup selaras dengan alam. Mari kita coba lacak lebih jauh. Jauh sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan, komunitas yang bermukim di lereng-lereng Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompobattang menganut kepercayaan yang disebut Patuntung.
Kata Patuntung berasal dari bahasa Makassar “panuntung” yang berarti penuntun kehidupan di dunia. Historiografi lontara memuat legenda tentang sejarah asal mula peradaban di Bantaeng yang bermula dari kampung-kampung di tepi hutan di dataran tinggi Lompobattang.
Diriwayatkan bahwa ketika terjadi akdampang (keadaan kacau yang tidak terkendali), dari ‘Dunia Atas’ turun seorang dewa yang kemudian diberi gelar Tumanurung untuk menentramkan keadaan. Tempat Tumanurung tersebut, yakni di sebuah batu keramat kemudian dinamakan Panurungang.
Selain Tumanurung, kepercayaan Patuntung juga menyebutkan adanya roh atau jiwa yang bersemayam saukang, seperti pohon besar atau batu besar, sungai, mata air, atau beragam medium lainnya.
Oleh karena roh dan jiwa tersebut dapat mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari, maka untuk mendapatkan perlindungan dan berkahnya, diperlukan acara Attoana, yaitu persembahan sesajen yang diletakkan pada saukang.
Persembahan sesajian, terutama dilakukan pada saat akan memasuki musim tanam, dan bepergian luar daerah. Attoana adalah ungkapan harapan untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari roh Tumanurung.
Selain Attoana, ritual penting lainnya adalah akkawaru, upacara penyucian yang dilaksanakan untuk memurnikan kampung serta melindunginya dari malapetaka, penyakit dan roh jahat. Pada zaman dahulu, bagian penting dari Akkawaru adalah pawai yang mengelilingi kampung.
Pinati (pemimpin ritual) berhenti pada tiap sudut pemukiman, lalu meletakkan sajian persembahan bagi penunggu alam dan memohon kepada leluhur untuk melindungi kampung dari malapetaka. Ritual lainnya yang berhubungan dengan tradisi menjaga alam yang bertahan hingga sekarang antara lainnya lappassa’ tinja’, dan caru-caru.
Di Campaga, dan mungkin juga di tempat lainnya, Akkawaru, lappasa’ tinja’ dan caru-caru masih sering dihelat oleh berbagai komunitas masyarakat di desa-desa. Khusus untuk caru-caru hampir setiap musim tanam dan musim panen banyak dilakukan oleh petani di Campaga.
Tradisi ini mempererat kebersamaan dan mendidik generasi muda tentang pentingnya melindungi hutan. Setelah bertandang ke Campaga untuk mengulas bagaimana manusia atau suatu komunitas masyarakat memperoleh pengetahuan dan membangun budayanya, paling tidak terdapat dua hal penting yang patut dicatat baik baik!
Pertama, dalam konteks masyarakat lokal Bantaeng, hidupnya masih bercorak agraris (hal ini semua orang sudah tahu). Kedua, sebagai masyarakat agraris, tradisi yang lahir, berkembang dan sebagian masih dijalankan selalu selalu berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam.
Dari dua poin yang disebutkan kita bisa menyimpulkan bahwa: jika ingin budaya lokal, baik benda maupun tak benda tetap ada, diterapkan dan berinteraksi dengan perkembangan zaman, maka masyarakat lokal harus berdaulat terhadap tanah, lingkungan dan sumber daya alamnya.
Sebab dari sana lah budaya mereka lahir, tumbuh dan berinteraksi dengan perkembangan zaman. Lalu apa hubungan ulasan di atas dengan debat kedua Pilkada Bantaeng, khususnya topik budaya yang menjadi pertanyaan moderator?
Ulasan di atas dimaksudkan untuk menjelaskan dengan terang kepada publik, bahwa budaya bukanlah sesuatu yang lahir dari ruang hampa. Budaya lahir dari interaksi manusia atau komunitas masyarakat dengan lingkungan dan sumber daya alamnya.
Corak dan orientasi interaksi masyarakat dengan sumber daya alamnya sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan pemerintah. Jika pemerintah menempatkan lingkungan dan sumber daya alam semata-mata sebagai potensi untuk dikapitalisasi secara komersil, maka budaya yang tumbuh dari praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam akan punah.
Kalaupun masih ada, maka yang tersisa hanyalah simbolisasi semata. Tidak lagi menjadi pedoman hidup. Lebih celaka lagi jika ritual dan simbol-simbol budaya kemudian dipandang potensi yang bisa dikapitalisasi baik secara politik maupun secara ekonomi, maka disanalah budaya akan kehilangan maknanya sebagai pedoman hidup.
Contoh paling konkrit adalah ditetapkannya lima desa di Pa’jukukang sebagai Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), yang kemudian menjadi dasar pembangunan smelter pemurnian bijih nikel. Industri yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan potensi sumber daya lokal.
Keberadaan industri ini jelas mengubah pola kehidupan masyarakat yang hidup dari bertani, melaut dan membuat batu bata. Budaya agraris yang menandai tempat-tempat tertentu sebagai saukang, menggelar ritual-ritual kecil sebagai simbol interaksi spiritual, jelas tidak relevan dengan karakter industri yang bersifat monopoli.
Monopoli lahan untuk industri membuat pesta rakyat tahunan sebagai ekspresi budaya yang digelar di gantarang keke dan Pa’jukukang akan kehilangan makna, sebab saukang yang menjadi salah titik sentrum pesta rakyat ini tepat berada di batas KIBA.
Dalam debat Calon Bupati, paslon 01 menggunakan isu pesta rakyat Pa’jukukang untuk menyerang Paslon 02. Paslon 01 menuding palon 02 yang tidak pernah sekalipun hadir dalam pesta rakyat tersebut, adalah bukti tidak adanya kepedulian.
Paslon 01 Tidak sedikit pun membahas eksistensi pesta rakyat Pa’jukukang yang jelas terganggu dengan keberadaan smelter, padahal saat menjabat sebagai ketua DPRD, paslon tersebut yang menyetujui penetapan Pa’jukukang sebagai kawasan industri.
Paslon 02, sebenarnya memiliki gagasan yang cukup baik dalam menjawab pertanyaan moderator dengan dengan topik budaya. Menurut Paslon 02 kebijakan yang diperlukan untuk memastikan pengetahuan dan kepercayaan lokal mendapatkan pengakuan serta dapat berinteraksi dengan perubahan zaman, harus mencakup beberapa aspek.
Pertama, regulasi pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam kurikulum di sekolah-sekolah untuk memperkenalkan generasi muda pada nilai-nilai budaya tradisional.
Kedua, dukungan terhadap riset dan dokumentasi pengetahuan lokal untuk memastikan keberlanjutan dan transformasi pengetahuan antar generasi. Dan terakhir, menyediakan platform atau wadah yang memungkinkan pelestarian budaya tak benda, seperti festival budaya, pusat studi, dan ruang digital untuk mempromosikan pengetahuan lokal.
Tiga poin yang disampaikan paslon 02 jelas sangat menarik, namun seperti yang disampaikan paslon 01, sebaik apapun gagasannya jika tidak diikuti komitmen anggaran, maka itu hanyalah pepesan kosong. Dan paslon 02 hanya menyampaikan gagasan, tidak sedikit pun menyinggung komitmen anggaran, termasuk saat menjabat selama lima tahun.
Pada akhirnya, tulisan ini hendak menegaskan, bahwa melindungi budaya lokal berarti melindungi sumber daya alam dan identitas masyarakat, karena keduanya saling terhubung secara mendalam.
Budaya lahir dari cara masyarakat memahami dan berinteraksi dengan alam di sekitarnya. Tradisi, kepercayaan, dan pengetahuan lokal tumbuh dari lingkungan yang mereka kelola dan manfaatkan secara berkelanjutan. Ketika lingkungan rusak, tidak hanya ekosistem yang terancam, tetapi juga budaya yang berakar pada hubungan tersebut.
Budaya yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat lokal merupakan cara mereka untuk memastikan keselamatan hidup. Menghancurkan relasi mereka dengan alam sama dengan menghancurkan budaya yang menjamin keselamatan hidup mereka.
Demikianlah yang terjadi di Papan Loe dan Borong Loe. Barangkali sebentar lagi akan melebar ke Pa’jukukang dan Baruga. Dan perlu diingat, dampak kerusakan lingkungan tidak mengenal batas administrasi, bau busuk dari pembakaran smelter, sudah dikeluhkan sampai Bulukumba dan Jeneponto.
Tanpa regulasi yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat lokal, budaya hanya akan tersisa sebagai simbol kosong—ritual yang dilakukan tanpa memahami esensinya. Melindungi budaya lokal bukan hanya soal pelestarian tradisi, tetapi juga menjaga akses masyarakat terhadap sumber daya alamnya.
Hal ini membutuhkan komitmen nyata dari pemerintah. Sudah saatnya pembangunan berorientasi pada pemulihan alam dan pelestarian budaya, menempatkan alam dan budaya sebagai subjek, bukan sebagai objek untuk dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi.
Tulisan ini merupakan bagian dari proyek kecil nada merah yang sedang berjibaku mengumpulkan bahan dan membuat konten untuk merespon debat kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Editor: Sahrul Ramadan