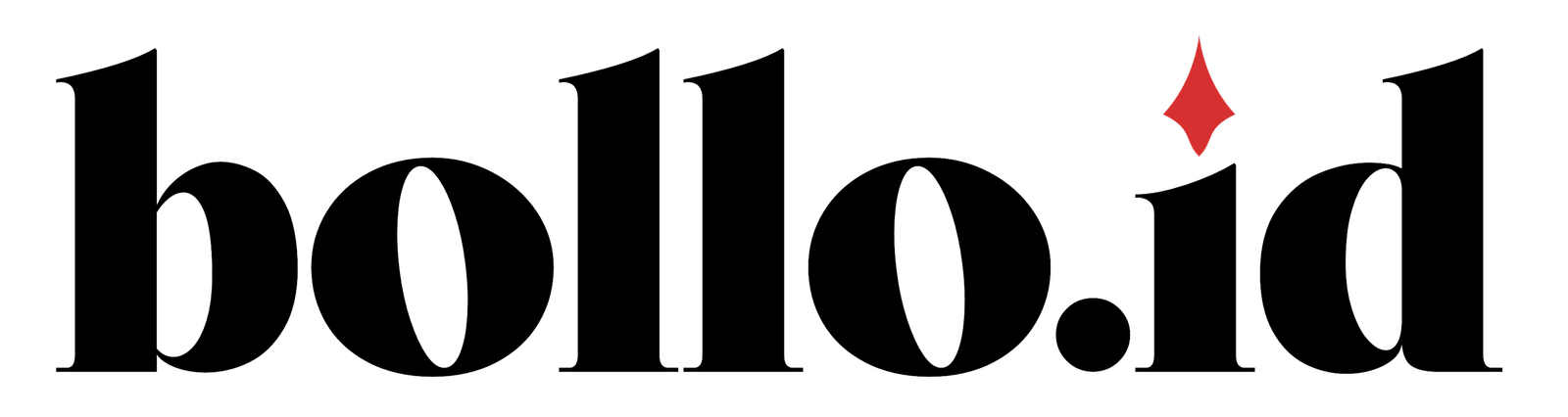Herto Bouri–wilayah gurun di Ethiopia, menjadi panggung pertunjukan para arkeolog dalam upaya merunut muasal manusia. Situs tersebut memberi petunjuk penting tentang pitarah yang memula hidup di belantara Afrika. Perubahan alam berpadu insting bertahan hidup membuat mereka mulai melakukan perjalanan sekitar 120 ribu tahun yang lalu. Sekian generasi kemudian, mereka mencapai Asia dan Australia. Di semesta Sulawesi, imajinasi tentang kehidupan awal bermula dari kisah La Galigo, epik penciptaan yang menjadi ensiklopedia kosmologi, moralitas, dan penjelajahan yang merekam tumbuh tutur peradaban manusia. Dengan struktur dramatik dan kompleksitas naratifnya, La Galigo menjadi karya yang meramu kebermulaan, cinta, perang, hingga kematian.
Ada mula kisah La Galigo diawali dari kehampaan–sebuah kekosongan yang melahirkan telur kosmik. Dari telur inilah kemudian menetas para dewa yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Batara Guru sebagai aktor dalam semesta La Galigo, diriwayatkan sebagai pencipta yang turun ke bumi. Melalui perkawinannya dengan We Nyili Timo, Batara Guru menurunkan keturunan yang menjadi leluhur manusia. Salah satu tokoh yang kisahnya membiak dalam epik ini adalah Sawerigading. Sebagai keturunan Batara Guru, ia memiliki peran sebagai penjaga keseimbangan kosmos dan turut dikisahkan sebagai penjelajah.
Motif utama ketika berpangkal pada sumber arkeologi atau kisah La Galigo adalah perjalanan, penjelajahan, dan perantauan. Sumber arkeologi seperti fosil, alat-alat batu, dan lukisan gua, memberikan gambaran ilmiah tentang kapan dan bagaimana manusia purba tiba dan hidup di Sulawesi. Perspektif ini menggunakan pendekatan yang bersifat empiris dan berpedoman pada metode ilmiah. Sementara kisah La Galigo bersifat metaforis dan mitos, tidak terikat pada waktu yang spesifik. Tuturannya menceritakan kisah penciptaan manusia secara simbolik dan mistis. Daur kisahnya memberikan penjelasan tentang muasal manusia dan alam semesta. Dengan lain kata, kisah La Galigo lebih bersifat kosmologi sementara sumber arkeologi berfokus pada aspek biologis dan budaya manusia purba. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya dapat memberikan serumpun perspektif tentang sejarah dan budaya masyarakat Sulawesi. Data arkeologi memberikan dasar ilmiah, sementara La Galigo memberikan dimensi spiritual dan filosofis.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Dalam pertunjukan terbaru Kala Teater, Shinta Febriany sebagai sutradara dan penulis naskah menyelidiki laku rantau, jelajah, dan perjalanan manusia melalui teater berjudul ‘Passompe’ Perjalanan Melintas Batas Kesedihan’. Seperti ada mula La Galigo, ruang pertunjukan yang dilaksanakan di Gedung Mulo, Makassar pada tanggal 8 hingga 10 Desember 2024 tersebut berawal dengan kekosongan. Tidak ada gerak dan cahaya. Narator membawa kita ke dalam semesta Passompe’ yang dimulai dengan dramaturgi tubuh dalam ritme yang bergerak cepat. Sebuah insiden ketika dua aktor berlanggaran mengubah ritme menjadi lamban.
Saya duduk di kursi lima belas pada baris pertama dengan sudut pandang pertunjukan cenderung dari arah kanan. Dari atas panggung, kehadiran dua kursi merah yang dibekali roda sehingga dapat bergerak riang sepanjang pertunjukan seakan menyurati pirsawan untuk mengamati setiap gerak, bunyi, cahaya, dan kilasan yang dihadirkan pada dinding putih. Dua aktor yang duduk di kursi tersebut melakukan percakapan tentang riwayat asal. Mereka mengajukan pertanyaan, sudah sampai mana kita? Tidak jauh dari percakapan itu, pertanyaan lain diperdengarkan, apa itu identitas?
Kedua pertanyaan tersebut memberi saya kesempatan memasuki semesta Passompe’ sebagai arena budaya. Apa itu passompe’? Impresi yang saya dapatkan setelah menyaksikan pertunjukan ini, suatu sikap yang tidak terikat oleh batas, tidak terkekang oleh kekuasaan, dan tidak dilumpuhkan oleh waktu. Dalam pertunjukan ini, sompe’ dihadirkan sebagai naluri manusia untuk melakukan perjalanan yang berspekulasi pada kesedihan. Sebuah adegan ketika dua pelantang suara digaungkan aktor untuk membaca butir kedelapan Perjanjian Bongaya mewajahkan kesedihan tersebut; mereka yang melanggar harus menebusnya dengan nyawa dan harta.

Motif Perjalanan
Upaya pertunjukan ini melakukan pembacaan ulang terhadap sompe’ dihadirkan dengan beragam motif perjalanan. Jika percakapan tentang sompe’ kerap berambu pada perspektif maritim, Shinta mengajak kita melihat bagaimana kolonialisme dan perkembangan industri turut memengaruhi motif perjalanan kita. Walau tidak sepenuhnya lepas dari metafora laut, kapal, dan layar, kehadiran nuansa bandara, pesawat, dan musim yang tidak akrab, meluaskan pandangan kita tentang motif perjalanan. Dengan lain kata, sompe’ akan selalu bersangkut-paut dengan cara hidup kita dan cara kita hidup.
Salah satu cara tumbuhan paku berkembang biak adalah melalui spora; terbawa angin, mereka mungkin melakukan perjalanan jauh sebelum mendarat di tanah yang tepat untuk perkecambahan. Disjungsi jarak jauh mengacu pada cara populasi tumbuhan paku dapat tumbuh di daerah yang terpisah dan terputus-putus. Kata diaspora dan spora berakar dari bahasa Yunani, sporas yang berarti tersebar. Dalam pertunjukan Passompe’ ini, diaspora Sulawesi Selatan yang terjadi di berbagai tempat dan kejadian dijadikan pertanyaan, bagaimana kita memaknai sompe’? Musabab apa yang membuat mereka senang bernyanyi di geladak kapal menuju tanah baru? Dibutuhkan sejumlah peristiwa untuk menjawab kompleksitas tersebut. Sejauh yang dapat ditelusuri, gelombang rantau di Sulawesi Selatan dapat dikategorikan ke dalam empat babak utama.
Gelombang pertama, seperti dikisahkan dalam kitab La Galigo, ketika pusat Kerajaan di Ussu’ dan sekitarnya sudah terlampau sempit untuk mencari penghidupan, masyarakat mulai menyebar ke seluruh Sulawesi hingga ke Maluku dan Ternate. Di tempat baru tersebut, mereka membentuk kerajaan, Wedang di Gorontalo, Tompo Tika di Luwuk Banggai, Kaili di Sulawesi Tengah hingga Balanipa di Mandar. Semua kerajaan tersebut, mulanya berindung ke Kerajaan Luwu. Silsilah raja-raja mereka juga bernasab hingga ke Sawerigading.
Kedua, pascaperang Makassar. H. J. de Graaf, sejarawan yang lahir di Rotterdam pernah menulis secara cermat peristiwa tersebut. Sejumlah pasukan Kerajaan Gowa, yang diinisiasi Laksamana Karaeng Bontomarannu dan Laksamana Muda Karaeng Galesong melarikan diri ke Jawa untuk bergabung bersama pasukan Trunojoyo. Pelarian tersebut, salah satunya dilatari keputusan Sultan Hasanuddin menyerah melalui Perjanjian Bongaya.
Ketiga, pasca-rumpa’na Bone pada tahun 1905. Peristiwa tersebut menjadi puncak pecahnya hubungan Belanda dan Kerajaan Bone. Perang yang terjadi di Pantai Bajoe tersebut menewaskan ribuan orang dari kedua pihak. Runtuhnya Bone dan berlakunya aturan yang membuat masyarakat berantakan–terutama yang berhubungan dengan perdagangan, menjadi alasan kuat mereka meninggalkan kampung halaman. Hal ini turut direkam Jacquline Lineton dalam tulisannya pada tahun 1975, yang menguraikan bahwa sebagian besar pedagang-pedagang Bugis dan Makassar meninggalkan daerah mereka karena domestic conflicts yang kadang diatur dan dicampuri oleh kepentingan Belanda.
Dan gelombang keempat, Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin Kahar Muzakkar, pada periode 1949. Terjadi gejolak berdarah; pembakaran kampung; pemaksaan masyarakat menjadi ‘gorilla’; penyiksaan orang-orang yang dianggap musuh Islam. Gejolak tersebut menjadi fresh impetus bagi sebagian masyarakat Bugis–diikuti pula Makassar, Mandar, Toraja, Selayar, Duri, dan Enrekang untuk massompe’.
Sebuah ajakan diujarkan dengan putus asa oleh aktor dalam pertunjukan Passompe’. “Sawerigading, mari kita tinggalkan kesengsaraan ini!”
“Ke mana?”
“Ke tanah baru!”
Percakapan itu membuat saya mengingat karya Subagyo Sastrowardoyo, Daerah Perbatasan. Puisi yang pertama kali terbit di Budaja Djaja itu dibuka dengan meramu perasaan putus asa dan kebimbangan manusia.
“Kita selalu
berada di daerah perbatasan
antara menang dan mati.”
Dalam puisi tersebut, ruang diadaptasi menjadi konsekuensi. Manusia dihendaki bergerak dalam dua pengarungan: antara menang dan mati. Makna serupa dapat ditelusuri dalam salah satu lontara yang disusun Andi Palloge Petta Na’ba–digunakan sebagai pedoman masyarakat Bugis dan Makassar ketika hendak merantau: “Pura ba’bara sompekku, pura tangkisi golikku. Ule’birengngi telleng natowalie.” Pesan itu bermakna, ketika layar dan kemudi telah memilih arah, lebih baik tenggelam ke dasar lautan daripada kembali ke pelabuhan. Muatan kedua karya yang berjarak ratusan tahun tersebut memperhadapkan manusia pada pilihan: kehendak atau kemestian. Kepedihan semacam apa yang membuat manusia mengukir nama di nisannya sendiri?
“Tak ada kepastian yang bertahan
Kita telah kehilangan kepercayaan kepada keabadian
Semua hanya sementara: cinta kita, kesetiaan kita.
Kita hidup di tengah kesementaraan segala. Di luar
rumah terus menunggu seekor serigala.”
Baca: Kartografi Ingatan: Wahana Media dan Wacana Kaum Muda
Baris-baris puisi Subagyo dan pertunjukan teater Shinta berusaha menyusun tubuh-tubuh kepedihan dengan motif perjalanan manusia yang tidak berujung. Berlapis-lapis kemestian diletakkan seperti irisan bawang. Wangi dan perih. Walau daya ungkap keduanya cenderung menggunakan bahasa keseharian, tetapi dengan itu pula ia berhasil mengatakan apa yang kerap gentar kita ucapkan: semua yang bersifat sementara hanya metafora.
Motif Ekonomi
Apakah rantau dan kolonialisme memiliki relasi? Walau amat tipis dihadirkan dalam pertunjukan Passompe’, tulisan ini berusaha melihat motif lain. Ketika masyarakat Bugis dan Makassar perlahan mendominasi pesisir Kalimantan sejak berabad lalu, apakah dapat disebut kolonialisme atau merujuk pada metafora tumbuhan paku? Kolonialisme erat kaitannya dengan kebijakan atau praktik memperoleh kendali politik penuh atau parsial atas wilayah lain. Lantas wilayah tersebut dijadikan pemukiman dan mengeksploitasinya secara ekonomi.
Kuatnya tradisi rantau di masyarakat Bugis dan Makassar menghasilkan beberapa karya yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Pada tahun 1828, ditemukan peta Asia Tenggara yang dibuat orang-orang Bugis. Selain itu, disusun pula kitab undang-undang Hukum Pelayaran dan Perniagaan yang dikenal sebagai Amanna Gappa pada tahun 1676. Dalam pembuka lontara tersebut dituliskan: “Sepakatlah orang di Ujung Pandang pada serambi mesjid, menyepakati peraturan berperahu dalam hal berdagang. Maka itulah yang dinamai undang-undang. Karena takdir Tuhan yang Maha besar dan Maha tinggi jualah, maka sepakatlah tiga suku: Orang Wajo, Orang Bone, dan Orang Makassar.” Kitab undang-undang tersebut diadopsi menjadi hukum laut yang dirumuskan dalam berbagai konvensi internasional.

Selain itu, tidak terhitung pula jumlah pesan dalam lontara yang dapat dihubungkan dengan tradisi rantau dan bagaimana masyarakat Bugis dan Makassar membangun ambisi mereka. Seperti pesan yang terdapat pada kalimat berikut, Narekko sope’ku ri taue, aja mumelo mancaji ana’guru. Ancaji punggawako. Namauni punggawa parampo’ muna. Pesan tersebut dapat ditafsir menjadi, jika hendak merantau ke negeri asing, jangan ingin dijadikan anak buah. Jadilah pemimpin, walau hanya pemimpin perampok. Ambisi semacam ini bukan tanpa pasal. Dalam sejarahnya, banyak perantau Bugis dan Makassar yang akhirnya harus bertaruh nyawa. Sebut saja Daeng Mangalle–saudara Sultan Hasanuddin, yang memutuskan merantau ke Ayuthia, Siam. Dengan ditemani 60 keluarga Makassar, ia membangun pemukiman di daerah tersebut. Hingga suatu waktu, 10.000 pasukan Kerajaan Siam yang dibantu 40 serdadu Inggris, Portugis dan Perancis menyerang sekitar 300 pasukan Daeng Mangalle. Walau kalah, pasukan tersebut mendapat pengakuan atas keteguhannya. Ia dibenci sepenuh hati tetapi dihormati dengan khusus.
Telur dan Retak: Bagian Lain dari Passompe’
Setelah pertunjukan Passompe’ yang berdurasi sekitar enam puluh menit selesai, saya memberi selamat kepada aktor, kru, dan sutradara lalu lekas menyempatkan duduk di gazebo. Merapikan beberapa impresi dan pengalaman selama pertunjukan di buku catatan. Sesaat kemudian, datang beberapa pirsawan dan percakapan tentang teater dan keaktoran terjadi. “Setiap dialog dan gerak yang dilakukan aktor, itu harus menjadi bagian dari dirinya.” Buka Halim HD yang segera ditanggapi Luna Vidya dengan sejumlah referensi serupa. Saya menjadi penyimak yang berusaha meraba-raba pengalaman dan pengetahuan mereka.
Percakapan yang terus bertumbuh tersebut mengingatkan saya dengan adegan kecil dalam pertunjukan Passompe’ ketika seorang aktor membawa susunan piring berwarna merah dan menjatuhkannya tepat di tengah panggung. Bagian paling bawah dari tumpukan itu retak dan pecahannya tidak berdaya di panggung hingga pertunjukan selesai. Selaras dengan itu, ada mula kisah La Galigo diawali dari kehampaan–sebuah kekosongan yang melahirkan telur kosmik. Retak dan telur adalah sebuah metafora yang sederhana untuk melihat pertunjukan Passompe’ secara sepihak, telur yang retak dari luar berarti kehancuran dan telur yang retakannya berasal dari dalam berarti kehidupan. Ketika melakukan sompe’, kita seakan menggenggam telur di tangan. Dari mana retakan telur di tanganmu berasal?
Editor: Agus Mawan W