Kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan tanah masih menjadi masalah yang dihadapi petani. Konflik agraria masih terus berlangsung. Petani masih berhadapan dengan korporasi dan pemerintah, bahkan dengan keduanya sekaligus. Akibatnya, petani sering kehilangan tanah yang merupakan sumber penghidupan bagi mereka.
Di Meiwa, Kabupaten Enrekang, saya menemui seorang kakek, yang bagian bawah bibirnya terpaksa dijahit karena mendapat pukulan dari aparat kepolisian, yang mengawal proses pengukuran lahan. Ratusan petani menghalau tim pengukuran masuk ke tanah mereka yang akan dimasukkan ke dalam lokasi Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara (PTPN XIV). Mereka tak ingin tanahnya digusur, sebagaimana petani lainnya yang sudah mendapat giliran terlebih dahulu. Kakek tersebut bergabung bersama petani yang lain mempertahankan tanah mereka dari renggutan PTPN XIV. Saat protes berlangsung, tujuh orang petani ditangkap dan banyak warga yang harus menderita karena mendapatkan tindakan kekerasan.
Di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, para petani harus berhadapan dengan perusahaan tambang nikel PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) yang memaksa masuk dan beroperasi di pulau kecil ini. Mereka menolak, khawatir mata air rusak. Laut tercemar dan kebun beserta tanamannya sirna ketika tambang beroperasi.
Perusahaan membujuk warga untuk melepas lahan. Namun, tawaran uang ratusan juta hingga milyaran rupiah tak membuat para petani tergiur. Di atas kebun, sebagian warga mengantungi sertifikat, taat membayar pajak setiap tahun, dan telah menguasai lahan selama puluhan tahun.
Namun, perusahaan akhirnya menggusur. Kebun berisi tanaman seperti cengkih, mete, dan kelapa ditumbang. Para pemilik melapor ke polisi, tetapi laporan mereka menguap. Penggusuran lahan di Wawonii sering terjadi, tapi proses hukumnya tak pernah berlanjut. Usaha warga menghalau dan mempertahankan tanah dijawab dengan kekerasan, hingga intimidasi yang berujung trauma di warga.
Dua cerita di atas mewakili banyak kasus serupa yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Para petani harus kehilangan tanah, tempat mereka lahir, tumbuh, dan bercocok tanam demi hidup dan melanjutkan generasi.
Petani dan Kehampaan Hak
Di banyak daerah Indonesia, kita menyaksikan bagaimana konflik agraria masih terus berlangsung. Konflik petani, masyarakat adat melawan perusahaan perkebunan, proyek infrastruktur pemerintah, dan investasi yang sering kali merampas tanah petani.

Petani yang sudah menguasai dan mengelola tanah digusur tanpa ampun. Saat mereka protes, dijawab dengan tindakan kekerasan. Dilaporkan ke polisi. Ditangkap. Ditahan. Diintimidasi bahkan tak jarang di antara mereka harus meregang nyawa. Hak mereka sebagai warga negara diabaikan. Keadaan inilah yang disebut oleh antropolog Belanda Ward Barenschot dkk, sebagai kehampaan hak.1
Istilah kehampaan hak (rightlessness) merujuk pada keadaan ketiadaan, atau hampir tiadanya perlindungan hukum yang efektif atas kepentingan seseorang. Kehampaan hak dimaknai sebagai situasi ketika pengakuan dan pengejawantahan hak tidak dilakukan.
Secara hukum (de jure), penduduk di Indonesia tidaklah hampa hak karena ketentuan hukum tersebut telah memuat berbagai macam perlindungan atas hak warga negara. Misalnya, hak petani atas kepemilikan tanah, hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan hak untuk berpartisipasi serta berpendapat. Namun dalam implementasi aktualnya, ketentuan hukum tentang hak-hak tersebut tak dihormati, dilindungi, bahkan dipenuhi.
Sederhananya, kehampaan hak berarti ketiadaan implementasi (de facto) akan hak-hak yang secara tertulis telah diakui (de jure).
Dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah, hak petani atas tanah sering kali diabaikan oleh pemerintah (state) dan korporasi. Padahal, petani yang juga warga negara, di dalam dirinya telah melekat hak yang harus dihormati (respect), dilindungi (to protect), dan dipenuhi (to fill).
Masih menurut Ward Barenshot dkk, kehampaan hak bersumber pada tiga hal. Pertama, hak atas tanah yang dibatasi. Pengakuan hak atas tanah yang sangat terbatas menjadi salah satu alasan, mengapa pemerintah dan perusahaan sering menggusur tanah masyarakat atau mengapa petani sangat mudah untuk kehilangan tanah.
Pengakuan yang lemah merupakan kelanjutan warisan kolonial Belanda yaitu asas domein verklaring. Asas ini menyatakan bahwa semua tanah yang tak bisa dibuktikan kepemilikannya menjadi domain atau milik negara. Asas ini digunakan untuk menggerogoti hak tanah adat, dan memungkinkan pemerintah kolonial Belanda untuk mengklaim kepemilikan sebagian besar tanah di dan luar Pulau Jawa untuk memberi perusahaan perkebunan dan pertambangan Eropa akses murah ke tanah.
Setelah merdeka, orde baru bahkan setelah dua dekade reformasi, asas ini masih dipertahankan, termasuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Di kasus PTPN XIV di Enrekang, Luwu Timur, dan Takalar, alasan sebagian warga tak memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat menjadi dalih perusahaan untuk mengambil alih, bahkan menggusur tanah masyarakat.
Demikian halnya dengan konflik kehutanan. Pada kasus konflik kehutanan di Kabupaten Soppeng, polisi kehutanan sering kali melaporkan masyarakat dengan tuduhan perambahan dan pengrusakan hutan. Padahal keberadaan masyarakat sudah ratusan tahun dan menetap di dalam daerah yang belakangan diklaim sebagai kawasan hutan.
Di konflik pertanahan di Pulau Rempang, pemerintah merasa berhak merelokasi warga dengan alasan, bahwa warga tak memiliki alas hak yang kuat. Sementara, masyarakat sudah mendiami Pulau Rempang selama ratusan tahun secara turun temurun.

Kedua, permainan hukum lewat pintu belakang (backdooring of laws). Kerangka hukum Indonesia terkait tanah dan perkebunan merupakan percampuran kompleks yang terdiri dari beberapa undang-undang pokok seperti, UU Pokok Agraria tahun 1960, UU Penataan Ruang tahun 2007, dan Undang Undang Perkebunan tahun 2014. Terdapat pula undang-undang tambahan, instruksi presiden, peraturan menteri, dan peraturan pelaksanaan. Hubungan dan hierarki antara undang-undang pokok ini, juga berbagai jenis peraturan lainnya, sangatlah tidak jelas sehingga menimbulkan ambiguitas dan kebingungan.
Ambiguitas dan kebingungan ini menciptakan praktik ‘hukum lewat pintu belakang’; sifat tata kelola tanah yang berlapis-lapis, memungkinkan elit ekonomi yang kuat dan terkoneksi dengan baik mampu menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.
Manfaat praktis dari dan politik dari pintu belakang ini, terletak pada ketersembunyiannya yang mengurangi beban dan persyaratan regulasi negara, sembari mempertahankan legitimasi dari regulasi tersebut. Demokrasi Indonesia yang dikuasai oligarki memungkinkan kepentingan bisnis dapat dengan mudah masuk lewat pintu belakang regulasi negara.
Di kasus tambang di Pulau Wawonii, praktik ‘hukum lewat pintu belakang’ digunakan oleh perusahaan. Salah satunya dengan mengabaikan bahwa Pulau Wawonii, masuk kategori pulau kecil yang tak boleh ditambang berdasarkan undang-undang pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil.2
Terakhir, hubungan kolusi bisnis-politik. Hubungan yang mesra antara bisnis dan politik membuat para aktor melakukan pengelakan secara sistematis atas regulasi. Hubungan informal antara kelompok bisnis dan kelompok politik dengan mudah memanipulasi peraturan yang akhirnya mengesampingkan hak warga negara.
Hubungan bisnis dan politik punya sejarah panjang di Indonesia. Bisnis sangat bergantung pada kekuasaan politik sementara kekuasaan politik sangat membutuhkan kelompok bisnis sebagai donatur atau investor dalam setiap pegelaran Pemilihan Umum, yang meminta biaya yang sangat mahal.
Di zaman kolonial Belanda, banyak kegiatan ekonomi membutuhkan dukungan negara demi mengakses lahan dan tenaga kerja. Ketika Indonesia telah merdeka, hubungan mesra antara kekuasaan negara dan aktivitas ekonomi masih bertahan, bahkan berlanjut setelah reformasi seperti saat ini. Kemesraan antara kekuasaan negara dan bisnis bersekongkol dan mengorbankan kepentingan masyarakat.
Dua dekade setelah reformasi–nyatanya–tak merenggangkan hubungan bisnis dan politik. Keduanya masih tetap mesra dan saling membutuhkan. Akses ke otoritas negara untuk mendapatkan proyek dan investasi masih menjadi faktor penentu keberhasilan para pebisnis (oligarki), sementara aktor politik membutuhkan sokongan dana guna membiayai pertarungan politik baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun ke tingkat nasional.
Izin pertambangan dan konsesi yang muncul tanpa persetujuan warga serta pengabaian prosedur perizinan menjadi contohnya. Banyak izin yang secara prosedural bermasalah, tetapi terbit.
Di kasus lingkungan hidup, lemahnya pengawasan dan pemberian sanksi menjadi contoh yang relevan. Pelanggaran nyata atas lingkungan hidup dibiarkan begitu saja dan tanpa sanksi yang memberikan efek jera.
Hubungan bisnis dan politik yang sangat kolusi ini melahirkan peraturan baru yang berpihak pada kepentingan bisnis seperti UU Cipta Kerja. Memfasilitasi penghindaran terhadap peraturan yang akhirnya melemahkan supremasi hukum.
Kehampaan hak adalah kenyataan yang terus terhampar di depan mata. Di tengah banyak konflik, perlu membangun kesadaran kolektif sehingga memunculkan gerakan yang lebih luas. Penguatan hak atas tanah perlu dilakukan. Penguatan kelembagaan yang mampu memberikan perlindungan hak dengan kuat dan efektif, juga mesti dilakukan. Jauh lebih penting adalah memutus hubungan kolusi bisnis dan politik yang sudah mendarah daging dalam politik Indonesia. Ini tak mudah tetapi perlu dilakukan secara bersama-sama.

Halo! Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Catatan kaki
- Ward Barenschot dkk, Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia, Buku Obor, 2023. ↩︎
- UU Nomor 1/2014 ↩︎
Keterangan foto sampul: Saparuddin (40 tahun) memandang lahan keluarganya yang telah ditanami sawit PTPN XIV di Maroangin, Kabupaten Enrekang/Eko Rusdianto/Mongabay Indonesia

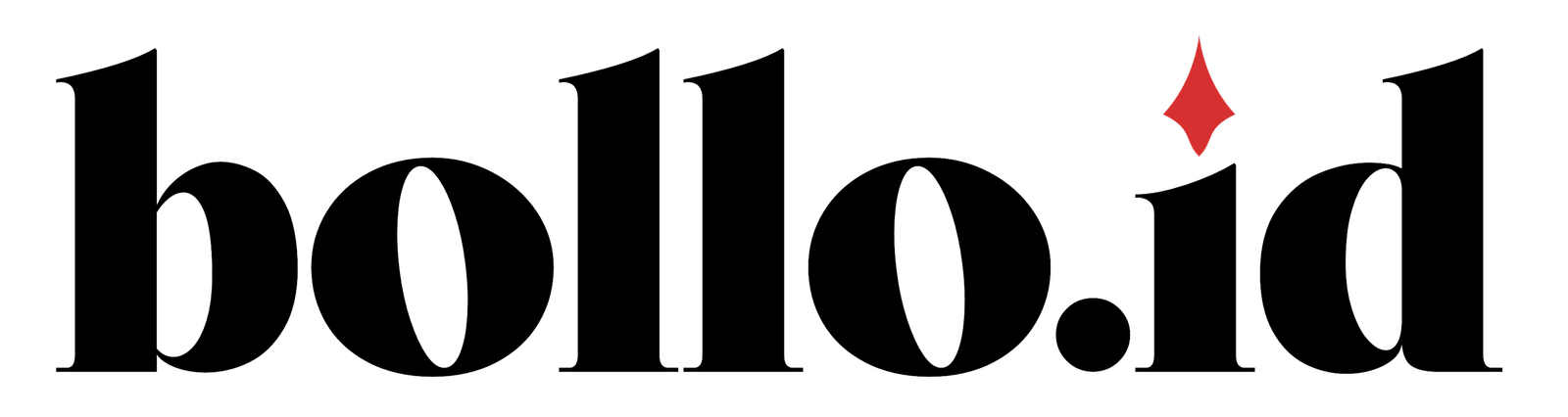










[…] Baca essay lain: Kehampaan Hak Petani […]