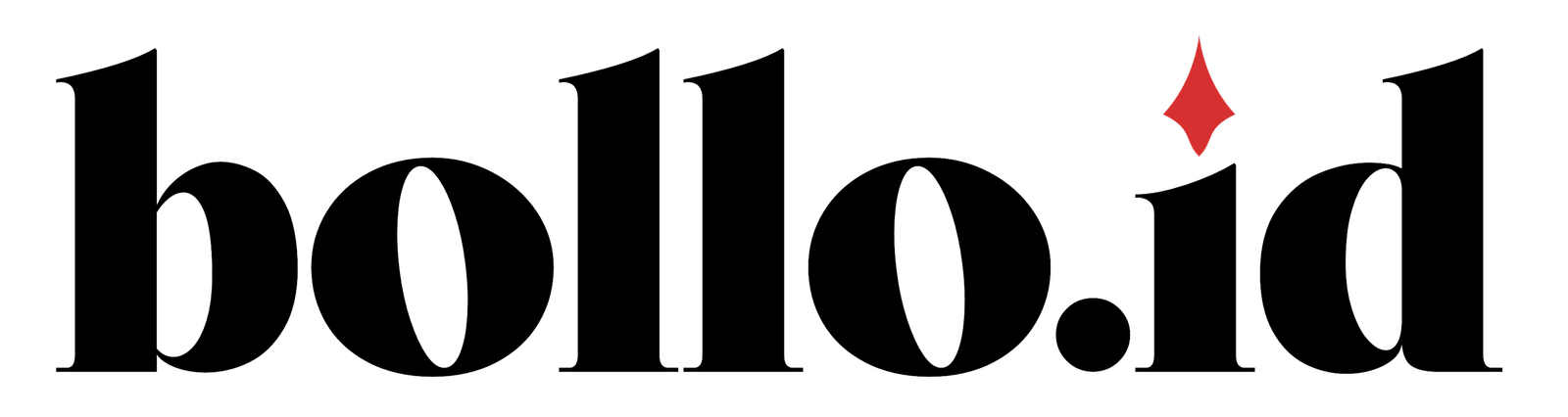Bollo.id — Persil-persil lahan petani menjadi lahan yang tidak lagi produktif dalam waktu belakangan saat itu. Bagi lahan yang harus bergantung pada skema tadah hujan, berdoa atau berpangku tangan sama-sama merupakan kebuntuan.
Jika hujan tidak turun, sulit membayangkan petani dapat bergiat mengupayakan proses produksi di atas tanah—hingga mereproduksi diri dan keluarganya. Bayangan menu makanan esok hari di meja dapur seolah menjadi obat bius belaka yang jawabannya sedang tersesat di tengah rimba persoalan.
Tidak hanya bagi lahan, kebutuhan konsumsi harian mereka turut terganggu karena kebutuhan air yang sulit. Tanah yang telah lama didiamkan membuat beberapa bapak-bapak tani mencari aktivitas lain demi menyiasati hidup yang semakin mencekik.
Bagi yang memiliki hewan ternak, mereka akan sibuk makkampi dengan sejumlah peliharaan sapinya. Sementara lahan-lahan yang memiliki sistem saluran irigasi juga mesti berjudi dengan praktik-praktik monopoli atas air.
Mereka yang tidak teraliri darah istimewa (bangsawan) terpaksa harus menekan aspirasi demi sesuap air. Seperti dalam ungkapan, “disini dek adaji uttang (mata air), tapi tidak bisa dipakai sebelum na pakai puang (orang yang dianggap punya derajat sosial yang lebih tinggi), kecuali kalau dibeli bah na kasi jaki,” ucap bapak K, di salah satu desa T.
Saat itu bapak K harus menerima tanamannya kehausan sembari melakukan protes secara diam-diam dengan mencela pola relasi sosial yang sedang bekerja dalam watak feodalistik yang telah mendarah daging.
Dalam kondisi krisis, proses komodifikasi atas sumber penghidupan (untuk diperjual belikan) menjadi lebih runcing ke bawah. Bagian pisau yang tajam perlahan-lahan menyentuh dan seolah hendak memutus nadi petani kecil untuk mencari makan.
Hal ini turut mempertegas privatisasi air yang bekerja sangat lokal dalam lanskap kerumitan akses atas sumberdaya yang terkerangkai dalam konteks relasi kuasa (antara bangsawan dan rakyat biasa).
Privatisasi menyakinkan bahwa kebebasan individu untuk melakukan pembatasan-pembatasan melalui seperangkat hukum formal (maupun non formal, misalnya tradisi) merupakan hal alamiah (Mansfield 2008, dalam Jurnal Wacana Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi dan Resistensi).
Baca juga artikel sebelumnya: Bagian 1: Fenomena di Balik Kekeringan
Meminjam argumen dari David Mosse (dalam Bekker 2010): air merupakan medium bagi setiap relasi sosial yang dialirinya. Privatisasi atas air menunjukkan dimensi relasi kuasa yang sedang bekerja sangat lokal sebagai buah dari otoritas kekuasaan.
Dengan demikian, sebagaimana disebutkan Foucault (1978): ada di mana-mana dan relasional. Bapak K harus menerima nasib tereksklusi dari sumberdaya air karena tidak memiliki kekuatan penyeimbang.
Pada kasus yang lain di pedesaan kawasan pegunungan Lompobattang, kekeringan panjang pada musim kemarau juga turut mempengaruhi produktivitas lahan warga sekaligus hasil panen tanaman hortikultura.
Kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi para petani tentunya adalah gagal panen, kerugian di beberapa lahan pertanian menjadi nyata adanya sebab rasio antara input produksi dan income yang didapatkan menjadi tidak stabil atau bahkan tidak ada yang bisa diharapkan dari lahan sama sekali.
Beberapa penampakan soal kekeringan pada lahan-lahan tertentu dapat dilihat dengan jelas saat hendak menuju pintu rimba pendakian Gunung Lompobattang.
Tanaman hortikultura banyak yang dibiarkan membusuk begitu saja di lahan-lahan warga (mulai dari kol, bawang, kentang, dan lain-lain) sambil beberapa petani menekan kecemasan sedikit demi sedikit berharap agar musim hujan segera datang.
Para petani biasanya harus membanting pikiran demi menyiasati kekhawatiran-kekhawatiran, beberapa di antara mereka memilih untuk menempuh jalan setapak demi setapak masuk sekitar ratusan meter ke dalam hutan untuk mencari hasil-hasil hutan seperti madu dan getah pinus (atau mungkin masih banyak jenis hasil hutan yang lain).
Mulanya hasil hutan ini hanya dijadikan untuk memenuhi keperluan rumah tangga, namun juga dapat menjadi pilihan dalam kondisi terdesak seperti saat ini untuk dijual ke pasar demi mendapatkan uang tunai (meskipun mungkin dengan harga yang tidak seberapa).
Selain itu, saat saya mengantar Amma ke kebun untuk memetik bawang, ia berucap “Kebunnya orang ini nak, keluarga ji yang punya saya bantu saja untuk dipanenkan”. Siasat-siasat bertahan hidup sebagai buruh tani dalam relasi kekeluargaan turut mempengaruhi upah yang dapat diterima oleh Amma.
Namun hal tersebut dilakukan untuk setidaknya sedikit menutupi kebutuhan-kebutuhan harian sekaligus kerugian gagal panen pada lahan miliknya yang kering. Lahan-lahan tersebut tentu tidak dapat diharapkan, terlebih lagi jika luasnya hanya secuil.
Kekeringan di beberapa titik mata air juga turut mempengaruhi timbulnya ketegangan antarwarga meskipun tidak secara terbuka.
Warga di atas dan warga di bawah (berdasarkan penuturan warga setempat untuk membedakan warga yang tinggal tepat di kaki gunung dekat hutan dan warga yang tinggal berdekatan dengan jalan raya) akhirnya saling memperebutkan titik-titik mata air yang dapat menopang pertumbuhan tanaman di lahan-lahan yang kering saat ini.
Ketegangan harian pada musim tertentu secara bersamaan dapat meruntuhkan pandangan yang melihat desa sebagai komunitas yang damai.
Kebutuhan untuk bertahan hidup dan juga demi mengembalikan modal biaya pertanian — hingga dorongan untuk mendapatkan keuntungan — dari lahan pertanian yang sedang ditanami membuat warga di bawah secara intens naik ke kaki gunung untuk memberi tawaran uang tunai dengan jumlah yang relatif besar agar mata air yang dimanfaatkan warga di atas juga dapat didistribusikan hingga ke lahan-lahan yang ada di bawah.
Meskipun tawaran ini mendapat penolakan dengan berbagai macam pertimbangan, khususnya berbagi air secara luas dalam kondisi terjepit saat ini sama halnya mengikat leher sedikit demi sedikit.
Ketimpangan pembagian air tersebut tentu dapat dengan mudah memperkokoh ketegangan sosial. Kondisi-kondisi yang semakin tegang dan menjepit para warga juga turut mempengaruhi karakter orang desa dalam mengurusi persoalan masing-masing pada lahan mereka.
Karakter orang di pedesaan tergambarkan secara sederhana dengan melihat kesibukan mereka mulai dari pagi hingga sore hari atau bahkan kadang-kadang hingga larut malam, orang-orang desa sibuk dengan urusan masing-masing dalam menyiangi kebun yang dianggap masih bisa diharapkan untuk dipanen minimal demi menutupi kebutuhan subsistensi hingga mengontrol laju air setiap saat demi memastikan sumber air tetap dapat sampai pada kebun mereka.
Kesibukan secara sendiri-sendiri di sepanjang hari dalam mengurusi kebun akhirnya menguras banyak energi setiap kelompok keluarga rumah tangga dan lebih memilih untuk beristirahat setelah pulang dari kebun hingga berakibat pada berkurangnya porsi untuk berinteraksi antar sesama orang desa.
Pola yang mungkin sering kita dapati di kota-kota, akhirnya mengemuka juga di desa-desa dalam bentuknya yang berbeda. Orang-orang lebih condong menyelesaikan persoalan bersama secara pribadi.
Misalnya, jika di kota kita dapat menjumpai cara orang-orang dalam menyiasati kemacetan adalah dengan mengumpat menggunakan berbagai varian bahasa kasar, entah umpatan-umpatan tersebut ditujukan kepada siapa, padahal barang tentu tidak ada umpatan yang bisa menyulap kemacetan menjadi jalan yang lengang seketika.
Hal lain sebagaimana yang pernah ditulis oleh Nurhady Sirimorok, “di kota-kota, untuk mengatasi kemacetan, warga dipaksa menyelesaikan persoalan sendiri-sendiri: membeli kendaraan yang lebih nyaman, dengan pendingin dan pengharum, penganan dan minuman, bahkan pemutar dan pelantang musik — apa pun yang bisa membuat seseorang semakin nyaman di tengah kemacetan.”
Pola yang sama dapat kita jumpai di pedesaan, dalam bentuk yang jauh lebih khas, masing-masing petani dengan pekerja keluarga akan berusaha sendiri mengatasi persoalan pada masing-masing kebun mereka, mulai dari masalah pengairan, kekeringan, dan seterusnya.
Para petani yang tinggal dekat dengan hutan secara aktif akan terus berusaha mencari titik mata air baru hingga ratusan meter ke dalam hutan yang lebat untuk dapat dimanfaatkan demi menutupi kebutuhan akan air atau mereka juga secara teknis kadang memilih untuk membuat penampungan air di dekat kebun hingga rumah masing-masing yang dapat menopang konsumsi air rumah tangga juga lahan dan tanaman.
Kesibukan yang lain adalah menyiangi kebun yang biasanya menguras banyak energi dan waktu bagi para anggota keluarga rumah tangga. Mereka biasa memulai aktivitasnya mulai dari pagi hingga sore.
Sedangkan pada malam harinya beberapa anggota keluarga rumah tangga terpaksa mengurangi jatah tidur untuk terus mengontrol perairan dan bahaya-bahaya yang memungkinkan dapat mengancam pertumbuhan tanaman hingga melakukan penyemprotan kebun secara rutin dan berkala demi menghalau serangan hama.
Padahal, serangan hama begitupula kekeringan selalu dialami beramai-ramai oleh petani yang tidak serang-pilih pada satu kebun saja. Kekeringan akan menimpa seluruh kebun, tidak hanya kebun tetangga.
Lantas, seperti apa kita menempatkan pola gotong royong di pedesaan yang banyak dipercaya oleh banyak orang?
Pada kasus kekeringan yang terjadi di kawasan kaki gunung Lompobattang selain diakibatkan oleh adanya mekanisme musim kemarau yang bekerja cukup panjang, hal lain yang juga dapat diidentifikasi karena terjadi penyumbatan serius pada sistem hidrologis yang sedang bekerja untuk menyediakan cadangan air pada musim kemarau.
Aliran air yang saling berkejaran di bawah permukaan tanah mengalami ekstraksi cukup serius oleh tanaman-tanaman dengan sifat individualitas yang kokoh dalam mengonsumsi air.
Tentu saja penyerapan volume air yang berlebihan oleh satu jenis tanaman saja memungkinkan terjadinya pemborosan sumber daya yang sedang sulit hingga tidak dapat didistribusikan pada tanaman yang lain — pun jika ada pasti jumlahnya hanya sepersekian atau terbilang sangat sedikit.
Sebagaimana penampakan di kaki gunung Lompobattang, dengan mudah kita dapat menemukan deretan pohon-pohon menjulang tinggi berupa pinus, baik yang berdiri kokoh di pinggir-pinggir jalan maupun yang bergerombolan di dalam gugusan hutan.
Entah dengan mekanisme seperti apa pohon-pohon itu bermunculan dan memenuhi kawasan gunung Lompobattang khususnya di pos 1 (istilah para pendaki).
Anggapan awal yang kemungkinan dapat kita lacak, deretan pohon pinus tersebut hadir memenuhi desa melalui pintu-pintu “konservasi” yang menilai bahwa arsitektur hutan dengan vegetasi tutupan lahan pohon pinus dapat menghindarkan kawasan tersebut dari erosi atau malapetaka-malapetaka yang tidak diundang masuk ke desa.
Landasan ini turut dikawinkan dengan program-program penghijauan yang hampir setiap saat menyerbu demi membangun citra hutan lestari nan indah. Meskipun pada awalnya ditanam dalam kawasan-kawasan hutan negara, tetapi seiring berjalannya waktu mereka lalu memberontak hingga keluar merambah kebun-kebun warga di sekitar hutan hingga ke pinggir jalan raya.
Hutan pinus seringkali menjadi primadona wisata yang merembes pada booming-nya foto-foto ala anak muda yang ramai berseliweran di kanal-kanal Instagram dengan gaya potret memamerkan diri dikepung pohon pinus.
Seringkali foto-foto semacam itu diberi istilah folk oleh orang-orang kebanyakan lalu berlagak indie dan estetik bersama pemandangan alam yang raya. Namun, pernahkah kita bertanya kira-kira prospek sosial seperti apa yang ditawarkan oleh segerombolan pinus bagi sumber penghidupan petani di sekitar hutan, khususnya sumber daya air? Keindahan alam bagi orang-orang kota tentu dapat berjarak cukup dekat dengan bencana bagi orang-orang desa.
Salah seorang peneliti melihat skema penanaman pinus justru dapat menjadi bencana bagi para warga, misalnya di dua desa Kompang dan Gantarang, kini mengalami kesusahan karena pinus (Sirimorok 2018). Pohon pinus dianggap memiliki kekejaman tertentu baik pada keanekaragaman hayati hingga pada manusia itu sendiri.
Buah pinus sering kali dapat kita temukan jatuh berserakan di sekitar pohonnya, lalu kadang-kadang dipungut karena bentuk buahnya yang unik hingga sering disulap menjadi gantungan kunci atau sejenis hiasan di tubuh, namun ternyata buah-buah tersebut jika diamati lebih jauh dapat tumbuh dengan mudah untuk menopang pohon pinus lain yang sudah tumbuh besar, bahkan di lahan kritis sekalipun.
Sisi individualitas yang rakus dari pinus ditunjukkan dengan cara mencuri seluruh energi makanan yang tidak akan dibagi-bagi lagi pada pohon atau tanaman jenis lain.
Hal ini dapat kita lihat saat menemukan satu pohon pinus, pastilah selalu diikuti oleh segerombolan pohon pinus yang lain saling berdempetan. Pohon-pohon yang mencoba tumbuh di sekitarnya hanya akan tercekik lalu mati. Begitupun nasib dari rerumputan dan belukar.
Belum lagi pohon pinus seolah punya kekuatan dahsyat dalam menghalau air hujan untuk menyentuh tanah karena desain daunnya membuat tugas dalam menyimpan dan mengolah makanan bergantung sepenuhnya pada sumber air yang terus menerus dihisap tanpa pilih-pilih selama ada kesempatan.
Terlebih jika kondisinya sangat mendesak untuk berbagi air seperti pada musim kemarau yang panjang ini, semakin sedikit curah hujan yang turun dari langit secara bersamaan membuat pohon pinus juga akan semakin giat dan rakus merampok air. Kerakusan dalam mengonsumsi air juga dapat ditemukan dari desain akar tunggang yang menjalar ke dalam tanah lalu meluas.
Hal ini dapat menjadi asumsi awal bahwa salah satu penyebab serius yang menyumbat sistem hidrologis di kaki gunung Lompobattang karena adanya kawanan pohon pinus yang tumbuh semakin lebat dengan pola pengisapan air yang jauh lebih serakah tujuh kali lipat lebih banyak dibandingkan pohon-pohon jenis lainnya.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Pohon pinus selalu memiliki kekuatan untuk memanfaatkan air baik dari atas langit hingga dari dalam bawah tanah. Inilah yang dapat kita lihat ketika memulai pendakian di dalam rimba Gunung Lompobattang, beberapa titik mata air yang biasa dimanfaatkan oleh para pendaki juga para warga mengalami kekeringan yang parah.
Pohon-pohon pinus bisa saja tumbuh lebih lebat dan besar di kaki gunung, namun harga yang harus dibayar adalah akan melenyapnya sedikit demi sedikit sumber mata air.
Ketika mendengar keresahan warga yang tinggal berdampingan dengan kawasan hutan Gunung Lompobattang, menurut penuturannya pernah ada orang dari luar desa (berdasarkan istilah warga) yang pernah datang dengan keinginan menggarap lahan tepat di pos 1 melalui skema pengetahuan yang simpang siur.
Seperti mempertegas tanda-tanda yang kentara pada lanskap hutan sebagai bukti kerja sekaligus penguasaan yang sebelumnya telah ada di masa lampau. Merekonstruksi sejarah adalah skema yang dipilih oleh orang luar tersebut demi menopang keinginan dalam membuka dan menggarap beberapa petak lahan yang ada di sana (pos 1) berdasarkan ingatan yang ada.
Asumsinya dibangun berdasarkan pengetahuan bahwa siapapun yang memiliki klaim mengetahui seluk-beluk sejarah seluruh sisi gunung tempat lahan pernah dimanfaatkan di masa lalu dari generasi ke generasi, meskipun pengetahuan tersebut juga harus ditopang oleh kemampuan dalam meyakinkan banyak orang.
“Sebab pengetahuan, khususnya klaim atas silsilah dan lanskap hutan, merupakan sumber kekuasaan sekaligus hasil dari kekuasaan. Orang yang berkuasa dianggap dapat membuat klaim mereka bertahan, sementara pengetahuan orang lain yang tidak berkuasa diabaikan dan klaim mereka ditolak, (Tania Li: 2020).”
Namun, untungnya klaim tersebut dapat ditolak secara mentah-mentah oleh warga yang tinggal di sana hingga mampu menghalau penggarapan lahan dari orang luar tersebut.
Menariknya dalam kasus ini, penulis mendengar bahwa ternyata di kaki gunung para warga sekitar telah melakukan pengavelingan sejak lama sebagai kawasan yang bisa dimanfaatkan oleh warga, ketegangan yang pernah muncul dan berhasil diselesaikan tersebut membuat mereka (warga sekitar) yang kawasannya merasa terancam turut melakukan perlawan dengan mengusir orang luar tersebut.
Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan yang patut digali lebih jauh adalah bagaimana awal mula skema pengavelingan itu muncul? Hingga praktik harian seperti apa yang mengemuka dari pengavelingan tersebut?
Apakah pengavelingan tersebut mengandaikan lahan hutan dapat diakses bersama oleh warga sekitar atau justru menimbulkan tindak-tanduk eksklusi antar warga yang satu dari yang lain (baik dengan sifatnya yang permanen maupun sementara)?
Artikel ini sebelumnya telah dimuat di Suluhpergerakan.org. Redaksi Bollo.id, menerbitkannya kembali dan membagi menjadi beberapa artikel.
Editor: Sahrul Ramadan