I
Siang itu, 14 Januari 2021, langit sedang gerimis. Seorang petani kemiri menanjaki sebuah bukit, yang berhadapan langsung kampung kelahiran petani itu, Aholeang, satu dusun penghasil kemiri di Desa Mekkatta, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Orang-orang menjuluki bukit indah itu, Tanete Bajo.
Tanete Bajo serupa mangkuk terbalik. Punggungan melebar, melandai dan kebanyakan diisi bidang datar. Warga mengubah bukit itu menjadi kebun kemiri dan ladang padi. Di sela ladang padi dan pohon-pohon kemiri yang menjulang, jalan tanah setapak meliuk ke puncak. Jalan inilah, saban hari, dijajal warga menuju kebun masing-masing, termasuk petani berusia 31 tahun itu.
Nama petani itu, Jasman.
Kebun milik Jasman, terletak di seberang Tanete Bajo. Hujan masih mengguyur, ketika Jasman mencapai kebunnya. Rabas hujan menghujam sekujur tubuhnya yang lusuh. Tas yang dia pikul, lalu disandarkan ke rumah kebun. Di depannya, kemiri sudah berserakan. Petani dua anak itu menunduk, memungutnya dengan tekun. Biji, demi biji.
Bagi Jasman, kemiri merupakan keajaiban ekonomi. Kemiri seperti diciptakan untuk tak kenal musim panen. Duit jutaan bisa datang hampir saban bulan. Siang itu, warga lain juga melakukan hal sama di kebun. Beratus meter dari kebun, istri dan anak-anak mereka menghabiskan hari di kampung.
Belum lima menit Jasman bekerja, tanah menggelinjang kuat. Menyentak tubuh Jasman ke tanah. Suara gemuruh mengisi langit. Dari arah punggungan bukit, longsoran meluncur begitu cepat. Jasman tahu, itu linor — bahasa Mandar untuk gempa. Dadanya berguncang hebat.
Jasman berlari pulang, melupakan tas berisi bekal dan air minum dari istrinya, Sartika. Dia melebarkan langkahnya, cepat-cepat.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melansir, gempa itu berkekuatan 5,9 Magnitudo. BMKG mengkategorikannya sebagai gempa pembuka (foreshock), berpusat di darat, hanya beberapa kilometer dari tempat Jasman.
Ketika mencapai puncak Tanete Bajo, Jasman menenangkan diri. Nafasnya megap-megap. Dia sungguh lelah, tapi tak ada alasan untuk berhenti. Dalam benak Jasman, hanya ada nasib Sartika dan dua anaknya yang masih kecil.
Di hadapannya, melintang retakan panjang. Punggungan bukit itu merekah tak karuan. “Mungkin bisa masuk tiga jari,” kata Jasman. “Kelihatannya dalam.”
Apakah bukit itu akan longsor? Tak mungkin pikir Jasman. Dia terus melanjutkan perjalanan, memotong jalur, lalu mengarah lurus ke rumahnya, yang berhadapan Masjid Aholeang.
Di Kampung, orang-orang telah berhamburan keluar rumah. Ketakutan mengubah wajah mereka, menjadi pucat. Jasman dan keluarganya akhirnya bertemu.
II
Di sisi barat lembah Tanete Bajo — ratusan meter dari rumah mungil Jasman, orang-orang berkumpul di depan rumah. Mereka berencana mendirikan tenda, melintangi jalan menuju Rui. Rumah batu mereka kebanyakan sudah retak. Tapi, Lukdin keukeuh melarang mereka. “Jangko di sini! Ayo kita ke atas gunung.”
Bersama istri dan tiga anaknya, Lukdin panik menuju puncak Tanete Bajo. Semua tetangganya — tanpa bertanya-tanya, ikut. Dari tua sampai anak-anak. Blok berisi 17 rumah itu, praktis tanpa penghuni.
Lukdin, adalah pengumpul kemiri di Aholeang. Dia juga nyambi, mengurusi kebun kemiri miliknya. Rempah itu lah yang bikin dapur di rumahnya terus mengepul tiada henti.
Belasan meter dari belakang rumah Lukdin, sebuah rumah batu berdiri. Penghuni rumah itu merupakan sepasang keluarga: Nurlia bersama sang Suami, Rahmat, dan Nurfatma, putri berusia 4 tahun dari mendiang suami pertama Nurlia. Kala itu, Nurlia sedang mengandung adik Nurlia. Dia sedang hamil 5 bulan. Bersama Nurfatma, Nurlia ikut rombongan Lukdin. Rahmat tidak ikut.
Di puncak, rombongan Lukdin berpencar mengitari rumah kebun. Menggelar tenda, menghalau hujan yang belum redah. Makin sore, dingin mulai menggerayangi tubuh mereka. Sedang dari arah barat, matahari perlahan meringkuk di balik pelupuk Selat Makassar.
Mendekati petang, Jasman kembali ke kebun, hanya buat mengambil tas dan bekal yang tak sempat dia cicipi. Ketika di puncak, dia melihat kembali rekahan itu. Tanah telah menimbun celahnya, walaupun garis rekahan itu masih terlihat jelas. Sesekali gempa kecil muncul, tapi Jasman tak ambil pusing.
Sepulang dari kebun, Jasman bertemu Nurlia. Ibu itu hanya kenakan sarung. “Oh, kamu juga di sini?”
“Iya. Saya panik sekali, jadi saya lari ke sini,” kata Nurlia.
Jasman meninggalkan Nurlia. Jasman pulang melewati jalan biasa. Semakin mendekati kampung, hari semakin gelap. Dari arah bawah, suami Nurlia muncul. “Di mana Mamaknya Fatma?” tanya Rahmat ke Jasman.
Jasman melempar telunjuknya. “Di atas.”
“Di mana jalan ke atas?”
“Lurus saja masuk,” kata Jasman. “Ada nanti jalanan, belok kiri naik.”
Rahmat bertemu Nurlia dan putrinya. Mengajak mereka kembali ke rumah.
Baca juga: Bagaimana Media di Makassar menjadi Mimbar Kebencian terhadap Keragaman Gender dan Seksual?
III
Dari Ale-ale, dusun pesisir Mekkatta, Sarbidin melesat ke Aholeang, menembus hujan. Lelaki itu menyusul istri dan anak-anaknya yang sedang berkebun, di bukit sisi barat Tanete Bajo. Setelah gempa mengejutkan mereka, mereka takut meninggalkan kebun. Di kebun itu, puluhan orang bernasib serupa. Hujan yang luar biasa lebat menjebak mereka di sebuah rumah kebun.
“Kami tidak bisa kembali. Di kebun mki situ, terjebak,” kata Sarbidin.
Ketika sampai, hari sudah gelap dan membutakan Sarbidin. Hujan belum berhenti. Di seberang bukit, semburat lampu dari sebuah rumah berkilau. Itu rumah Nurlia. “Alhamdulillah, ada orang di sana,” Sarbidin bergumam.
Usai salat magrib, Jasman bersama tetangganya, mulai mendirikan tenda darurat di tengah gempuran hujan. Rahmat bersama Nurlia turun ke kampung Jasman.
Di Aholeang, Rahmat santer dikenal sebagai tukang rumah yang pandai. Rahmat meminang Nurlia, pada tahun 2019. Usia Rahmat dua kali lipat dari usia Nurlia. Keluarga itu, menemui Jumaluddin, seorang guru sekolah dasar, berusia separuh abad.
Jumaluddin bukan sekadar guru sepuh yang sebentar lagi bakal pensiun. Dia pernah mengepalai dusun Aholeang selama 16 tahun. Warga Aholeang, selalu menghormati pendapatnya.
“Bagaimana ini? Kalau Pak Tukang tidak ke tenda kami, silahkan ke Rui,” Jumaluddin mengingatkan Rahmat.
“Insyaallah, kami nanti ke Rui.”
Rahmat berasal dari pesisir Mekkatta, sementara Nurlia berasal dari Rui. Di Rui, kedua orang tua Nurlia, tinggal.
Ayah dan Ibu Nurlia, sudah usia sepuh. Usia Massagala, sang Ayah bahkan sudah seabad. Pendengarannya sudah terganggu, meskipun tubuhnya masih kuat. Sedang, Ibunya, Jumriah, mulai ringkih.
Dua hari sebelumnya, Nurlia sekeluarga berkunjung, membawa Nurfatma, si cucu yang setiap saat dirindukan Massagala dan Jumriah. Ini seperti tradisi akhir pekan bagi Nurlia dan kedua orang tuanya. Hanya untuk bertemu dan saling menanyakan kabar.
Malam itu, di hadapan Jumaluddin, Rahmat dan Nurlia pamit pulang. Tapi, mereka tak pernah sampai ke Rui.

Hujan makin deras. Tenda-tenda telah berdiri. Jumaluddin, terus merapal doa-doa. Dia tak ingin tidur. Dia punya firasat, gempa susulan — yang lebih hebat — segera tiba.
Bersamanya, 46 orang ikut mengungsi. Jumaluddin terus mengingatkan mereka, agar tidak panik, bila gempa susulan datang. “Jangan juga kita terlepas membaca Lailahailallah, apabila terjadi.”
Di puncak Tanete Bajo, Lukdin dan keluarganya kedinginan. Anak-anaknya terus menangis. Mereka lapar. Kepanikan sore tadi, bikin mereka lupa bawa makanan. Sedikitpun. Lukdin juga baru sadar, tak mengenakan baju. Celana yang menempel, salah satu harta yang bisa terbawa.
Lukdin lekas membawa anak-anaknya ke rumah kebun milik Habu, saudaranya. Di situlah, mereka meringkuk kedinginan, menahan lapar.
IV
Tengah malam, desas-desus akan ada perampokan menyebar ke telinga warga Mekkatta. Perampokan itu kabarnya, hanya menyasar rumah-rumah yang ditinggal mengungsi. Terdengar seperti kejahatan yang terorganisir tapi belum satupun ada bukti. Kepala Desa Mekkatta, Kasman berkeliling, sekaligus melihat kondisi Desa yang dia pimpin. Perkampungan bak kampung mati.
Sebetulnya, Kasman telah membawa keluarganya untuk mengungsi di rumah keluarganya, sebuah rumah batu yang bersambung dengan bangunan kayu, di bukit perkebunan sawit, puluhan meter dari Kantor Desa. Kasman khawatir akan ada tsunami.
Ketakutan itu tidak mengada-ada, Mekkatta memang berada di pesisir Teluk Lebani, diapit dua tanjung ‘besar.’ Jarak laut dengan perkampungan pesisir — tempat Kasman tinggal — hanya beberapa langkah, tetapi pada sisi timur — juga hanya beberapa ratus meter, merupakan daratan tinggi dengan bentangan gunung raksasa.
Usai ‘patroli’, Kasman kembali bergabung bersama keluarganya. Di ruang tengah, Kasman berbaring beralas tikar spons. Dia akhirnya tertidur pulas.
Ketika runtuh

I
Dini hari, 15 Januari 2021, Sartika, membangunkan Jasman, di dalam rumah. Anaknya tak berhenti menangis. Di luar, Jumaluddin menyuruh warga membangunkan anggota keluarga yang tertidur. Sementara, orang-orang mengira Rahmat, Nurlia, dan Fatma sudah sampai di Rui.
Di rumah kebun, Sarbidin, melarang siapapun keluar. Di puncak Tanete Bajo, Lukdin bersama warga lain, diserang kantuk dan lapar. Sementara, hujan makin deras.
Jasman keluar mendekap anak terkecilnya. Rengekan anaknya perlahan berhenti.
Pukul 02.28 Wita, gemuruh ledakan menyambar telinga Lukdin. Dia terperanjat. Lalu, gempa menggelinjang ke arahnya, begitu cepat. Begitu kuat. Listrik padam. Lukdin terus mendekap anaknya. Semakin kuat, semakin erat.
Dari perkampungan, Jumaluddin dan warga terus berteriak. Memekik bersama bunyi genteng yang terhempas-hempas dan dinding yang runtuh ke tanah.
“Allahu Akbar! Allahu Akbar!”
“Lailahaillallah! Lailahaillallah!”
Dalam kekalutan, ledakan kembali merebak telinga Lukdin. Punggungan Tanete Bajo, runtuh dan mengarah ke kampung. Di bawah, Jumaluddin dan warga lain tak tahu, bongkahan batu raksasa dan tanah sedang bergelindingan ke mereka. Bunyi letusan berkali-kali, seakan-akan bukit itu meletus.
Dalam rumah kebun, hati Sarbidin gamang, tapi senantiasa menenangkan keluarganya yang dirundung ketakutan.
Dari arah rumah Nurlia, rintihan seorang perempuan mengejutkan Sarbidin. Hanya teriakan itu, yang terdengar jelas.
“Ahhhhhh….”
“Aaaahhhhhh….”
Lalu teriakan itu lenyap, bersama gemuruh longsor.
Malam itu, Sarbidin mengira, orang-orang Aholeang tak ada yang selamat dari maut.
***
Mustaman berhasil loncat ke bagian belakang rumah, yang terbuat dari kayu. Gempa, dalam sekejap mata merontokkan tembok rumah itu, tempat Kasman bersama Nurdina, istri Kasman dan dua anaknya sedang tertidur.
Kasman sempat mendekap putrinya, melindunginya dari reruntuhan bata. Dia meregang nyawa tak lama kemudian. Istrinya sempat koma dan dirawat di Rumah Sakit Majene. Selama dua minggu, Nurdina bahkan tak tahu, suaminya telah mendahuluinya. Bagi warga Mekatta, Pakde — sapaan karib Kasman, telah menuntaskan tugasnya, sebaik-baiknya.
Baca juga: Hidup di Tengah Gempuran Tambang Nikel: Cerita Nelayan Luwu Timur ‘Terciprat’ Limbah [1]
Apa pemicu gempa Mamuju-Majene?
Hasil perhitungan BMKG menyebut, lindu maut malam itu, berkekuatan 6,2 M. Berpusat (episentrum) di darat, sekitar Desa Bambangan, Kecamatan Malunda, dengan kedalaman 10 km. Inilah gempa utama (mainshock) dari serangkaian gempa sebelumnya.
Dampak parah akibat gempa dimulai dari batas Kecamatan Sendana-Ulumanda, Majene, hingga Kota Mamuju. Ribuan rumah warga rusak. Beberapa tempat terjadi longsor dan mengisolir warga di beberapa daerah pelosok. Di Malam itu, beberapa warga yang tertidur tak pernah bangun kembali.
Di jantung Mamuju, dalam sergapan gelap warga berhambur keluar rumah, menuju lokasi tertinggi. Berlari, menunggangi motor, atau mengendarai mobil. Menyelamatkan diri adalah utama. Di tepi jalan, warga yang keluarganya terkubur runtuhan meminta tolong kepada orang-orang yang berlari kepanikan. Tim SAR belum datang. Hanya ada warga yang saling berjibaku menarik warga yang terjebak runtuhan.
Data yang diperoleh Pemerintah menunjukkan ribuan orang mengalami luka-luka. 107 orang meninggal, 96 di antaranya dari Kota Mamuju, jantung pemerintahan Sulawesi Barat. Puluhan ribu warga mau tak mau mengungsi.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia melansir, rentetan gempa di Majene-Mamuju, sejak 14 Januari, dipicu aktivitas sesar naik Selat Makassar, yang berada di pesisir dan lepas pantai sisi barat Sulawesi. Di wilayah ini, ada unsur tektonik, dikenal dengan jalur lipatan dan sesar naik (fold and thrust belt) yang menerus ke arah darat. Pemetaan mutakhir tahun 2017, menyingkap, terdapat tiga segmen Sesar Naik Selat Makassar: Segmen Tengah, Segmen Mamuju, dan Segmen Somba. Pertahun, peniliti memperkirakan sesar ini bergeser, sekitar 4–10 mm.
“Ada beberapa klaster pusat-pusat gempa, mencerminkan bahwa sumber gempa di jalur ini sangat aktif,” kata Daryono, Koordinator Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG.
“Jika, mencermati aktivitas kegempaan di wilayah Sulawesi Barat, tampak di daratan dan lepas pantai, banyak sekali aktivitas gempa dengan berbagai magnitudo dan kedalaman.”
Sumber gempa sesar naik di wilayah ini, berulang kali telah memicu gempa kuat yang merusak dan membangkitkan lambong tallu, pengetahuan lokal di Mandar tentang tsunami. Katalog gempa BMKG mencatat, sudah enam gempa merusak sejak tahun 1967: tahun 1967, 1969, 1972, 1984, 2020, dan 2021. Gempa tahun 1967 dan 1969, disusul tsunami.
“Sebenarnya, tahun 1968 juga tsunami. Cuman 1968 itu hanya sekitar 30cm. Tidak tercatat sebagai sebuah tsunami yang ‘sementereng’ Tsunami Aceh. Seperti tsunami yang menimpa Palopo, kira-kira tahun 1992,” kata Achmad Yasir Baeda, dari Center of Disaster Engineering (CoDE) Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (Unhas). “Itukan tidak pernah kedengaran.”
Wilayah Sulbar merupakan kawasan tertekan atau terkompresi. Ia masuk dalam lengan selatan pulau Sulawesi. Melansir penelitian tahun 2006, Daryono bilang, lengan selatan Sulawesi bergerak berlawanan arah jarum jam. Artinya, ada pergerakan ke arah barat, menyebabkan kawasan pesisir dan lepas pantai Sulbar, mengalami pemendekan (shorthening).
Gerakan tektonik semacam itulah, kata Daryono, membentuk zona lipatan dan sesar naik. “Sehingga bagi para ahli kebumian, terjadinya gempa merusak di Majene dan Mamuju bukanlah hal aneh.”

Setelah linor
Merasa aman, Jasman bersama warga lain menuju rumah Nurlia, sekadar memastikan. Dengan senter, Jasman berusaha menerawang, apa sesungguhnya yang telah terjadi. Jasman paling depan menyusur gunungan longsor, tetapi ledakan dari arah bukit menghentikan kaki mereka.
“Tidak usah lanjutkan perjalanan,” kata Jasman. Di sekitar lokasi itu, mereka pasang tenda.
Sekitar setengah enam pagi, Lukdin meninggalkan rumah kebun. Dia dan keluarganya begitu lapar. Lukdin ingin mengambil beras dari rumahnya. Tapi pemandangan di bawah yang dia saksikan membuat Lukdin pupus. Bongkahan batu sebesar rumahnya telah menghantam rumahnya. Rumah tetangganya pun, tak kelihatan. Lenyap. “Aih, tertimbun…”
Lukdin kembali. Untung saja, pepohonan mati di sekitar, menyediakan banyak jamur tiram buat santapan keluarga itu. Lukdin mencabut jamur-jamur itu dan merebusnya dengan garam. Lukdin, istri dan anak-anaknya begitu lahap. “Habis itu jamur, airnya mi diminum. Daripada mati. Mau turun, takut.”
Di bawah, Rasyid, warga Aholeang menemui Jumaluddin, mengajak untuk mengosongkan kampung.
“Kenapa?” tanya Jumaluddin.
“Ada longsor tadi malam. Ada rumah di sana tertimbun.”
“Betulkah?”
“Iya”
“Mari kita sama-sama lihat.”
Jumaluddin berangkat. Belum jauh keluar dari pengungsian, paras Tanete Bajo mengejutkan dirinya. Separuh bukit itu benar-benar berhamburan. Tepi puncak patah dan membentuk barisan tebing baru. Di belakang kampung Jumaluddin, longsoran meluluh ke sisi kanan dan kiri. “Astagfirullah Aladzim.”
Jumaluddin, segera menuju rumah Nurlia, tetapi batu-batu raksasa telah menimbun. Jumaluddin tidak menemukan sesuatu. “Kalau anak ini tidak keluar tadi malam — tidak mengungsi — pasti mati.”
Pagi itu, orang-orang Aholeang memutuskan mengungsi ke bukit perkebunan sawit, beberapa kilometer ke arah pesisir. Di batas dusun, longsoran menutup akses jalan. Dalam sergapan hujan, rombongan Jumaluddin melipir dan memutari sungai. Mereka mempercepat langkah, seolah-olah gempa terus mengejar. Yang berusia muda dan relatif kuat memapah orang-orang berusia sepuh dan ibu hamil. Atau paling tidak, menenteng barang dan makanan semampu yang mereka gapah.
“Betul-betul menderita batin,” peluh Jumaluddin.
Di puncak Tanete Bajo, Lukdin dan lainnya, menuju Rui, pada sore hari.
Tanpa nisan
Di Rui, keluarga Nurlia menanti cemas. Bahwa mungkin, Nurlia tak meninggalkan Aholeang, dan memilih bersama warga di sana, tetapi, bahwa apakah mereka benar-benar aman, terus jadi pertanyaan yang mengusik keluarga Nurlia.
Jelang sore, jaringan telepon membaik. Jumaluddin menerima telepon dari Keluarga Nurlia di Rui. Suara di ujung telpon itu bertanya ke Jumaluddin. “Kau lihat dia?”
Tapi, di lokasi ungsi, tak satupun orang melihat Nurlia, atau Rahmat, ataupun Nurfatma. “Wai…. Mati. Pasti hancur. Pasti tertimbun,” kata Jumaluddin.
Di hari itu, Rahmat, Nurlia, Nurfatma dinyatakan hilang.
Minggu, 17 Januari, Tim Pencarian dan Penyelamatan gabungan mulai mencari mereka. Tim menyisir di antara lautan longsor. Anjing pelacak dikerahkan. Di hari pertama, Tim tak menemukan sesuatu. Di hari kedua. Hari ketiga. Hari keempat, tetap sama. Tanda keberadaan mereka tak ditemukan. Di sisi lain, kondisi longsor yang labil, membayahakan keselamatan tim. Pencarian akhirnya disetop. Tiga orang itu dinyatakan hilang hingga sekarang.
Di hari penghentian pencarian, saya menemui keluarga Nurlia di tenda pengungsian. Massagala, sedang salat. Saya menunggunya. Hari itu, doa Massagala begitu panjang. Dia sudah tahu, sang cucu kesayangan telah tiada bersama putrinya dan menantunya. Dia juga tahu, tak akan ada batu nisan yang tiap usai tradisi lebaran akan dia ziarahi.
BELI MERCHANDISE BOLLO.ID
Ragu dan takut
Setiba di Rui, Lukdin bergegas bergabung dengan keluarga Jabir. Ketika mereka berjumpa, hari sudah malam dan hujan belum reda. Lukdin lalu menggelar tenda buat tempat berlindung anak dan istrinya.
Lukdin dan Jabir bersaudara. Kampung Jabir menjadi satu-satunya tujuan bagi Lukdin setelah longsoran batu di Aholeang, melumat kampungnya. Dari puncak Tanete Bajo, Lukdin bersama puluhan warga lainnya harus melipir agar mencapai Rui dengan aman.
Rui dan Aholeang dulunya merupakan satu daratan, sebelum batas administrasi seolah-olah memisahkan mereka di dua daratan berbeda. Ia berada di dataran tinggi, puluhan menit dari tempat tinggal Lukdin. Perkampungan di Rui terbagi dua blok. Di blok satu, rumah-rumah berderet satu sisi, sepanjang punggungan yang landai dan melengkung. Sementara blok lain — kampung Jabir, berbidang datar.
Gempa dini hari, telah merontokkan rumah-rumah orang Rui. Meninggalkan rekahan, memanjang di perkampungan punggungan, tempat Irsan bermukim. Membelah pondasi dan lantai rumah-rumah. “Bisa masuk kaki di retakan itu,” kata Irsan.
Irsan lahir di Rui, 38 tahun silam. Usia muda, dia menikahi Hijrah dan melahirkan 5 anak yang tekun. Saban hari, Irsan mengurus kemiri dan kakao, komoditi yang menghidupi keluarganya. Banyak kenangan yang dilalui keluarga Irsan di sini. Tapi, dia harus pergi. “Takut kita tinggal di sana.”
Irsan bersama tetangga, mengosongkan kampung dan menuju kampung Jabir. Selama tiga hari dua malam, mereka mengungsi dan tak ingin meninggalkan Rui. Tak ada siapapun dari luar mendatangi mereka. Mereka pun terlalu takut beranjak. Malam hari adalah saat-saat yang menakutkan. Bayangan gempa terus mengusik mereka. “Menderita mka di situ. Pasang tenda, baru hujan terus. Ndak bisa tidur,” kata Jabir.
Pagi hari yang cerah, warga Rui akhirnya beranikan diri meninggalkan kampung dan bergabung bersama warga Aholeang — yang tak lain adalah keluarga mereka, berpisah dari rumah, ternak, harta benda, dan matapencarian mereka. Keputusan yang pahit. Sepanjang perjalanan menuju pusat Desa Mekatta, orang-orang mencari jawaban, apakah kelak mereka bisa kembali?
Sebuah tanah penuh harapan
Di awal Februari 2021, saya kembali ke Mekkatta. Saya ingin melihat Aholeang, atau paling tidak, saya bisa menemukan kepingan cerita dari Malam mengerikan itu. Pakai sepeda motor, saya akhirnya mencapai Aholeang. Tanete Bajo menyambut siapapun kala memasuki kampung itu. Parasnya yang sekarang membuat siapapun bergidik. Gempa pada 15 Januari, dini hari itu mengubahnya jadi ‘situs’ mengerikan. Di hadapannya, kaki saya tak henti gemetar.

Separuh Tanete Bajo amblas dan pecah berkeping-keping. Di puncak, bak kue bolu yang telah diiris, berubah jadi barisan tebing cadas yang panjang. Pohon kemiri, padi, dan segalanya yang di permukaan tanah menyungsep dan terkoyak-koyak bersama batu-batu gamping raksasa. Menghujam rumah-rumah dan mengubur apapun sejauh mana longsoran itu berhenti. Kepingan ornamen-ornamen gua yang patah bertebaran seperti jatuh dari langit.
Ketika berdiri di bukit seberang, longsoran Tanete Bajo begitu panjang dan luas. Rumah kebun di puncak, tempat Lukdin mengungsi masih berdiri dan hanya terpaut belasan meter dari tepian longsor. Di sisi kiri longsoran, adalah titik di mana Nurlia bersama putri dan suaminya tertimbun. “Kalau jalan ki ke Rui, ada ji dilewati rumahnya,” kata Fachri, dari relawan CKCK.
Relawan CKCK, adalah gabungan relawan dari mahasiswa dan pencinta alam di Tanah Mandar. CKCK adalah slang untuk patung-patungan duit.
Menurut ahli gempa, longsor batu di malam itu adalah bencana susulan akibat gempa. Seolah-olah, kejadian itu adalah bencana yang berbeda dan kesialan yang berbeda.
Dari Aholeang, hingga Tappalang, Mamuju merupakan kawasan bentang alam karst. “Hampir sama dengan di Maros dan Pangkep. Tapi umur batuannya lebih tua dibanding di Majene,” kata Adi Maulana, dari Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin. “Sebenarnya, komposisi kimianya itu sama. Sama-sama punya komposisi kalsium karbonat, sehingga menyebabkan gampang terjadi proses pelarutan.”
Di bawah permukaan tanah, Adi menduga, banyak gua-gua yang terbentuk dari pelarutan batuan karbonat. “Saya lihat dari struktur batuannya, ini mudah longsor atau runtuh. Apalagi ada getaran gempa,” kata Adi.
Sebagian bentukan batuan di Majene berumur Pra Tersier yang terdiri batuan metamorf dan meta sedimen. Beberapa tempat berumur Tersier, yang berupa batu gamping hingga batuan sedimen. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, batuan itu telah mengalami pelapukan, yang bersifat urai, lunak, lepas, belum kompak (unconsolidated) dan memperkuat efek guncangan gempa.
Aholeang dan Rui kini tanpa penghuni. Beberapa warga kembali barang sebentar, hanya sekadar memberi makan piaraan atau ternak yang mereka tinggal kelaparan. Di Aholeang, saya bertemu seorang warga yang datang mengecek rumahnya. Rumah dia memang masih berdiri, tapi tembok dan langit-langit hancur tak karuan, seperti hati pemiliknya.
Terlepas dari parasnya yang sekarang, Aholeang, sesungguhnya kampung yang menyenangkan dengan hamparan tanah subur dan sejuk sepanjang waktu. Rumah-rumah berdiri rapat saling berhadapan, di antara jalan setapak yang meliuk. Di sepanjang jalan, ada banyak batu gamping menyembul dari tanah.
Kampung ini ditemukan para peladang nomaden dari Tamaindung, kampung teratas di Mekkatta. Mereka lalu mendirikan perkampungan dan meneruskan tradisi berladang nomaden. Sampai tahun 60-an, ketika tradisi itu tergerus praktik pertanian baru, Aholeang, seumpama tempat persinggahan bila masa jeda berladang tiba.
Puluhan gua menyebar di sembarang tempat hingga ke Rui. Gua-gua inilah dijadikan identitas kampung bagi pemukim awal. Aho berarti ‘di atas’ dan Leang berarti ‘gua’. “Jadi, kami sebenarnya ini, mendirikan kampung di atas gua,” kata Jumaluddin.
Orang Aholeang percaya, terdapat gua yang melintas di bawah perkampungan, bagai ular raksasa. Yang menurut dugaan mereka, bakal amblas bila kembali diguncang gempa. Sementara di bawah Tanete Bajo yang amblas itu, menurut warga, tak kurang terdapat 10 gua.
Sebagian gua diberi nama. Gua Tallu Lotang, salah satunya. Dalam perut Tallu Lotang sungai mengarus. Kala kemarau, orang-orang Aholeang menyusuri gua itu, untuk berburu udang dan ikan sidat. Di gua lain, air dari Rui, mengarus masuk ke dalam gua, lalu, seperti keajaiban, keluar di Aholeang melalui mulut gua.
Di Aholeang, tanah adalah ruang hidup. Tempat yang tepat memupuk harapan. “Seandainya tidak ada kejadian seperti ini, kami tidak keluar. Kami dengan Aholeang, sudah terikat. Karena sumber kami semua dari Aholeang,” kata Jumaluddin. Di Aholeang, Jumaluddin adalah generasi keempat.
“Apa yang membuat, Om, terpaksa meninggalkan Aholeang?” tanya saya.
“Perasaan kami, setiap kembali, pokoknya gelisah. Kami, khususnya masyarakat Aholeang, sudah trauma, untuk kembali ke kampung. Kami sangat ketakutan. Banyak orang dulu, setiap datang di kampung kami, bilang, ‘Kamu tidak takut tinggal di sini, karena kamu di atas gua?’. Tetapi, sudah ada di dalam hati, jangan-jangan kalau ini gempa, kita benar-benar tenggelam. Karena kita berada di atas gua. Ya mau diapa lagi. Tidak ada tempat lain. Apalagi tempat matapencarian kami di sana.”
VIDEO
Nestapa Nelayan di Tengah Gempuran Tambang Nikel
Naskah ini telah terbit di situs Mongabay Indonesia, dalam versi sudah sunting. Untuk membacanya silahkan klik di sini.

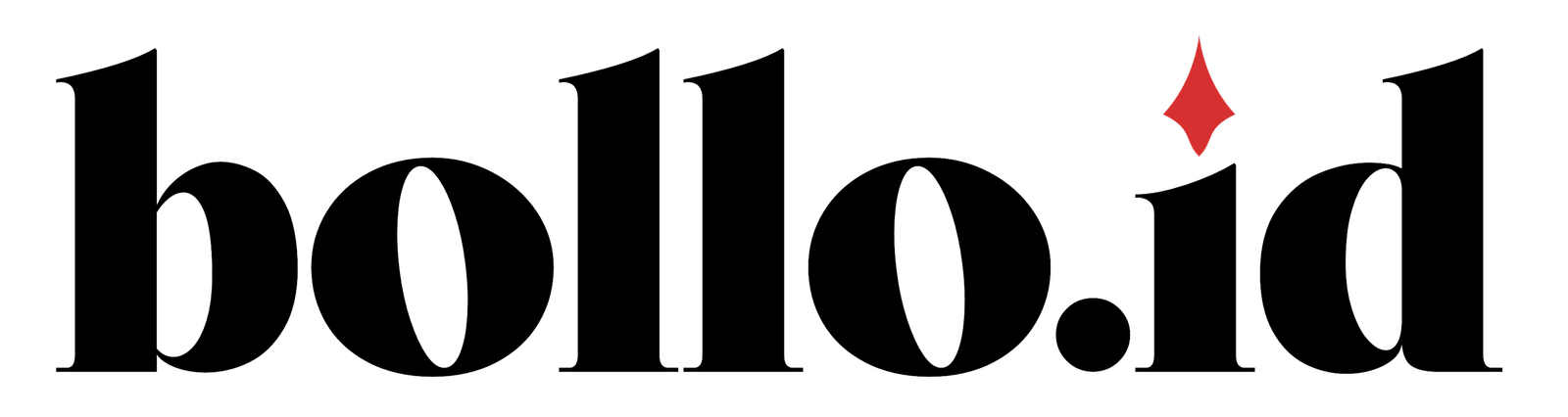







[…] Baca laporan mendalam dari Agus Mawan: Linor: Amuk Gempa di Majene […]