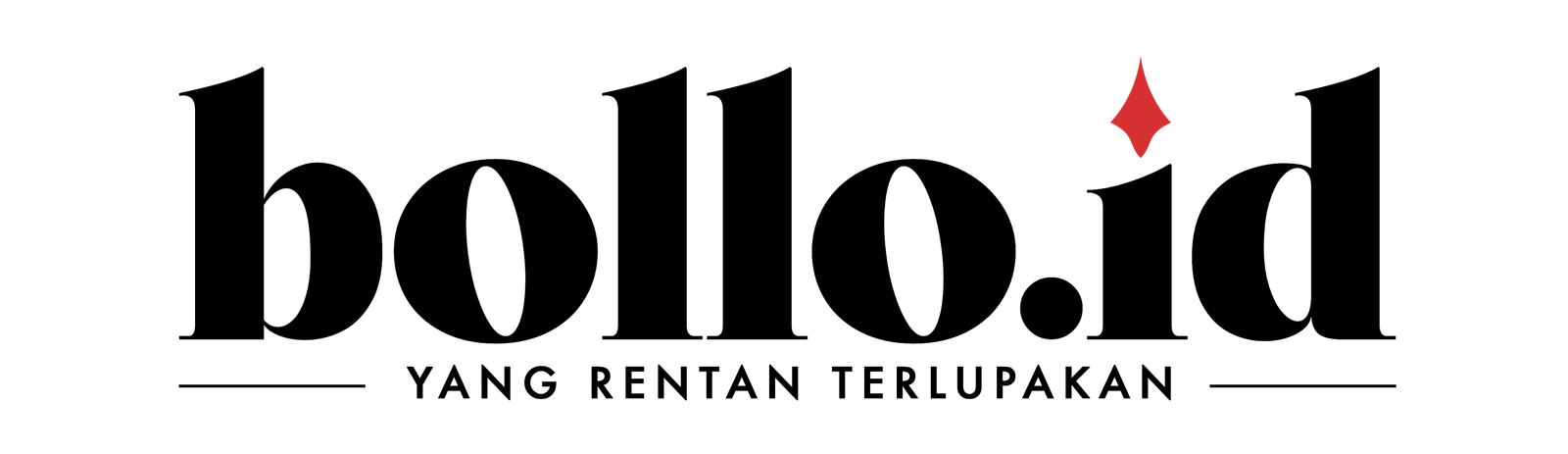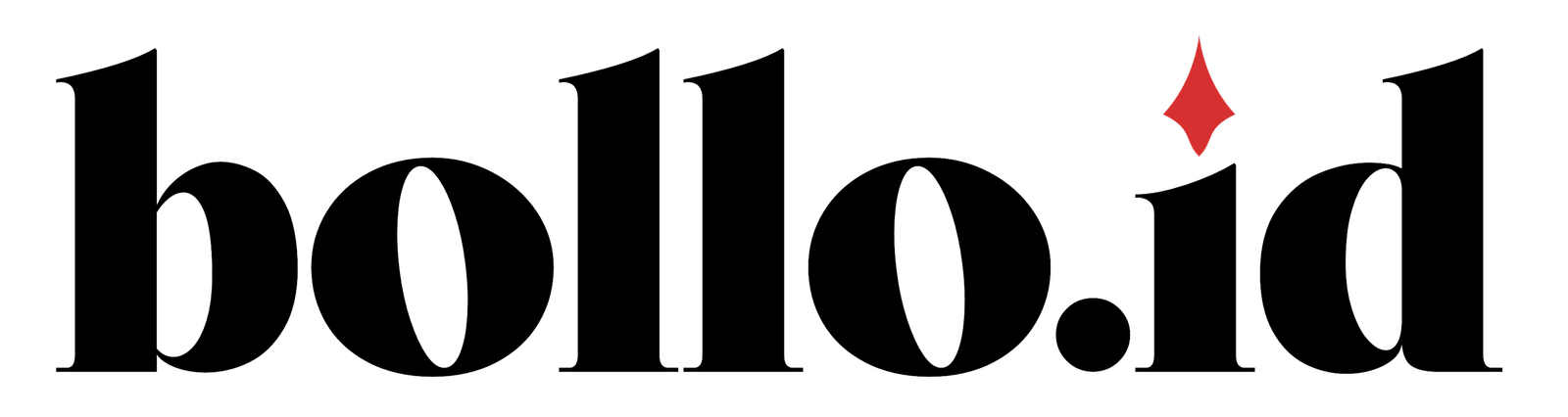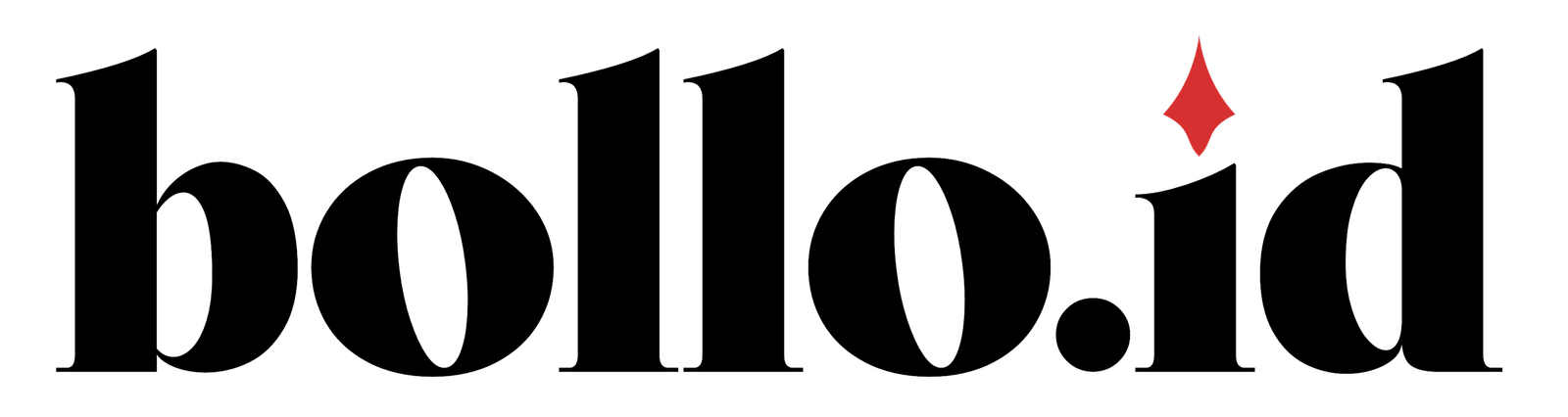Di balik layar, suara dari kelompok minoritas gender dan seksual dibutuhkan para kontestan yang bertarung dalam ajang pemilihan umum.
Tetapi, ketika berada di panggung pesta politik, mereka justru dikorbankan demi meraup suara.
Ujaran kebencian
Diskriminasi
Teror
Kekerasan
Persekusi
Berkelindan bersama stigma dan menjadi penghalang pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara.
Mereka yang Dibenci Tapi Dibutuhkan
Beberapa keterangan tempat kami samarkan, atas permintaan narasumber transpuan, berikut dengan identitasnya, dengan alasan keamanan diri.
Dalam laporan ini kami tidak menggunakan akronim LGBT dan menggantinya sebagai “kelompok minoritas gender dan seksual”. Dalam beberapa hal kami menggunakan akronim LGBT jika berasal dari pernyataan narasumber atau dokumen.
Lima tahun lalu, Ratih – bukan nama sebenarnya – hadir dalam suatu pertemuan elit-elit partai politik di Sulawesi Selatan. Dia dijemput oleh utusan petinggi partai, beberapa jam sebelum pertemuan.
Utusan itu mengajak Ratih berkeliling menemui para pejabat partai yang lain.
Di hadapan para petinggi partai itu, Ratih diminta berbuat sesuatu: Menggalang dukungan dan suara dari kelompok minoritas gender dan seksual kepada salah satu pasangan calon kepala daerah yang mereka usung.
“Berapa anggotamu?” tanya petinggi partai itu kepada Ratih.
“Berapa bisa kau kasihkan saya suara?”
Ratih adalah seorang transpuan yang hidupnya kerap dibayangi ketakutan. Perlakuan diskriminasi, intimidasi, dan persekusi sudah terlalu sering dia dapatkan dari berbagai kelompok di Sulsel, terutama yang menolak keras keberadaan kelompok minoritas gender dan seksual.
Namun di tahun politik, Ratih dan kawan-kawannya justru sangat dibutuhkan. Sering kali utusan dari petinggi partai datang menemui kelompok minoritas gender dan seksual. Meminta dukungan suara agar kontestan mereka bisa menang.
Mereka, kata Ratih datang membawa janji-janji. Bahwa jika kelak calon itu terpilih, kelompok Ratih akan mendapat perlindungan. “Tapi ujung-ujungnya ketika duduk, Ya.. bye-bye.”
Saya menemui Ratih di sebuah Kafe di Kota Makassar, pada suatu sore awal Januari 2024. Saat menceritakan kisahnya, Ratih mengangkat tangannya menutupi separuh wajahnya.
Di tengah keramaian, dia begitu khawatir.
Kekhawatiran Ratih tidak mengada-ada. Rentetan kejadian yang pernah menimpa Ratih selama ini, masih membekas dan membuatnya merasa terus diawasi.
Dalam laporan ini, Ratih meminta identitasnya disamarkan. Dia–lagi-lagi–khawatir dengan keamanan dirinya. Di Indonesia, hidup sebagai seorang transgender akan berbahaya, menurut sebuah laporan tahun 2016.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo

Teror, Persekusi, Janji Politik
Suatu hari tahun 2013, telepon genggam Ratih berdering. Di layarnya berkali-kali muncul pesan singkat dan sejumlah panggilan telepon dari orang yang tak dia kenal.
“Di mana ki?” tulis pesan itu.
“Tinggal di mana?”
“Apa kau bikin?”
Selama sepekan, pesan-pesan serupa masuk. “Sms yang tidak biasanya,” menurut Ratih.
Teror pesan dan serangkaian panggilan telepon itu kata Ratih, bermula dari sebuah peristiwa pembubaran kegiatan komunitas minoritas gender dan seksual, di Kota Makassar, seminggu sebelumnya.
Kala itu, sekitar seratusan orang–laki-laki–menyerbu kegiatan itu. Mengancam para peserta dan penyelenggara. Mereka, sebut Ratih banyak berpakaian serba putih dan membawa senjata tajam.
Peserta yang hadir ketakutan. Kabur mencari tempat berlindung.
“Waktu itu juga saya langsung lari. Pusing. Sampai saya tiba di hotel, saya tidak sadar kayak menabrak pintu kaca hotel,” cerita Ratih.
“Untung tebal kacanya, jadi tidak pecah.”
Kegiatan itu terpaksa harus bubar. Tumpukan berkas dan uang kegiatan senilai Rp3 juta raib, termasuk sebuah diska lepas milik Ratih.
“Jadi dalam flashdisk itu ada data-data. Besoknya kita rencana mau upload,” katanya. “Waktu itu saya khawatir karena dalam file yang hilang itu, ada identitasku di dalam. Ada alamatku.”
Beberapa hari kemudian setelah pembubaran paksa, berkas itu ditemukan. “Tapi,” kata Ratih. “Uangnya hilang.”
Hari-hari berikutnya, hidup Ratih penuh cemas. Bagaimana jika tempat tinggalnya sudah disatroni?
Ratih tak tahu harus berbuat apa. “Saya hidup dalam ketakutan.”
Baca juga:
Politisasi Isu LGBT Menuju Tahun Politik di Media
Bagaimana Media di Makassar menjadi Mimbar Kebencian terhadap Keragaman Gender dan Seksual?
Aksi pembubaran itu rupanya tak berakhir. Pada 2017–empat tahun setelah peristiwa di Makassar, sebuah kegiatan tahunan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Kerukunan Waria – Bissu di Kabupaten Soppeng dibubarkan, bahkan sebelum acara itu sempat mulai.
Kegiatan itu menghadirkan ratusan transpuan dari berbagai daerah untuk berlomba dan beradu bakat seni. Ketika kegiatan itu akan dimulai dan para peserta telah berkumpul, polisi dan tentara datang. Melepas tembakan ke udara.
Peserta panik dan mencari-cari sumber ledakan. Mereka mengira, suara itu berasal dari sebuah bom.
“Tembakan itu sebagai bentuk peringatan bahwa acara itu harus dibubarkan,” kenang Ratih.
Seusai kejadian, Ratih mendengar kabar bahwa para penyelenggara Porseni bersama ketua dari salah satu organisasi transpuan di Sulsel, diajak bertemu oleh pejabat pemerintahan setempat. Sebuah pertemuan untuk berunding.
Ratih diberitahu bahwa Kepala Kepolisian, kejaksaan, pejabat Kesbangpol, Bupati dan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hadir dalam pertemuan itu. “Kayak negosiasi dan acara tidak bisa dilanjutkan,” kata Ratih.
“Disuruh bubarkan acara. Akhirnya bubar.”
Padahal, kata Ratih kegiatan itu telah mengantongi izin. Berkas-berkas yang diminta sebagai syarat telah lengkap dan mendapat izin dari Bupati.
“Jadi ada semacam lima berkas,” katanya, tetapi menurut pemerintah syarat terakhir tidak terpenuhi.
Dalam pertemuan itu, kata Ratih, seorang pejabat tinggi di Soppeng mengatakan, kegiatan yang telah bubar itu; “anggap sebagai jalan-jalan atau liburan.”
Dari pengalaman memilukan inilah yang bikin Ratih dan teman-temannya di komunitas, juga meminta timbal balik, jika mereka didatangi utusan partai politik yang meminta dukungan suara.
Janji-janji yang ditawarkan ke Ratih, harus disepakati dalam sebuah kontrak perjanjian. Ada hitam di atas kertas putih. Dia tidak ingin dibohongi.
Bagi Ratih permintaan itu masuk akal. Dia dan teman-temannya ingin keberadaan mereka dapat diterima. Mereka tak ingin lagi ada teror, diskriminasi, dan persekusi.
“Saya minta juga dong apa yang bisa kamu lakukan,” kata Ratih.
“Tapi kan dia tidak mau. Memberatkan kalau saya minta kayak kontrak perjanjian.”
“Untung di dia dong. Waktu itu akhirnya tidak jadi,” kata Ratih.
Di Sulawesi Selatan, Ratih bukan satu-satunya seorang transpuan yang kerap disambangi utusan partai.
Perkenalkan; Kiki seorang transpuan di sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan. Suatu hari pada 2018, dia dan kawan-kawannya disambangi oleh para calon legislatif (Caleg).
Di hadapan Kiki, Caleg itu menjanjikan kemudahan jika mereka mengadakan kegiatan–jika berhasil duduk di kursi dewan.
“Ayomi satukan suaramu, supaya saya bantu ko kalau ada kegiatanmu,” kata Caleg itu pada Kiki. “Tidak ada lagi pencekalan.”
Caleg yang mendatangi Kiki itu pun menang dan duduk di kursi dewan.
Namun, janji hanya tinggal janji. Suara Kiki dan kawan-kawannya sebagai kelompok minoritas gender dan seksual tak pernah didengar. Apalagi dikabulkan.
Dan tetap saja, kehidupan para transpuan seperti Kiki di daerah asalnya tak berubah. Tak pernah diterima baik di tengah masyarakat. Bila hendak mengadakan kegiatan pun, mereka tak akan diberi izin.
“Acara-acara 17-san saja kita di sini diperibet begitu. Contohnya misalnya gerak jalan di daerah– saya di perkotaanlah begitu–kayaknya selalu mendapat diskriminasi,” kata Kiki.
“Kalau misalnya belum mulai, baru diumumkan kita berpartisipasi ikut gerak jalan, pasti sudah banyak suara-suara sumbang dari oknum-oknum yang menentang kita ikut berpartisipasi merayakan HUT Kemerdekaan gerak jalan.”
Dalam laporan ini, Kiki meminta identitas dan asal daerahnya dirahasiakan, karena persoalan keamanan.
Menjadi Korban Politik
Ratih dan teman-temannya di komunitas akhirnya belajar banyak. Dari pengalaman tahun-tahun politik sebelumnya, mereka pun tahu bahwa para kontestan kerap memanfaatkan mereka demi kepentingan suara–meraup suara dari kantung minoritas.
Janji-janji mereka beragam.
“Melindungi. Membantu kalau ada kegiatan, mendukung pendanaan,” kata Ratih.
Tetapi di hadapan publik, mereka yang berkontestasi justru bersikap sebaliknya.
“Malah mengikuti psikologi massa [penentang kelompok minoritas gender dan seksual], supaya meraup suara banyak. Begitu,” kata Syamsurijal, Peneliti di Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Para kontestan kata Syamsurijal, melihat pemilih sebatas angka-angka yang dapat mengerek elektabilitas dan memenangkan mereka. Sementara kelompok minoritas gender dan seksual, tidak demikian.
“Kalau Anda [kelompok minoritas gender dan seksual] saya pedulikan,” kata Syamsurijal. “Justru berefek terhadap elektabilitas saya yang akan turun. Maka lebih baik justru Anda saya korbankan.”
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, isu kelompok minoritas gender dan seksual melambung tajam setelah Calon Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman–saat itu, menjawab pertanyaan dari Calon Wakil Gubernur Sulsel nomor urut 2, Tanribali Lamo, saat debat ketiga pemilihan calon Gubernur Sulsel di Studio Televisi Republik Indonesia atau TVRI Nasional di Jakarta, Rabu 9 Mei 2018 lalu.
Andi Sudirman diserang melalui pemberitaan setelahnya.
Tanribali Lamo bertanya kepada Andi Sudirman Sulaiman (ASS) calon wakil Gubernur Sulsel nomor urut 3: “Apa peran Pemprov [Pemerintah Provinsi] dalam ikut menangani tentang LGBT?”
“Kita harus ada perhatian khusus kepada mereka,” kata Andi Sudirman merespons pertanyaan itu.
“Mereka harus diberdayakan, mereka diberi kreativitas. Supaya mereka bisa hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang normal.”
Andi Sudirman melanjutkan. “Itu yang saya rasa penting bagi mereka. Kenapa? Kalau mereka semakin tersisih kemudian dibuat semakin menderita dengan perbedaan pelayanan kepada mereka, otomatis mereka akan semakin tersisih dan semakin terpinggirkan.”
Empat tahun setelah debat, Andi Sudirman Sulaiman pun didapuk sebagai Gubernur Sulsel menggantikan Nurdin Abdullah – yang terjerat kasus korupsi.
Pada 21 Agustus 2022, Andi Sudirman pernah meminta kampus bertindak tegas jika “terdapat indikasi kampanye LGBT”, buntut pengakuan seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin sebagai individu dengan gender non biner.
“Kalau pelaku menyebut diri Non-Biner dalam perkara orientasi seksual pribadi yang menyimpang, menyimpang baik secara pemahaman maupun perilaku maka pihak kampus harus bertindak hingga sanksi. Ini bisa menjadi kampanye LGBT,” kata Andi Sudirman dikutip dari Fajar.co.id.
“Pihak kampus untuk lawan dengan sanksi serta menetapkan kebijakan sehingga kejadian serupa tidak terjadi.”
22 Agustus 2022 Pemprov Sulsel mengeluarkan surat edaran memuat empat butir ketentuan untuk ‘pencegahan’ LGBT di lingkungan sekolah dan kampus. Surat Edaran Nomor 420/8434/Disdik itu diteken Abdul Hayat Gani – saat itu – Sekretaris Pemprov Sulsel.
Satu butir dari surat edaran itu meminta kepada institusi pendidikan: “Mengambil kebijakan untuk mencegah penyebarluasan paham pemikiran dan sikap perilaku yang mendukung LGBT di lingkungan kampus/sekolah dan mengambil tindakan yang tegas serta pembinaan yang tuntas termasuk pemberian sanksi terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam kegiatan maupun komunitas LGBT.”
Bollo.id sudah menemui Andi Sudirman Sulaiman di kediamannya yang terletak di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada 25 Januari 2024, untuk meminta tanggapan soal kelompok minoritas gender dan seksual. Namun Andi Sudirman tak ingin membahasnya.
Dalam pertemuan itu, Bollo.id juga telah menyampaikan tiga pertanyaan kepada Andi Sudirman Sulaiman tetapi dia tidak ingin membahasnya. Bollo.id telah menyampaikan surat permohonan wawancara, tetapi Andi Sudirman Sulaiman tetap menolak untuk diwawancara.

***
Di Kota Makassar, kehidupan individu kelompok minoritas gender dan seksual berada di persimpangan jalan.
Awal tahun 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anti LGBT. Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mendukung rancangan itu.
“Pasti saya dukung [Ranperda Anti LGBT di Makassar]. Jelas tidak ada aturannya, adakah aturannya diperbolehkan diakui LGBT? Tidak ada,” kata Danny–sapaan Mohammad Ramdhan Pomanto, kepada Bollo.id, 30 Januari 2024.
Pada Mei 2022, Danny pernah menyatakan bakal membubarkan acara Idahobit (Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia), yang sedianya bakal digelar di Kota Makassar melalui panggung seni.
Penolakan kegiatan itu rupanya berdampak pada Ratih.
Rumah Ratih disatroni orang tak dikenal, berulang-ulang. “Dalam sehari, bisa sampai empat orang yang datang,” katanya.
“Waktu itu saya ditempatkan di tempat yang aman, sembunyi.”
Setahun sebelum itu, Danny pernah berjanji akan memenuhi hak dan perlindungan kelompok minoritas di Kota Makassar, yang dituangkan dalam visi misi Danny bersama wakilnya–tanpa menyebut secara spesifik kelompok minoritas yang mana. Hal ini dilontarkan saat Danny menjadi narasumber di Festival HAM Apeksi tahun 2021.
Saat Bollo.id menemui Danny Pomanto, dia mengatakan: “Jadi kalau dia [kelainan] organ seksual, itu dari Tuhan. Tapi kalau dia, laki-laki sama laki-laki terus berperilaku seksual secara terbuka, no. Tidak ada tempatnya. [Jadi] jelas, ini bukan mendiskriminasi,” katanya.
“Belum ada undang-undangnya untuk diterima di Indonesia. Selama tidak ada aturan yang mengesahkan atau tidak. Ya, kita ikut aturan. Begitu saja.”
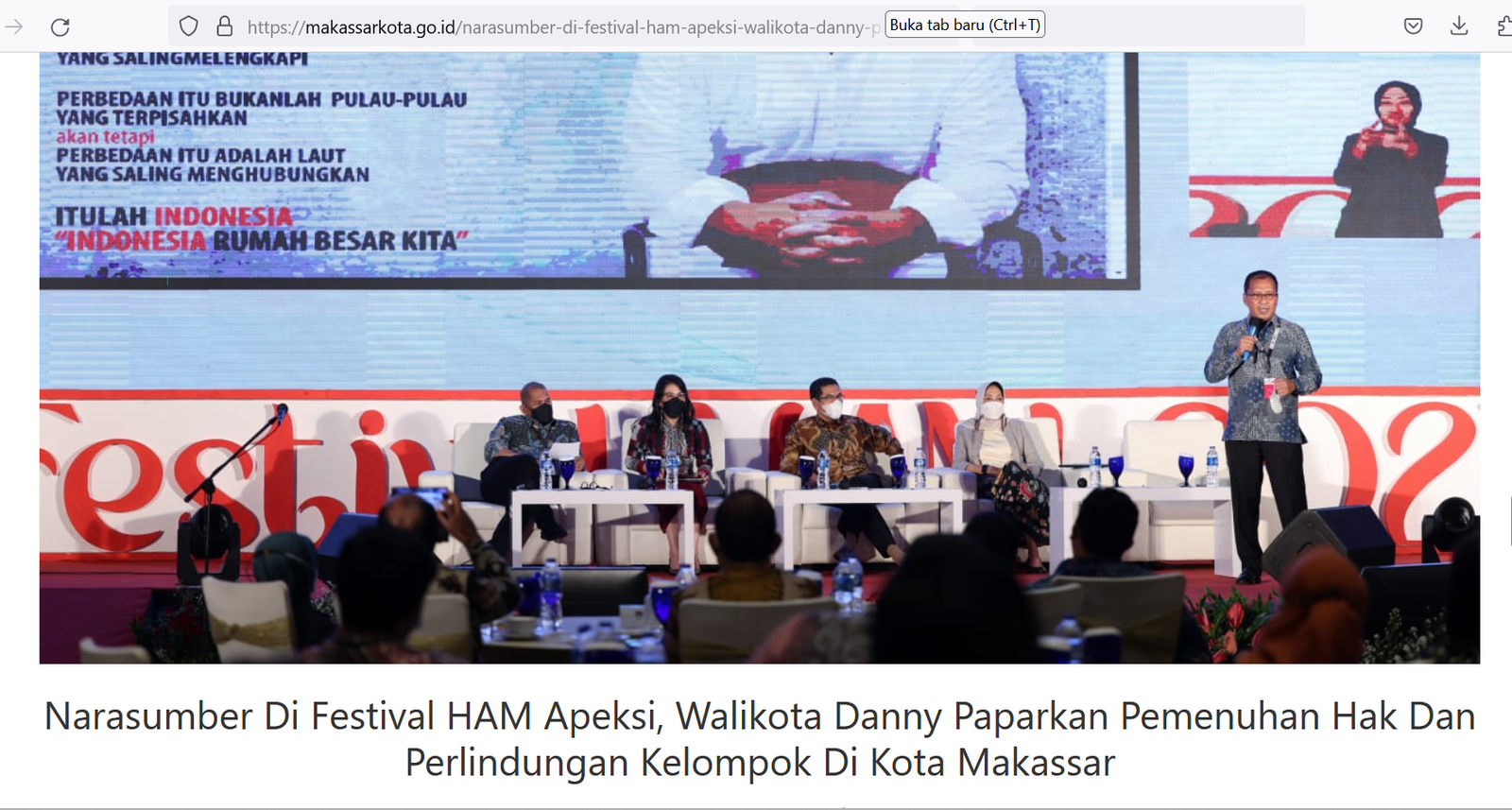
Topik Panas
Kedua narasumber transpuan dalam tulisan ini mengatakan isu kelompok LGBT, akronim yang disematkan untuk kelompok minoritas gender dan seksual di tahun-tahun politik akan menjadi topik panas.
Di momentum itu, kekerasan, sentimen, persekusi, hingga ujaran kebencian dari pejabat publik dan berita-berita negatif kerap menyasar mereka.
KSM mendokumentasikan kasus berbasis orientasi seksual, identitas, ekspresi gender, dan karakteristik seks (SOGIESC) di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2007 hingga 2019. Dalam rentang 12 tahun, terdapat 35 kasus.
Dari 35 kasus tersebut, kasus yang dialami kategori individu sebanyak 23 kasus. Sementara 12 kasus lagi, dialami oleh kelompok atau komunitas. Di tahun-tahun politik angka kasus mengalami kenaikan.
Dari 23 kasus individu, korban mencapai 33 orang, sementara korban dari kasus kategori komunitas atau kelompok LGBT mencapai 1.507 orang.
Kasus-kasus itu menurut catatan KSM, menyebar ke delapan wilayah di Sulawesi Selatan.
Kota Makassar tercatat dengan kasus tertinggi, mencapai 24 kasus. Disusul Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Bulukumba masing-masing 3 kasus. Sementara Toraja Utara, Soppeng, Luwu Timur, Gowa, dan Bone tercatat masing-masing 1 kasus.
Kasus ini, menurut catatan KSM semula hanya berpusat di Kota Makassar kemudian menyebar ke tujuh kabupaten lainnya di Sulsel.
Isu kelompok minoritas gender dan seksual menjadi isu yang paling gampang dimainkan politisi, menjelang Pemilihan Umum 2024, menurut hasil pemantauan tiga organisasi masyarakat sipil: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), dan Arus Pelangi.
Sering kali isu kelompok minoritas gender dan seksual dijadikan alat untuk meraup suara. Ratih bilang orang-orang partai memainkan isu ini dengan memancing kebencian masyarakat yang menolak bahwa ‘ini sesuatu yang tidak baik’ melalui pemberitaan.
“Isu ini dijadikan alat untuk mempersatukan, mendulang suara dari masyarakat yang sama-sama membenci,” kata Ratih.
“Menjadikan isu ini sebagai politik identitas. Itu yang menjadi wacana bersama dari orang-orang, khususnya yang menggunakan politik identitas.”
Peneliti di Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syamsurijal mengatakan pada panggung-panggung elektoral, kelompok minoritas gender dan seksual memang sering dijadikan korban untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Namun Syamsurijal, belum dapat memastikan apakah itu berasal dari strategi yang telah didesain sejak awal atau hanya semacam kebetulan yang bertepatan dengan tahun politik.
Mereka yang terlibat dalam kontestasi, menurut Syamsurijal kerap kali memainkan psikologi massa dari kelompok “agamawan” yang cenderung tidak dapat menerima keberadaan kelompok minoritas gender dan seksual, atau yang disebut Syamsurijal dengan istilah kelompok minoritas gender non-mainstream.
“Ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah representasi orang yang tidak senang dengan kelompok semacam ini,” kata Syamsurijal.
“Jadi seakan-akan ingin mengatakan kita sejalan dalam persoalan ini.”
Menurut Syamsurijal, para kontestan yang datang mendekati kelompok minoritas gender dan seksual tidak akan menggaungkannya di hadapan publik. Mereka yang maju di legislatif misalnya, hanya datang menunjukan bahwa mereka ‘memiliki kepedulian’, yang sebetulnya, kata Syamsurijal “sekedar ingin meraup suara.”
Para kontestan tak pernah sungguh-sungguh menyuarakan kelompok minoritas, menurut Syamsurijal. Buktinya kata Syamsurijal, masih banyak terjadi diskriminasi dan penyingkiran minoritas di Indonesia.
“Tidak ada yang melakukan itu karena dianggap bunuh diri secara politik karena justru akan berbalik ke dia,” katanya.
“Masyarakat mungkin tidak akan setuju dengan gagasan-gagasan itu.”
Dalam beberapa tahun terakhir ini, kata Syamsurijal, negara tidak memberikan perlindungan yang pasti terhadap kelompok minoritas gender dan seksual. Justru, kata Syamsurijal malah melahirkan aturan-aturan di tingkat pemerintahan daerah yang justru mendiskriminasi kelompok minoritas itu.
“Dengan perda-perda anti LGBT dan seterusnya,” katanya. “Pemerintah di beberapa tempat itu tidak memberi tempat atau tidak mengakui keberadaan kelompok ini.”
Senapas dengan Syamsurijal, Koordinator Divisi Hak Sipil dan Politik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Muhammad Ansar mengatakan bahwa negara tidak melindungi hak-hak kelompok minoritas gender dan seksual “sebagai manusia yang berhak berekspresi.”
“Selama ini kelompok minoritas gender dan seksual kerap didiskriminasi, mendapat perundungan, dibubarkan dan lain-lain,” kata Ansar.
“Sangat minim memang peran negara untuk memberikan perlindungan, utamanya terhadap kebebasan mereka.”
Berdasarkan catatan LBH Makassar, ada tiga kasus persekusi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender dan seksual yang mereka dampingi sepanjang lima tahun terakhir.
Pertama kasus pembubaran kegiatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2021. Kemudian, kasus pelarangan membawa pasangan di Kota Makassar tahun 2022. Dan kasus persekusi mahasiswa hukum Universitas Hasanuddin karena mengaku sebagai individu dengan gender non biner, pada tahun 2022.
LBH Makassar, kata Ansar, melihat isu kelompok minoritas kerap dimainkan ketika menjelang Pemilu karena dianggap sebagai ‘komoditas’ yang dapat mendongkrak elektabilitas.
“Secara hak asasi manusia,” kata Ansar. “Itu tidak boleh dilakukan.”
Situasi Hak Asasi Manusia kelompok minoritas gender dan seksual di Indonesia telah disorot banyak negara, pada Universal Periodic Review (UPR) yang diselenggarakan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada akhir 2022.
Setidaknya ada 13 rekomendasi yang diterima oleh Indonesia berkaitan dengan kelompok minoritas gender dan seksual. Menurut Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk UPR, Indonesia hanya mendukung delapan rekomendasi.
Melalui situs Dewan HAM PBB, rekomendasi berkaitan dengan kelompok LGBTIQ, Indonesia mencatat bahwa “tidak ada undang-undang, aturan, norma atau prinsip yang diterima secara internasional mengenai masalah khusus ini.”
Indonesia, dalam situs itu, berkomitmen terhadap “prinsip penegakan supremasi hukum, dan terus melindungi hak-hak dasar setiap orang.”
Tetapi, menurut Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk UPR, upaya Indonesia tidak sejalan dengan “kenyataan sehari-hari yang terjadi di lapangan.”
Tindakan diskriminasi terhadap orang-orang LGBTIQ, menurut koalisi semakin meningkat dan kian terstruktur. Contohnya ialah, tidak satupun organisasi LGBTIQ di Indonesia dapat mendaftarkan organisasi secara resmi apabila terdapat kata lesbian, gay, biseksual, transgender, waria di dalam dokumen konstitusi organisasi.
Di sisi lain, maraknya peraturan daerah yang bagi koalisi diskriminatif terhadap kelompok LGBTIQ juga menjadi trend, terutama pasca disahkannya KUHP baru.
Diskriminasi struktural melalui perda, menurut koalisi juga ditujukan kepada perempuan dan transpuan, yang menurut data Komnas Perempuan dilembagakan melalui 421 regulasi diskriminatif pada tingkat lokal.

Perundungan
2018 lalu, di hari pemungutan suara, Kiki sudah bersiap sejak pagi.
Sekitar pukul 10.00 Kiki berangkat ke Tempat Pemungutan Suara. Kiki sengaja berangkat pagi supaya proses pemilihan cepat selesai. Tetapi rupanya tidak.
Kiki tertahan. Kertas panggilan suara yang disetornya lebih awal ke panitia, diselip paling bawah. Orang lain yang datang belakangan lebih didahulukan masuk ke bilik suara.
Di tempat itu, Kiki menjadi bulan-bulanan warga dan petugas.
“Bencong!” teriak seorang di tempat itu ke Kiki.
“Tidak naik lagi partai!”
“Ada Syahrini!”
Sebagian orang lagi, kata Kiki “Ada yang nyolek-nyolek begitu, teriak-teriak ‘ih calledana.’”
“Saya tidak nyaman, apalagi di situ [TPS] banyak orang-orang yang tidak saya kenal juga.”
Lebih dari itu, Kiki khawatir jika kontestan yang terpilih adalah mereka yang tidak berpihak terhadap kelompok minoritas gender dan seksual. “Dan akan menekan komunitas LGBT.”
Saat kami berbincang melalui panggilan telepon, Kiki mengatakan pada saya, bahwa dia tak lagi percaya dengan bujuk rayu kontestan yang datang kepadanya.
Ketika kami berbincang, kampanye politik sedang bergulir. Jika utusan kontestan datang meminta dukungan suara, Kiki akan bersikap dingin. “Selalu itu [perlindungan] yang dia janjikan, namun realisasinya yang terjadi tidak seperti itu,” kata Kiki di ujung telepon.
“Bukannya saya tidak mau, tapi tidak ada bukti konkrit bahwa ada yang membantu kita setelah mereka ‘duduk’.”
Selain hanya jadi objek meraup suara, kata Kiki, perlakuan diskriminasi yang mereka terima tak berkurang. “Makanya kita beserta teman-teman yang lain ogah,” seloroh Kiki.
***
Pemerhati Budaya, Halilintar Lathief mengatakan kelompok minoritas gender dan seksual sering kali didekati oleh kontestan karena populer dan punya massa banyak.
Perkataan Halilintar itu beralasan. Kelompok minoritas kerap terlibat dalam acara hajatan masyarakat sebagai indo’ botting dan dari situlah mereka meraih popularitas dan disenangi orang banyak. (Indo’ botting adalah perias pengantin dan dekor pernikahan)
“Cuma mereka tidak sadari hubungan-hubungan sosial itu. Kayak itu Bissu Tomatoa, tidak ada yang tidak kenal,” kata Halilintar.
“Jadi dari pada [politisi gunakan] baliho, [mending politisi gunakan kelompok LGBT], sebagai baliho yang berjalan.”
“Hidup akan seperti ini-ini saja”
Ratih kini sudah jemu dengan politik elektoral. Teman-teman Ratih di komunitas sudah enggan diajak oleh kontestan yang ingin melenggang ke kursi kekuasaan.
“Teman-teman sudah pintar,” kata Ratih. “Karena kita mau dijadikan alat raup suara saja.”
Beberapa di antaranya bahkan pernah mengatakan kepada Ratih, bahwa hidupnya tak akan berubah dan ‘akan seperti ini-ini saja’, kendatipun mereka menggunakan hak suaranya pada Pemilu.
“Ada beberapa yang mencoba mempengaruhi teman-temannya. Kita nanti golput aja,” kata Ratih.
Ketika saya menemui Ratih, rangkaian proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 telah bergulir. Empat hari mendatang, para pasangan calon akan berdebat tentang keamanan.
Di tahun-tahun tanpa pemilu sekalipun, isu kelompok minoritas gender dan seksual acapkali digunakan untuk menebar ujaran kebencian dan membuat keamanan individu kelompok minoritas gender dan seksual menjadi rentan.
Mereka dituduh tanpa dasar, bahwa mereka penyebab tsunami dan berbagai bencana, penular HIV, pendosa, hingga merusak moral.
Stigma ini membuat hati Ratih remuk.
Riak-riak Pilpres tak lama lagi akan usai dan beberapa bulan kemudian pemilu akan berlangsung di Sulsel: Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota.
Ratih mulai khawatir dan ketakutan. Dia membayangkan pemilu-pemilu sebelumnya yang penuh dengan kebencian. “Kalau musim begini meningkat itu ujaran kebencian. Tentunya berdampak kepada teman-teman,” kata Ratih.
“Dan ditakutkan akan meningkatkan kekerasan di ruang-ruang publik.”
Ratih mengangkat tangan dan melindungi wajahnya. “Kayak di beberapa wilayah kan sudah ada. Di UGM dan Sumatra, itu sudah muncul kebijakan diskriminasi.”
Liputan ini Mendapatkan Dukungan Hibah dari Program Fellowship AJI Indonesia
Foto sampul: Generate by AI, Adobe Firefly
Penulis: Muh. Aidil
Editor: Agus Mawan W
Penata ruang: Agus Mawan W