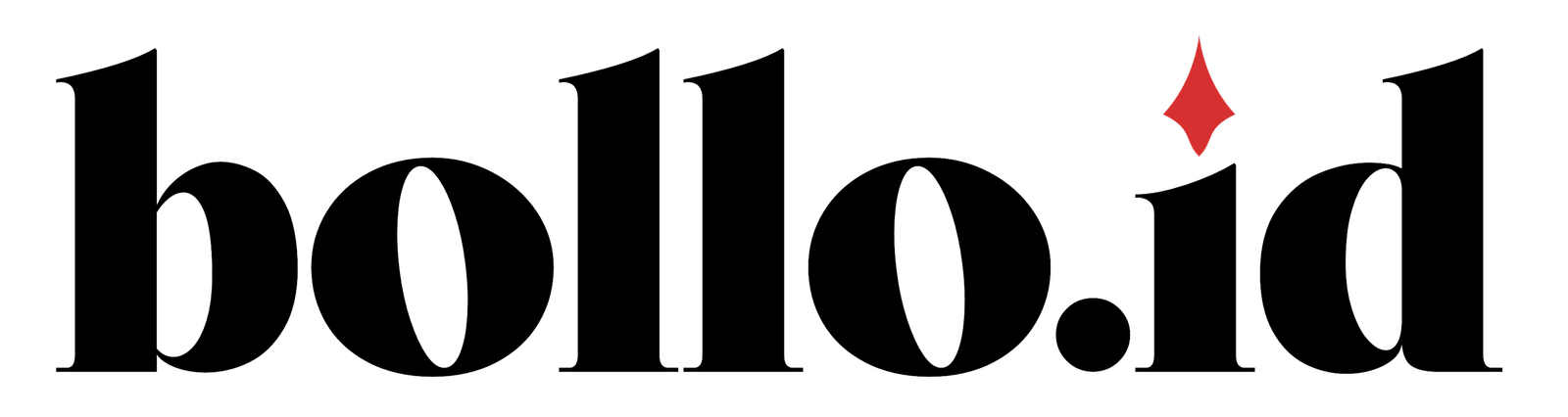Siam Sia berusia lima tahun ketika tiba di Kampung Kajang, di sebuah daerah pinggiran Kota Makassar bernama Antang. Kampung ini bagian Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala.
Selain sawah dan rawa-rawa yang menghampar jauh, hanya ada delapan rumah kayu panggung yang menjulang di antara pematang sawah. Di salah satu rumah itulah, Sia—begitu sapaannya, tinggal. Bersama saudara tertuanya bernama Sannai, si empunya rumah.
Sia seorang perempuan yang lugas, anak keempat dari enam bersaudara, lahir di Batunilamung, sebuah desa dataran rendah di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
“Saya dulu ke sini itu diajak sama kakak,” kata Sia pada saya. “Di sini saya akhirnya bisa sekolah.”
Kami berjumpa pada Januari 2024. Sia kini berusia 26 tahun dengan menyandang gelar sarjana ekonomi, lulusan Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar. Sia sedang mengandung anak pertamanya.
Usai menikah, Sia pindah ke rumah Ramsi, salah satu kakaknya yang belakangan juga menyusul ke Kampung Kajang, bekerja sebagai sopir truk sampah. Tak lama setelah Sia menikah, Ramsi meninggalkan kampung itu, bekerja sebagai pakkampas dan Sia membeli rumah permanen miliknya, lengkap dengan perabot.
Sia dan saudaranya meninggalkan Batunilamung demi mengubah arah nasib. Di kampung, kata Sia, hasil kebun tak lagi mampu menopang hidup. “Cuaca tidak menentu, sering kekeringan. Apalagi seperti tahun lalu itu misalnya, kemarau panjang (El Nino 2023).”
“Dari pada habis-habis uang saja,” kata Sia. “Mending saya di sini, cari uang sambil sekolah.”
***
Kota Makassar seperti magnet. Pusaran ekonomi yang berusia ratusan tahun telah merayu orang-orang dari pelosok Sulawesi Selatan, mengadu nasib di kota ini. Setidaknya Kota Makassar telah jadi muara gelombang perantauan sejak era kolonial.
Tahun-tahun kemudian, Makassar berubah jadi kota metropolitan. Penuh keriuhan dengan setiap sudut memunculkan kantong-kantong ekonomi. Menjadi tumpuan mimpi bagi perantau yang berniat mengadu nasib.
Jelang Tahun 2000, banyak Orang Kajang merantau ke Kota Makassar, sebagai kuli bangunan dan bekerja sebagai awak truk sampah. Mereka yang di Makassar mengajak sanak keluarganya datang dan mencoba peruntungan bersama. Di Makassar, mereka menjalin keakraban dan menempati satu wilayah dan membentuk semacam ‘perkampungan.’
Perkampungan mereka banyak bersebaran di pinggiran kota, tempat di mana harga kontrakan rumah jauh lebih murah dan tak menguras separuh upah mereka. Di Makassar mereka membawa tradisi, budaya, dan beberapa butir aturan adat yang berlaku di Kajang.
Seperti nikahan, kematian, hingga maddinging-dinging, ritual untuk memberkati rumah. Rumah-rumah di Kampung Kajang terdapat sebuah gambar garis-garis berbentuk anatomi tubuh manusia, atau tau-tau, menandakan rumah itu telah diberkati.

Tahun 1995, dua tahun setelah kompleks Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang beroperasi, tiga orang Kajang, Maro, Malang, dan Ambo, menemukan sebuah lokasi, di seberang titik penampungan terbuka TPA, tempat di mana sampah-sampah milik warga Makassar bermuara dan ‘membentuk pegunungan.’
Tiga orang itu membeli masing-masing sebidang tanah dan segera mendirikan rumah panggung di atasnya. Di sini, mereka memulai hidup sebagai buruh tenaga angkut sampah. Menjadi awak bantu di setiap armada truk sampah. Mengikuti ke mana pun truk itu berlabuh dan mengangkut sampah dari halaman rumah warga ke dalam bak truk.
Tahun-tahun berikutnya, lusinan perantau Kajang mengikuti jejak tiga orang itu. Membeli sebidang tanah. Membangun rumah. Dan bekerja sebagai buruh tenaga angkut sampah. Perkampungan itu pun ramai dan berdenyut sepanjang hari.
Di kampung ini mereka bertutur memakai Bahasa Konjo, salah satu sub Bahasa Austronesia yang menyebar di bagian selatan Sulawesi.
Kala itu mereka diupah Rp200 ribu untuk satu bulan dan terkadang upah itu tersendat. Jadi, para anggota keluarga perempuan harus bekerja sebagai pemulung. Memilah sampah yang bernilai uang, seperti plastik, elektronik, atau kardus. Hasil itu mereka pakai menutupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak mereka.
Baca laporan mendalam lainnya:
Kala itu, warga harus berdamai dengan keadaan. Rumah-rumah mereka masih berdiri di atas rawa dengan akses keluar masuk kampung hanya melalui pematang sawah. Ketika banjir, mereka memakai rakit bambu atau gabus-gabus besar yang mereka dapat dari gunungan sampah, di TPA. Tahun 1998 banjir menenggelamkan kampung itu, dengan kedalaman dua meter.
Tahun 2001, Sia tiba di kampung ini. Jalan keluar masuk kampung telah ada. Seorang warga bernama Usman bercerita pada saya, bagaimana mereka membuat jalan dan bersiasat agar kampung ini tidak lagi tenggelam ketika musim hujan.
“Mungkin kamu rasa, ini tanah goyang kalau truk lewat,” kata Usman. “Kamu tahu kenapa?”
“Ini semua dataran di sini itu hasil timbunan. Dan timbunan paling pertama itu sampah. Kita ambil dari TPA kemudian diratakan. Habis sampah, baru kami taruh batu dan di atasnya lagi itu baru tanah timbunan.”
Saya bertanya. “Berapa tingginya ini timbunan?”
“Dua meter!”
“Siapa yang menimbun? Pemerintah?” saya bertanya.
“Kami di sini yang patung-patungan. Dulu itu jalan hanya bisa dilewati becak. Sekarang sudah bisa dilalui truk. Karena kita perlebar jalan, berarti tanahnya orang harus kita beli. Jadi kita patungan lagi.”
Di tahun 2002, kampung ini telah dihuni 50-an keluarga, ketika Pemerintah Kota Makassar mengakui status perkampungan ini menjadi bagian Rukun Tetangga 4 di Kelurahan Tamangapa. Kampung ini semula tak bernama. Penduduk sekitar hanya menyebutnya sebagai Kampung Kajang, karena menjadi pemukiman bagi orang-orang yang berasal dari Kajang.
Tahun 2004, Pemerintah Kota Makassar meresmikan kampung itu dan menamainya “Kampung Kajang”. Saat itu, Pemerintah Kota Makassar membangun sebuah gapura di ambang kampung, yang hingga hari ini masih berdiri.
Di gapura itu tertulis: “SELAMAT DATANG DI KAMPUNG KAJANG”.
***
Pandang tiba di Kampung Kajang pada Tahun 2003, setelah bertahun-tahun jadi nelayan di Ambon. Pandang ‘tobat’ jadi nelayan, terutama karena dia bekerja di kapal pembom ikan. “Saya takut dipenjara,” katanya.
Pandang adalah seorang ayah tiga anak berusia 42 tahun. Di dagu laki-laki berkepala plontos itu ada sebuah tato garis hitam, yang dia tato saat menjadi nelayan.
Pandang berasal dari Lolisang, tetangga desa kelahiran Sia yang menghampar hingga pesisir Bulukumba.
Di Lolisang, Pandang punya lahan satu hektare, yang dia tanami jagung, sebelum akhirnya jadi awak kapal. “Minta maaf ini, bukannya mau menghina,” kata Pandang mengangkat telunjuknya.
“Berkebun itu susah. Jagung, hasilnya tidak seberapa. Belum lagi banyak babi. Belum lagi kita beli pupuk. Racun rumput. Kadang cuaca tidak menentu. Susah!”
Di Tahun 2003, Pandang sudah punya dua anak. Hasil kebun miliknya tak cukup untuk menjamin dapurnya terus mengepul dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Dia tak mau, anak-anaknya buta huruf seperti dia. Dia pun merantau ke Kota Makassar, bekerja serabutan.
Hingga akhirnya, saudaranya mengajak Pandang bekerja sebagai awak pengangkut sampah, dengan upah Rp600 ribu untuk satu bulan. “Saya langsung terima. Saya tahu suatu saat saya bisa jadi sopir,” kata Pandang.
Pandang tertawa. “Ada kariernya toh?”
Jadi Pandang mulai bekerja dan pindah ke Kampung Kajang. Anak-anaknya pun bersekolah.
Bertahun-tahun Pandang jadi awak truk sampah dan sepuluh tahun terakhir, Pandang telah menjadi sopir, dengan upah Rp2,3 juta tiap bulan. Pandang menjadi sopir sejak truk sampah milik Pemerintah Kota Makassar tampak lusuh dan membosankan hingga sekarang. Truk-truk itu kini dominan bercat putih dan penuh jargon-jargon “Makassar Tidak Rantasa” hingga “Lihat Sampah Ambil.”
Di Kampung Kajang, jenis pekerjaan tidak jauh dari: sopir truk sampah atau awak truk sampah, atau memulung sampah. Yang sedikit berbeda jadi kuli bangunan.
Ketika berkunjung ke Kampung Kajang, saya menyaksikan lusinan truk sampah terparkir di ujung kampung, di depan rumah Pandang dan Sia. Truk-truk bermesin diesel dengan kapasitas mesin empat ribu cc.

Kampung Kajang dijejali perkampungan padat, blok demi blok. Sebetulnya kampung ini tak hanya dihuni Orang Kajang semata, tetapi juga rumah bagi perantau dari Malino, Sinjai, Bone, dan pelosok daerah lainnya.
Pemukiman Orang Kajang terpusat di satu blok terujung mendekati penampungan TPA. Dari sini saya harus mendongak untuk melihat pucuk dari gunungan sampah di TPA. Saking dekat dan tingginya. Di Google Maps, seseorang memberi titik pada tumpukan sampah itu dan memberikan sebuah nama; “Gunung Antang”.
Di Kampung Kajang, air bersih berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Sebelum PDAM tiba sekitar Tahun 2005, warga bergantung pada sumur bor. Sepuluh tahun lalu, kampung ini mulai dialiri listrik dari Perusahaan Listrik Negara.
Separuh jalan di Kampung Kajang masihlah jalan tanah. Ketika musim hujan jalan itu berubah jadi berlumpur, lengket, dan penuh kubangan air. Satu tahun lalu, Pemerintah Kota Makassar memperbaiki jalan sepanjang lorong yang jadi hunian Orang Kajang. Memasang paving block.
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo
Saat saya di Kampung Kajang, rumah-rumah telah dominan permanen, menghimpit rumah panggung yang terbuat dari kayu. Rumah panggung Pandang berada di persimpangan lorong. Berdinding papan dan beratap seng.
Siang itu, Pandang beristirahat. Dia baru saja pulang dari berkeliling kota menjemput sampah-sampah warga Makassar. “Sekarang kehidupan saya sudah nyaman,” katanya pada saya.
“Saya tidak perlu lagi pergi merantau. Anak-anak saya sudah saya sekolahkan. Saya sudah nyaman di sini.”
***
Di Kampung Kajang, orang-orang saling mengenal. Dan pada blok hunian Orang Kajang, mereka berasal dari satu rumpun sama. “Di sini tidak ada orang lain,” kata Usman.
“Pandang itu sepupu satu kali saya. Sia itu keponakan saya.”
Usman berasal dari Lolisang. Dia sebetulnya tak punya rencana untuk merantau ke Kota Makassar. Tahun 1998, Usman menikah dan segera dikaruniai seorang anak perempuan.
Di Lolisang, Usman punya kebun kecil yang dia tanami jagung, yang hasilnya tentu tak banyak. Usman ingin menambah lahan tapi di Lolisang permukiman menyempitkan lahan-lahan yang tersedia.
Jadi, Usman memutuskan merantau ke Malaysia, menjadi buruh panen kakao di salah satu perusahaan. Sepulang dari Malaysia, Usman kembali mengurus kebun miliknya sembari memakai sisa tabungannya.
Suatu hari di akhir Tahun 2003, Usman menerima undangan pernikahan dari adik Pandang, di Kampung Kajang. Dari Lolisang, Usman menuju Makassar buat menghadiri hajatan itu, bersama istri dan putrinya.
“Pas itu acara, Pandang ajak saya untuk kerja di sini,” Usman menunjuk rumah Pandang.
“Saya terima. Dan sejak itu saya tinggal di sini.”
Seperti Pandang, Usman mula-mula bekerja sebagai awak truk sampah, sebelum menjadi sopir dengan upah Rp2,3 juta, di bawah Upah Minimum Kota Makassar sebesar Rp 3.529.181.
Saya menemui Usman di depan rumah sepupunya, di samping sebuah tanah lapang tempat truk-truk sampah terparkir. Usman kini berusia 43 tahun. Dia kini punya sepasang anak. Anak pertamanya baru saja tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). “Dia mau kuliah. Tapi saya masih pikir-pikir,” kata Usman pada saya.
“Saya tidak tahu apakah saya bisa sanggup biayai.”
Ketika kami berbincang, Usman ditemani Sangkala, keponakannya. Sangkala berusia 44 tahun dan beranak tiga. Sangkala telah merantau di Makassar sejak 1995 dan menempati Kampung Kajang pada tahun 2004.
Sebelum di Kampung Kajang, Sangkala bekerja sebagai kuli bangunan, satu pekerjaan primadona perantau Kajang. “Orang Kajang itu senang jadi tukang bangunan,” katanya pada saya.
“Karena itu keahlian kita.”
Kini Sangkala bekerja sebagai sopir truk sampah. Tiga anaknya lahir di Kampung Kajang, menjadi generasi kedua pemukim kampung ini—sebagaimana anak-anak perantau Kajang yang lahir di Kampung Kajang.
Bertahun-tahun hidup di Makassar, Orang Kajang di kampung ini bertutur dengan tiga bahasa: Konjo, Makassar, dan Indonesia. Secara administrasi mereka terdaftar sebagai penduduk Kota Makassar. Penduduk di Kampung Kajang telah mencapai seribuan jiwa dan akan meningkat di tahun-tahun kemudian.
“Saya sebenarnya rindu juga dengan kampung,” kata Usman. Sangkala menganggukkan kepala.

***
Sia berkuliah pada tahun 2015 dan tamat enam tahun kemudian. Itu bukan karena malas. Sia tahu, berkuliah menuntut biaya banyak. Jadi dia bekerja serabutan sambil berkuliah. Pagi hingga sore berkuliah, dan malam untuk bekerja.
Tahun 2019, Sia bekerja di salah satu departemen store sebagai kasir, selama tiga tahun. Dan kemudian bekerja sebagai kasir di toko elektronik, sebelum akhirnya menikah pada Juli 2023.
“Sebelum saya hamil, saya sempat kerja di dekat sini. Jadi kasir di toko campuran. Tapi saya berhenti,” kata Sia.
Hari semakin terik, dengan angin sepoi-sepoi menyelinap masuk ke ruang tamu Sia. “Lihat ini sekarang cuaca,” kata Sia.
“Tambah panas. Bagaimana mau bertani? Kadang kita sangka sudah mau hujan ternyata tidak. Jadi itu kenapa banyak anak muda pergi merantau. Mereka ragu bertani.”
Bagi Sia, Kampung Kajang tempat para perantau menemukan kehidupan baru.
Di sini, perantau Kajang membangun persaudaraan yang kuat sembari membantu keluarga mereka yang tidak beruntung, di kampung asal. Kampung-kampung Kajang di Makassar, kata Sia seperti suaka bagi mereka–anak-anak muda yang tak lagi ingin bertani dengan berbagai alasan.
“Dan di sini kita bisa saling membantu.”