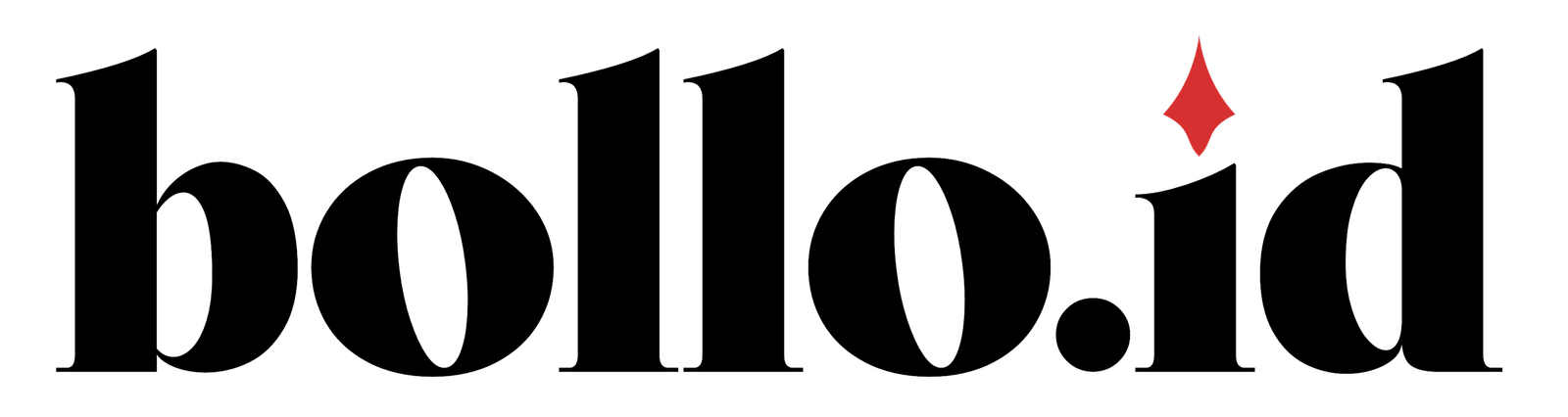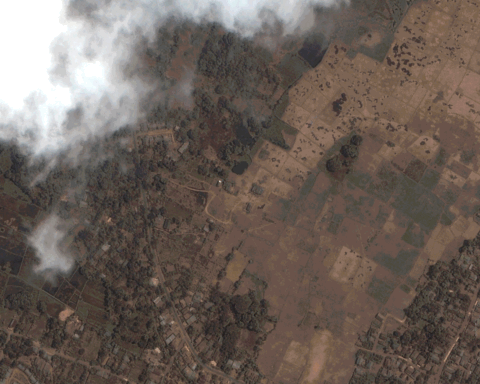Menjelang subuh, itu sebelum pukul 04.30, pada 3 Mei 2024. Banjir menghantam wilayah hilir, Kabupaten Luwu. Dua sungai masing-masing Suso dan Suli, membawa luapan air, bercampur lumpur yang pekat. Sebanyak 14 orang meninggal dunia, ribuan keluarga dan rumah terkena dampak, dari rusak ringan, hingga hanyut tersapu air.
Orang-orang terperangah. Mereka tak pernah menyaksikan sungai menjadi beringas. Warga tak sempat saling mengingatkan, sebab tak pernah mereka punya pengalaman banjir sebesar itu. Di Kampung Poringan, hulu Sungai Suli, luapan terjadi sekitar pukul 02.00. Setengah jam kemudian, banjir itu memporakporandakan rumah di sempadan.
Seorang bapak, menjadi panik. Air deras sudah menggenang setinggi satu meter di dalam rumahnya. Listrik sudah padam, gelap mencekam. Dia menaikkan anaknya ke plafon dan mengikatnya dengan sarung di tiang rumah, agar tak terjatuh, sebab dia yakin air tak akan mencapai atap.
Sementara dia menerobos air yang deras, dan mencari keluarga lain serta bantuan, rumah itu tiba-tiba roboh. Dia mendengar sekali suara anaknya, memanggil. Dunia serasa runtuh. Dia tak bisa kembali, lalu berenang dan dirinya menabrak pohon kakao di belakang rumahnya.
Suara air bagai gemuruh. Orang-orang meneriakkan nama keluarga untuk memastikan keselamatan.
Sementara itu, sekitar 8 kilometer di wilayah hilir, hujan mengguyur lebat dini hari itu. Banyak warga tertidur lelap. Di Kelurahan Suli, jelang pukul 03.00, air sungai telah meluap dan menggenangi jalan kampung. Meluber mengisi drainase dengan deras. Di Kampung Botta, sebuah keluarga yang jarak rumahnya dari batang sungai sekitar 300 meter, juga ikut tertidur lelap.
Risma yang punya anak dua, dan tinggal bersama bapaknya yang berusia 65 tahun. Pikirnya, banjir hanya akan menggenangi sawah di belakang rumah dan tidak akan memasuki rumah.
Tapi dini hari itu berbeda. Anak pertamanya, yang kebelet kencing, berdiri menuju toilet. Tapi alangkah terkejutnya, ketika kakinya telah menapak air yang deras. Dia teriak dan membuat penghuni rumah terbangun.
Air sudah setinggi betis dalam rumah. Risma terperanjat dengan panik. Kemudian menggendong anak keduanya, dan memegang anak pertamanya. Bersama bapaknya, dia membuka pintu dan air menerobos kian deras.
Di halaman rumah, keluarga itu dengan susah payah menerobos air yang sudah setinggi pinggang orang dewasa. Saat berhasil menapak jalan utama desa–yang lebih tinggi dari lantai rumah–mereka menghela nafas. Tapi dengan cepat, rumah mereka tersapu banjir.
Langit seperti runtuh, begitu Risma menggambarkannya. Dia mengusap wajahnya, “sesak sekali. Hanya bisa menangis,” katanya.
Dukung kami
Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.
Donasi melalui: bit.ly/donasibollo

Sebelum pukul 06.00 langit mulai benderang. Di Kampung Cimpu, banjir lebih besar, tinggi air mencapai 2 meter, yang terbawa dari Sungai Suso.
Sebuah keluarga, memilih naik ke atas plafon rumah. Bersama orang tua dan anak kecil. Mereka bertahan karena tak bisa menerobos banjir hingga jelang pukul 13.00 Wita. Mereka kedinginan dan kelaparan. “Saya tidak bisa membayangkan. Saya panik karena komunikasi terputus,” kata Rajib.
Rajib adalah anak dari keluarga itu. Saat ini bermukim di Ambon. “Saya tidak bisa gambarkan pikiran keluarga, ponakan dan orang tua waktu itu,” lanjutnya.
“Tapi, seperti kau tahu, banjir selesai. Kenapa semua menjadi hilang.”
Rajib sedang dongkol, tetapi itu bukan tanpa sebab. “Mereka (para pejabat pemerintah itu) bilang, harus saling menguatkan. Dan bantuan terus akan disalurkan,” kata seorang warga Suli.
“Itu memang gampang. Tapi kau suruh mereka ke hulu, siapa yang punya lahan paling luas di sana. Mereka pasti tahu, tapi tidak bisa buat apa-apa,” lanjut warga lainnya.
“Daumo jaka i, umba nasulei. Inang iyya iya to buntu jao, na taemo kajunna,” suara yang lain. (Kau tidak usah cari penyebabnya banjir, gunung sudah tidak ada kayunya. Itu pasti penyebabnya.)
Selamat datang banjir
Apa yang terjadi di hulu? Di bentangan pegunungan Latimojong itu? Saya bersama tim dari Perkumpulan Wallacea dan Huma, menulusuri batang Sungai Suli dan Suso.
Dari hilir menuju hulu, kami mengikuti jalan kampung yang meliuk mengikuti garis sempadannya. Aturan mengenai sempadan sungai yang selalu dimasukkan dalam pembahasan pembangunan kabupaten, benar saja hanya menjadi sekadar dokumen. Tak ada lagi kawasan penyangga. Sungai kini hanya menjadi sebatas air yang mengalir di antara tebing tanah.
Jika tebingnya terkikis dan runtuh, maka sungai hanya akan dianggap melebar. Ingatan kolektif warga, mengenai sungai yang ramah, hanya bermukim di kepala para penduduk yang usianya kini di atas 40 tahun.

Di Desa Poringan, Kecamatan Suli Barat, kami menghamparkan pandangan seluas jangkauan, dan mendapati semua telah berubah menjadi kebun. Sementara data Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Latimojong, menyebutkan jika Luwu memiliki luas kawasan hutan mencapai 103.580 hektare.
Tak heran, perubahaan fungsi dalam data pengamatan KPH Latimojong, setelah banjir menerjang, menemukan 545 titik longsor yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso. Dan sebanyak 1.141 titik longsor di DAS Suli.
“Itu juga yang menjadi soal sampai sekarang. Kami sudah melaporkan keadaan lapangan ke provinsi. Tapi belum ada tindak lanjut,” kata Rusdi Mustamin, Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Perlindungan Masyarakat, KPH Latimojong.
“Kenapa wilayah kelola warga tidak dikeluarkan dalam kawasan hutan?” saya bertanya.
Rusdi, menghembuskan nafasnya dengan berat. Baginya itu juga menjadi pertimbangan yang berat, sebab pelepasan kawasan, dapat memicu pembukaan lahan yang massif tanpa ada kontrol.
“Seharusnya masyarakat lah yang mengelola hutan mereka. Sebenarnya warga dengan sadar dan memahami betul, bagaimana memperlakukan hutan itu,” kata Guru Besar Kehutanan Universitas Hasanuddin, Muhammad Alif.
Ketidakpercayaan pemerintah, kata Alif, pada warganya sendiri, merupakan petaka yang terus menerus bertumbuh di wilayah tapak dan tak pernah ada upaya membuatnya menjadi lebih baik. Aturan dan tatakelola kehutanan di pemerintahan, sampai ke masyarakat menjadi sejumlah poin-poin larangan.
“Apa yang terjadi dengan banyaknya larangan itu? Warga menjadi subjek yang harus patuh. Padahal kawasan secara hutan dan sosialnya tidak terpisah,” kata Alif.
Gambaran itu lah yang kami temukan di lapangan. Sebelum perkebunan skala massif dikenalkan pendatang pertengahan tahun 2000, dari kampung-kampung tetangga, warga desa hidup dengan mengelola rotan. “Saya masih merasakan bagaimana mengambil rotan itu. Diangkut dari hutan, lalu dihanyutkan di sungai,” kata Suharman, Kepala Desa Poringan.
Baca juga:
- Nelangsa Banjir Luwu, 13 Orang Meninggal Dunia Hingga 16 Desa Terisolir
- 4 Kecamatan di Luwu Utara Terendam Banjir Berbulan-bulan karena Pemerintah Abai
Meski kemudian harga rotan berangsur tinggi, tapi membuka lahan dengan menanam kakao, kemudian nilam, selanjutnya cengkeh dan jagung, menjadi lebih mudah dan tak memerlukan banyak tenaga.
Akibatnya, hutan-hutan sekitar desa yang awalnya bertumbuh rotan, menjadi lenyap. “Dulu, kalau rotan tidak jauh ambilnya. Sekarang, sudah jauh sekali. Na taemo kora panggala,” lanjut Suharman. (Sekarang sudah hampir tidak ada hutan)
Suharman adalah generasi kedua yang lahir di Kampung Poringan. Kakeknya bermukim di kampung itu entah tahun berapa. Dia tahu, di belakang masjid desa–dekat kantor desa, ada sebuah batu yang dikeramatkan sebagai batu buat mengasah parang leluhur mereka. Tapi batu itu telah berpindah karena terjangan banjir.
Suharman, berusia 30 tahun. Dia ingat, awal tahun 2000-an, ketika dia masih Sekolah Dasar, kampungnya sungguh sejuk. “Kayaknya sebelum tahun 2019, ini kampung masih dingin sekali. Sekarang panas,” katanya.
Perubahan suhu kampung itu menjadi fakta berkurangnya tutupan hutan yang mengelilingi desa. Warga lain yang lebih tua mengenang, hingga pukul 08.00 Wita kampung masa lalu itu masih sangat dingin. Orang-orang yang berjalan masih mengenakan sarung untuk menyelimuti badan. “Sekarang, jam 06.00 Wita bisa lepas baju orang,” kata warga.
Tak hanya itu, suara beragam burung, hingga biota sungai, menjadi sulit lagi dijumpai. Mereka kemudian mengatakan pada kami, bahwa masa lalu, secara uang, warga kekurangan, tapi secara kehidupan, sehat dan nyaman.
Tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenalkan skema Perhutanan Sosial (PS). Saat kehutanan masih menjadi wilayah kerja Kabupaten Luwu, diusulkan lah kawasan hutan itu menjadi Hutan Desa. Penetapannya disetujui tahun 2020, dengan luas 1.790 hektare.
Akhirnya, kebun warga, masuk dalam program PS.
Suharman bilang, Hutan Desa ini menjadi harapan baru. Warga tampaknya memiliki alas hak kelola, meskipun dalam aturannya hanya bisa dilakukan selama 35 tahun, untuk tahap pertama. Tapi program PS ini dievaluasi setiap lima tahun, oleh Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan.
Bagaimana evaluasi itu? Suharman bilang, tak begitu mengetahui detailnya. Orang-orang provinsi dan kehutanan biasa datang ke desa. Mereka bertanya dan melakukan kunjungan ke kebun yang dekat. “Bagaimana jika evaluasinya tak memenuhi standar, dan skema ini dicabut?” kata kami.
Suharman, tak bisa menjawabnya.
Sementara itu, di Desa Lambanan, Kecamatan Latimojong, tim kami menemui Sainuddin, 51 tahun. Dia mengelola kebun seluas 2 hektare, dan menanam jagung. Lahan itu masuk dalam skema PS Hutan Desa, yang secara total memiliki luas 342 hektare.
Secara pengelolaan kepemilikan lahan yang digarapnya dilakukan secara turun temurun. Sainuddin bilang, ketika kelompok dibentuk dia tak mendapatkan pemberitahuan dan penjelasan. “Jadi kelompok itu ada, tanpa persetujuan kami, dan lahan langsung dimasukkan,” katanya.
Di Luwu, pembentukan kelompok dan penentuan anggota, dilakukan oleh segelintir orang. Amiluddin, 38 tahun, warga lainnya membenarkan. “Saya sudah berkebun bersama orang tua, baru kali ini ada yang muncul istilah HD (Hutan Desa), tujuannya apa masa’ tiba-tiba masuk ke dalam wilayah perkebunan masyarakat,” katanya.
Sementara di Hutan Desa di Desa Tibussan, kami juga menemui Muktar, yang menjadi Ketua kelompok. Dia orang yang ramah berusia 44 tahun.
Tetapi sebelum Muktar menjadi kelompok, dia tak pernah memahami apa itu PS. Bahkan, namanya masuk dalam kelompok pengelolaan pun tak pernah diketahuinya. “HD ini terbentuk tanpa sepengetahuan kami, karena nanti kami tahu kalau kami masuk dalam kepengurusan setelah pergantian pengurus dan nama kami dicatut dalam kepengurusan sebelumnya,” kata Muktar.
Bagi Muktar dan banyak warga lainnya, mereka tak punya pilihan selain menerima pencatutan nama dalam kelompok. “Jika tidak masuk dalam kelompok HD. Kami tidak bisa mengelola kebun sendiri, jadi mau tidak mau kita harus masuk di dalam kelompok,” lanjutnya.
Tibussan merupakan wilayah yang menjadi tangkapan air Sungai Suso. Dan program PS ini dikenalkan sebuah lembaga pendampingan yang bekerjasama dengan perusahaan yang juga berafiliasi dengan pertambangan emas PT Masmindo Dwi Area dan Dinas Lingkungan Hidup Luwu.
Warga kemudian tak punya pilihan. Maka Muktar, dan beberapa warga lainnya menerima skema program tersebut.
Secara nasional, program Hutan Desa dilaksanakan tahun 2007, melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penataan Hutan Desa. Tujuannya memberikan akses dan pengelolaan hutan kepada masyarakat desa agar dapat digunakan secara berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.
Bentang alam yang menakjubkan di Latimojong ini, menjadi bagian penting dalam fungsi hutan dan menjadi penyangga utama dalam daya dukung lingkungan. Tapi, dokumen Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengarsir kawasan itu sebagai salah satu wilayah dengan risiko tinggi terpapar bencana.
Ironisnya, wilayah yang ditetapkan dalam zona risiko tinggi bencana, menjadi bagian dari konsesi perusahaan penambang emas PT. Masmindo Dwi Area, seluas 14.470,078 hektare. “Kita ada dalam wilayah dengan risiko bencana tinggi. Tapi kawasan hutan kita sudah berubah fungsi,” kata Hasrul, Kepala KPH Latimojong.
Hasrul bilang, pembukaan hutan menjadi kebun, sudah dimulai sebelum KPH terbentuk tahun 2017. “Jadi ketika melihat skema PS ini di lapangan, KPH tak bisa berbuat banyak. Menghentikan aktivitas akan menimbulkan konflik baru. Padahal warga dibebani pajak,” katanya.
“KPH bahkan menemukan, bahwa tanah dalam kawasan hutan, memiliki sertifikat hak milik.”
Bahkan di kawasan PS di Desa Mappatajang, yang juga merupakan kawasan hutan, telah berdiri rumah peristirahatan yang dimiliki oleh keluarga Basmin Mattayang (Bupati Luwu, periode 2019-2024).
Oleh masyarakat bangunan itu dikenal dengan sebutan villa. Tempatnya berada di puncak bukit dan dikelilingi pagar.
Inilah yang dikatakan, Muhammad Alif, praktik yang melupakan masyarakat. “Sosialnya hampir tak ada. Sosialnya, ya orang-orangnya di dalam kawasan, itu yang dilupakan,” katanya.
Bagi Alif, skema perhutanan sosial yang bijak itu seharusnya diberikan pada masyarakat sendiri. Secara turun temurun, warga lebih mengetahui dan memahami kawasan yang mereka diami. “Sekarang, orang-orang dengan sistem yang ada memungkinkan orang lain masuk merambah wilayahnya, tanpa permisi,” lanjutnya.
“Akhirnya, warga ikutan. Daripada mereka menjadi penonton. Kalau seperti itu, apakah warga yang disalahkan?”
Di Indonesia, penetapan kawasan hutan dimulai sekitar tahun 1970-an. Penentuan itu dilakukan melalui citra satelit, di mana skalanya 1:500.000. Artinya, jika pemasangan patok itu dilakukan di titik yang masih jauh dari tapal batas seharusnya, tak akan terdeteksi melalui citra satelit. “Jadi tak heran, ada ratusan ribu desa tersedot masuk sebagai kawasan hutan. Ini kan yang tak pernah diperbaiki,” kata Alif.
Selanjutnya, dia juga mengingatkan, arti kawasan itu, adalah wilayah. Sementara membicarakan hutan seharusnya melihatnya dari fungsi. “Jadi apakah secara penetapan waktu itu–yang di dalamnya ada desa–masih dianggap sebagai fungsi hutan?”
“Ini kan yang sejak awal tak pernah jernih.”
Bagi Alif, konsep Perhutanan Sosial dalam dokumen itu seakan-akan sangat baik. Tetapi dalam praktiknya di lapangan, tidak. Di Kabupaten Wajo, melalui skema itu, puluhan ribu hektare lahan, pada ujungnya dikuasai hanya oleh tiga orang bangsawan.
Temuan Alif itu, rupanya serupa dengan yang kami temukan di Desa Kaladi Darussalam di hulu Sungai Suli. Melalui nama Kelompok Tani Hutan Sepakat, yang ketuanya adalah Sukardi sekaligus Kepala Desa, mendapatkan hak kelola Hutan Kemasyarakatan (HKM Sepakat) seluas 2.405 hektare dengan jumlah anggota sebanyak 333 orang.
Jumlah, anggota tani itu bukan hanya berasal dari Kaladi, melainkan dari berbagai wilayah di sekitaran Luwu, yang didasarkan pada kepemilikan lahan. Sukardi bilang, itu untuk memudahkan dan memberikan jaminan pada petani dalam pengelolaan lahan mereka.
Bahkan dalam luasan HKM Sepakat, beberapa pejabat dan mantan perangkat kabupaten Daerah Luwu memiliki lahan. “Iya ada beberapa. Itu diberikan. Ya mereka menanam buah-buahan. Tidak luas juga, hanya 2 hektare,” kata Sukardi.
Tapi penyataan itu berbanding terbalik dari ungkapan warga lainnya. “Tidak mungkin. Itu ada puluhan hektare mereka punya,” kata salah seoang warga.
Masuknya beberapa mantan pejabat pemerintahan ke dalam Kawasan Hutan, menjadi salah satu daya tarik masyarakat ikutan membuka lahan. Mereka bilang, pejabat itu “memberikan perlindungan” secara tak langsung. “Itu warga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Karena ada pejabat juga yang buka lahan. Jadi kalau mau, hentikan mereka, baru warga juga berhenti,” kata beberapa warga.
“Masa mereka bisa, warga tidak bisa.”
Sementara itu, Sukardi, punya pandangan lain. Masuknya beberapa pejabat dalam lahan skema PS, akan memperbaiki banyak hal. Ada akses jalan yang mereka bangun atau mungkin bisa menjadi ‘penyambung lidah warga.’
Hal ini juga lah yang menjadi salah satu dasar, Sukardi ikut berkontestasi pada pemilihan dewan kabupaten Tahun 2024. Dia kemudian beruntung dan mendapatkan suara yang menjadikannya terpilih melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meskipun kata dia, harus mengeluarkan banyak uang untuk mengongkosi jalur politiknya.
Di teras rumahnya di Desa Kaladi Darussalam yang berhadapan langsung dengan Kantor Desa, dia bilang, jika percepatan pembangunan desa dan memaksimalkan program PS akan terus diperjuangkan. “PS di Kaladi ini sudah banyak yang datang melakukan penelitian. Ini menunjukkan kalau kami mengelolanya dengan baik,” katanya.
Saat memintanya menjelaskan, bagaimana skema PS yang dikelolanya, yang seharusnya mendukung fungsi hutan. Dia bilang, sejak dulu kawasan ini sudah menjadi kebun. Jadi PS seperti dokumen sah untuk tidak melarang warga berkebun dan beraktivitas. “Sampai kapan? Kita lihat ke depan,” lanjut Sukardi.
“Ada evaluasi dari dinas terkait. Kami sudah dievaluasi, dan tidak ada pencabutan. Artinya berjalan sesuai dengan kaidah.”
Namun, tim kami menemukan, untuk pembukaan lahan yang masuk dalam skema PS, pemilik yang masuk sebagai anggota kelompok akan mencari pekerja. Jika luas lahan 2 hektare, dan tak mampu membuat kebun, maka pemilik akan mempekerjakan seseorang yang selanjutnya ketika lahan berhasil, pekerja akan mendapatkan bagian seluas 1 hektare.
Muhammad Hasbi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, mengatakan jika evaluasi pada program PS berjalan dengan baik. “Evaluasi dari aspek percepatan target luasan, peningkatan kapasitas dan peningkatan ekonomi selalu dilakukan,” tulisnya dalam pesan.
Di Sulawesi Selatan, secara keseluruhan luasan kawasan hutan yang ditargetkan untuk menjadi bagian dari PS seluas 280.821 hektare. “Dan yang telah memiliki izin sekitar 200 ribu hektare lebih,” lanjutnya.
Sementara, khusus untuk wilayah Luwu, terdapat 28 izin pengelolaan PS yang terbit sejak tahun 2015 hingga 2019. Sebanyak 15 izin di kelola melalui skema Hutan Desa dengan luasan 8.088 hektare. Dan sebanyak 13 melalui skema Hutan Kemasyarakatan seluas 13.010 hektare. Jadi jumlah total pengelolaan PS itu mencapai 21.098 hektare.
Sistem pengelolaan PS yang seharusnya menjadi mata rantai ekonomi dan penguatan fungsi hutan, rupanya tak berjalan dengan baik. Kawasan hutan yang masuk dalam skema PS itu, sejak dulu telah dikelola warga sebagai lahan turun temurun.
Sementara itu, anggota kelompok yang menjadi pengelola PS juga menjadi sangat manipulatif dalam praktiknya di lapangan. Di Desa Kaladi Darussalam misalnya, beberapa anggotanya tidak bermukim di desa tersebut.
Bahkan KPH Latimojong menemukan, orang yang beralamat di Sumatera mengusulkan pengelolaan PS di Kecamatan Bastem. Temuan-temuan pelanggaran pengelolaan Kawasan PS, terjadi dihampir semua kelompok.

Rumitnya warga berhadapan dengan negara
Di Desa Salubua, KTH Salubua, mengelola lahan seluas 531 hektare. “Saya tidak tahu bagaimana program itu. Tiba-tiba kebun kami masuk jadi PS itu,” kata Marjuni, 52 tahun. “Itu tiba-tiba, orang tuliskan nama saya dalam kelompok. Padahal kebun saya ada sertifikatnya. Hak milik.”
“Kalau PS itu bagaimana kah selanjutnya?”
Marjuni, menatap kami dengan tajam. Baginya, orang kehutanan hanya datang jalan-jalan melarang. “Melarang bagaimana. Ini katanya hutan lindung. Terus itu hutannya di mana? Terus sertifikat kami katanya tidak sah,” Marjuni, geram.
Keluarga lainnya adalah La Dusi, juga mengalami hal yang sama. Seliweran kabar mengenai sertifikatnya yang palsu, akhirnya membawanya melakukan uji coba. “Saya bawa sertifikat itu ke Bank BRI untuk ambil kredit. Mereka terima, malah sekarang mereka menawarkannya untuk menambah kredit,” kata La Dusi.
“Yang mana yang tidak sah kalau begitu.”
Rusdi Mustamin, mengatakan jika PS di Luwu ini memang perlu untuk dievaluasi secara keseluruhan. “Saya tahu Salubua itu dilakukan tata batas sekitar tahun 1990-an. Di dalam kawasan itu, orang sudah beraktivitas. Jadi sudah ada kampung sejak dulu,” katanya.
“Di banyak tempat, kami mendapatkan banyak seperti itu. Ada SPPT hingga sertifikat. Mengusir warga keluar dari wilayahnya, akan menimbulkan konflik baru,” lanjutnya.
“Jadi, kalau mau jujur sebenarnya sudah tidak ada mi hutan dalam wilayah PS di Luwu ini. Jadi ini soal administratif kawasan saja.”
Baca: Banjir Lagi, Doa Bersama Lagi
Rusdi memandang kami yang keheranan. Dia kemudian bicara tentang fungsi hutan yang seharusnya menjadi bagian penting sebagai daya dukung lingkungan. “Mungkin tidak banyak yang harus dibicarakan. Fakta mengenai banjir kemarin dan membawa lumpur, itu menjadi penandanya,” katanya.
“Saya kira, wilayah kita (Luwu) secara fungsi hutan dalam kondisi tidak baik baik saja.”
Padahal, pada masa lalu sungai dianggap sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari, untuk minum dan kebutuhan sekunder lainnya, seperti mencuci dan juga untuk pembangkit listrik skala kecil menggunakan kincir.
Rian warga Kelurahan Suli, yang menjadi bagian hilir dari aliran Sungai Suli, menggeleng mendengarkan itu. “Kami sudah merasakan banjir besar itu sejak 2007. Puncaknya pada Mei 2024. Setiap tahun minimal dua kali sungai meluap,” katanya.
Dia bilang, bangunan rumahnya, yang dibangun dengan pondasi tinggi dan untuk menapaki teras, ada tujuh anak tangga. “Sekarang, anak tangga itu semua sudah terkubur dengan lumpur.”
“Jika keadaan terus seperti ini. Perlahan-lahan kami akan terkubur. Apakah itu yang diharapkan pemerintah?.”
Hasrul bilang, jika semua orang sepakat, juga didukung pemerintah daerah, kawasan hulu yang menjadi penyangga sungai, dikembalikan ke fungsinya, maka dibutuhkan minimal 20 tahun untuk dapat merasakan dampaknya.

Editor: Agus Mawan W